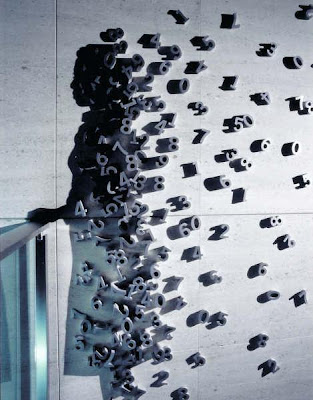ANTROPOLOGI SENI/SOSIOLOGI SENI
ANTROPOLOGI SENI
SENI PATUNG KONTEMPORER KARYA G.
SIDHARTA SERTA HUBUNGANNYA DENGAN KULTUR BUDAYA, GERAKAN REVITALISASI SERTA PENGKULTUSAN
KULTUR
Oleh :
SARIFUDIN, S.Pd
Kata Pengantar
Puji
syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas paper Antropologi seni Program
studi pendidikan seni rupa. Makalah ini disajikan menggunakan bahasa yang mudah
dipahami. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa atau pembaca dapat membuat hubungan
antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari..
Penyusun
telah berupaya semaksimal mungkin untuk berkarya dengan harapan makalah ini
dapat digunakan sebagai pegangan dan referensi dalam proses pembelajarannya,
khususnya untuk materi Antropologi seni. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih
dan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak dosen pembimbing mata
kuliah antropologi seni. Kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu
kami demi kesempurnaan makalah ini
Bab I
PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang
Perkembangan seni patung
di Indonesia yang tumbuh terutama di Bandung, Yogyakarta, Jakarta dan beberapa
kota lainnya, menunjukkan perkembangan yang berbeda dibandingkan dengan
pertumbuhan awal ditahun 1950-an. Pertumbuhan awal menunjukkan corak-corak representasional,
yang ditandai dengan munculnya kecenderungan patung figuratif seperti patung
potret diri atau sosok manusia tertentu yang dipatungkan. Lahirnya
gerakan-gerakan seni yang dilakukan para seniman muda tidak saja melabrak
kemapanan estetik, akan tetapi juga sikap dematerialisasi (pembebasan
material). Seni patung tidak lagi di pahami sebagai seni masif yang menggunakan
bahan khusus (kayu, batu, resin, bronze, dan lainnya) yang diletakkan di
atas sebuah base, akan tetapi muncul dengan sejumlah kecenderungan
estetika yang beraneka ragam.
Tanggal 5 Juni 1973
merupakan hari bersejarah bagi para pematung kontemporer Indonesia, karena pada
tanggal tersebut untuk pertamakali diadakan pameran patung modern Indonesia di
Taman Ismail Mazuki Jakarta. Hadirnya patung kontemporer sangat mengejutkan
publik, dikarenakan kurangnya informasi mereka tentang seni patung modern
dunia, khususnya Eropa dan Amerika. Ciri utama dari patung kontemporer ialah
bahasa bentuknya tidak lagi bersifat regional, akan tetapi universal. Referensi
sosialnya tidak ada sama sekali tetapi hal tersebut sudah didukung oleh
falsafah mereka masing-masing yang tidak bisa diterangkan secara obyektif untuk
semua orang. Karya-karya yang muncul bergerak kearah abstraksionisme ataupun
semi abstrak, deformatif, serta mengekploitir bentuk dan gerak.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian
a. pengertian patung
Patung adalah jenis
karya seni dalam wujud tiga dimensi. Dalam era industri dan teknologi yang
semakin canggih sekarang ini, karya-karya seni patung hadir dan ikut memberikan
interpretasinya atas dampak era tersebut. Para pematung tidak hanya sekedar mengekspresikan
manifestasi alam yang indah seperti apa adanya kedalam karya, akan tetapi juga
mengekspresikannya dari hasil simplifikasi alam dengan hanya menangkap hakikat
dari obyek, sehingga memunculkan karya-karya dalam wujud abstrak, dengan
berbagai ‘nilai-nilai’ yang diungkapkan lewat ‘tanda-tanda’
visualnya.
b. pengertian kontemporer
Contemporary
: kontemporer; masa kini, sewaktu, sejaman, waktu yang sama dengan
pengamat saat ini Art : seni; menurut Soedarso S.P. yaitu karya manusia
yang mengkomunikasikan pengalaman batinnya yang disajikan secara indah dan
menarik sehinggamerangsang timbulnya pengalaman batin pula pada manusia lain
yang menghayatinya. Kelahirannya tidak didorong oleh hasrat memenuhi kebutuh an
pokok, melainkan merupakan usaha untuk melengkapi dan menyempurnakan derajat
kemanusiaannya memenuhi kebutuhan yang bersifat spiritual.
Menurut Ki Hajar Dewantara P
yaitu seni merupakan bagian dari kebudayaan yang timbul dari hidup perasaan
manusia yang bersifat indah sehingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan manusia.
Seni itu pada dasarnya
kontekstual, sebab seni itu adalah persoalan nilai-nilai, dan nilai-nilai itu
selalu berhubungan dengan kenyataan konkrit. Sesuatu yang konkrit berada dalam
waktu dan tempat tertentu. Bagaimanapun dan apapun wujudnya, seorang seniman
tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai budaya masyarakatnya. Ia bisa tunduk,
loyal dan membenarkan nilai-nilai masyarakatnya, bisa pula mencoba memberikan
alternatif makna baru terhadap nilai-nilai masyarakat, atau sama sekali menolak
nilai-nilai masyarakat dan mengajukan nilai-nilai baru dalam karya nya.
Dalam seni modern, kreatifitas
merupakan hal yang sangat penting karena dari kreatifitas berkembanglah
sifat-sifat orijinalitas, kepribadian, kesegaran, dan sebagainya.
Seorang seniman biasanya merasa sulit untuk melepaskan diri dari ikatan sosial
yang ada disekitarnya. Oleh karena itu seorang seniman modern dengan sadar
berusaha membebaskan dirinya dari ikatan tersebut, dalam hubungannya dengan
tanggapan terhadap obyek Seorang seniman biasanya merasa sulit untuk melepaskan
diri dari ikatan sosial yang ada disekitarnya. Oleh karena itu seorang seniman
modern dengan sadar berusaha membebaskan dirinya dari ikatan tersebut, dalam
hubungannya dengan tanggapan terhadap obyek karyanya. aryanya. Sikap batin yang
tidak stereotip, yang selalu ingin akan yang baru dan yang lain dari pada yang
lain (sudah ada), merupakan ciri dari seniman modern.
Dalam karya seni rupa
modern, jumlah unsur informatif (denotatif) sengaja dikurangi dan dihadirkan
unsur-unsur visual yang mewakili nilai-nilai tertentu (konotatif). Unsur-unsur
visual yang digunakan (misalnya; warna yang tidak ikonografis, atau garis yang
tidak ikonografis) dan cara menyusunnya, mengharapkan keterlibatan pengamat
dalam melengkapi ‘pengertian’ terhadap tanda-tanda visual tersebut sesuai
dengan ground pribadinya. Dengan kata lain, karya seni modern ‘terbuka’
bagi interpretasi.
Sejumlah seniman
kontemporer (dari aliran seperti; Dada, Minimal Art, Op Art, Abstract,
Expressionisme) berupaya untuk membuat karya yang tidak diarahkan oleh
suatu ide atau maksud apriori. Mereka ingin menyajikan suatu peristiwa
visual (untuk dilihat) yang tidak mewakili ‘sesuatu’, tanpa referent. Pengamat
dibiarkan bebas dalam interpretasinya. ‘Meaning’ diberikan pada karya
oleh pengamat – posteriori, setelah karya selesai. Pengamat mencari-unsur-unsur
referensiil dalam memory dan jiwanya. Bila tanda-tanda visual yang dimanfaatkan
oleh si seniman adalah quali-sign, daya asosiatif pengamat dapat mengaitkan
sifat atau nilai yang dihadirkan oleh tanda-tanda visual yang bersifat Quali-Sign
(misalnya; nada warna tertentu, lengkungan garis tertentu) dengan nilai
yang pengamat kenal, yang penting baginya berdasarkan luas dan dalamnya ‘ground’.
Tentu saja cara menghayati karya seperti ini hanya mungkin dilakukan pada
karya-karya abstrak.
2.2. Tinjauan tentang
Seni Kontemporer
a. Karakteristik Seni
kontemporer
Sebetulnya
apakah itu seni rupa kontemporer? Bagaimana sebenarnya praktek seni rupa
kontemporer itu sendiri? Pertanyaan ini kerap dibicarakan sebagai bahan
diskusi. Pengertian arti dan prakteknya muncul beragam, barangkali karena
memang arti kontemporer itu sendiri yang mempunyai makna yang luas, bukan tidak
mungkin, siapa saja mempunyai tafsir yang berbeda tentang pengertian dan bentuk
praktek seni rupa kontemporer.
Berikut ini adalah
karakteristik dari seni rupa kontemporer, yaitu :
1. Adanya pluralism dalam
estetika, dalam prakteknya seniman
mendapatkan
kebebasan untuk berorientasi pada masa depan, masa lalu
ataupun
sekarang.
2. Berorientasi karya bebas,
tidak menghiraukan batasan-batasan kaku seni
rupa yang
dianggap baku.
3. penggunaan media atau
bahan apapun dalam berkarya seni
4. Berani menyentuh situasi
sosial, politik dan ekonomi masyarakat yang
sedang,
pernah ataupun mungkin akan terjadi.
Seni patung modern dapat
kita lihat pada karya-karya pematung terkenal di dunia, seperti; Auguste Rodin
(pelopor seni patung modern), Degas (pematung Impresionisti), Mattise, Picasso,
Henry Moore, atau yang berasal dari Indonesia, seperti; Rita Widagdo,
G.Sidartha, Arby Samah, Nyoman Nuarta dan banyak lagi pematung modern lainnya.
Cara memahami karya-karya mereka tentunya dengan cara penghayatan terhadap
tanda-tanda visual yang ada dalam karya dimana tanda yang digunakan mencakup
suatu representasi dan interpretasi, suatu denotatum dan suatu interprant.
b.
Semiotika
Kata semiotika berasal
dari kata Yunani semeion yang artinya tanda, jadi semiotika
berarti ilmu tanda. Semiotika adalah cabang ilmu yang berurusan dengan
pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti
sistem tanda dan proses yang berlaku bagi pengguna tanda. Semiotika kini adalah
bidang yang luas, dari zoo-semiotika, semiotika para-linguistik, semiotika
komunikasi visual, semiotika komunikasi massa, semiotika kode budaya dan banyak
lagi lainnya. Charles Sanders Peirce (1839-1914) adalah salah seorang filosof
Amerika yang paling orisinal dan multidimensional. Selain filsuf, Pierce adalah
seorang ahli logika. Menurut Pierce, tugas seorang ahli logika adalah memahami
bagaimana manusia bernalar. Sambil menyusun suatu teori mengenai bernalar,
Pierce sampai pada keyakinan bahwa manusia berpikir dalam tanda. Maka
demikianlah ia sampai menciptakan ilmu tanda. ‘Semiotika’, baginya, sinonim
dengan ‘logika’. Secara harfiah ia mengatakan: ‘kita hanya berfikir dalam
tanda’. Disamping itu ia juga melihat tanda sebagai unsur dalam komunikasi.
Bagi Pierce fungsi essensial sebuah tanda adalah membuat sesuatu menjadi
efisien, baik dalam komunikasi kita dengan orang lain maupun dalam pemikiran
dan pemahaman kita tentang dunia.
Karya seni rupa dalam
ragam perwujudannya tidak terlepas dari sistem penandaan atau semiotika. Tanda
dipakai oleh pengirim (sender) dan diterima oleh penerima (receiver),
dan si penerima memerlukan penafsiran terhadap tanda-tanda visual tersebut.
Sebuah tanda sebenarnya bukan “barang” atau benda, bukan ‘objek’ dalam
pengertian umum, melainkan suatu hubungan atau relasi.
c.
Tanda
Tokoh semiotika Peirce
(dalam Aart Van Zoest; 1930) membagi jenis tanda berdasarkan ground nya,
yaitu (1) Quali-sign, (2) Sin-sign dan (3) Legi-sign.
Quali-Sign adalah tanda yang
berdasarkan sifatnya, referent berdasarkan pengalaman seperti ‘merah’ yang berbeda
sifat dengan ‘hijau’.
Sin-sign adalah tanda-tanda yang
berdasarkan bentuk (rupa), tidak bisa begitu saja dihubungkan dengan sebuah
referent karena sin sign adalah super sign yang unik, inovatif, justru
menghadirkan referent baru yang belum diketahui sebelumnya.
Legi-sign adalah tanda
berdasarkan peraturan yang berlaku umum, suatu konvensi, atau kode. Suatu
peraturan, konvensi, dan kode berlaku umum, terbatas dalam suatu lingkungan
tertentu yaitu lingkungan kebudayaan. Referensinya adalah suatu aturan
tertentu, seperti repetisi.
Tanda melalui ciri-ciri
khasnya mengarahkan interpretasi pada content yang dimaksud. Qualisign Sin
sign Legi sign.
Inti pekerjaan sebagai
perancang (seniman, disainer, arsitek) yaitu menciptakan tanda-tanda visual,
tanda-tanda yang memvisualisasikan ‘sesuatu’ (ada referent = ide, maksud,
pesan). Jelas bahwa ide tersebut ada sebelum karya ada/apriori.
§ di seni murni : aneka
gagasan, angan-angan, perasaan yang jelas maupun yang tidak jelas, melalui
realisasi karya yang diformulasikan sehingga berbobot semantik.
§ di arsitektur :
unsur-unsur visual me-signifikasi masing-masing fungsi gedung, bersifat
informatif/denotatif, dan mengungkapkan hal-hal yang konotatif yaitu semantik.
§ di desain produk :
unsur-unsur visualisme-signifikasi sebuah fungsi, secara informatif/denotatif.
Desain hanya dapat dipakai bila tanda-tandanya dapat di dekodifisir, hanya
sekali-sekali, bentuk desain mengungkapkan hal yang di luar fungsi, yang
bersifat semantik. Tapi khusus desain grafis, tujuan desain adalah semantik,
namun jarang berbobot filosofis (contohnya ; kartu perkawinan)
d.
Tanda dalam Karya Seni
Penciptaan karya seni
terwujud dari hasil ungkapan bathin penciptanya. Ungkapan bathin ini tidaklah
datang begitu saja tanpa proses pengalaman artistik dalam diri si seniman.
Untuk mendapatkan pengalaman artistik tersebut dapat dipelajari melalui latihan-latihan
kepekaan jiwa dalam menangkap gejala-gejala alam, gejala-gejala yang tumbuh
dalam masyarakat lingkungan dan bermacam gejala fisik lainnya.Unsur-unsur
pembentuk pengalaman artistik antara lain bersifat estetis tetapi juga
non-estetis. Pengalaman artistik merupakan pengalaman yang kompleks dan oleh
seniman secara kreatif dapat dirangkum menjadi suatu hal yang berbentuk seni.
Para ahli Semiotik
mengatakan bahwa karya seni diciptakan ‘sebagai tanda’, lebih tepatnya, sebagai
‘Super-Sign’, untuk ‘menyebut sesuatu’. Sesuatu itu ada pada generasi
seniman dekade-dekade terakhir ini tidak terbatas pada pengalaman pribadi.
Upaya utama dalam seni abad ini adalah merujuk pada jenis ‘arti’ dan ‘makna’,
yang dapat ditangkap ataupun di rasakan, secara ‘inter-subjektif’, bersifat
‘supra-personal’, justru untuk mengatasi subjektivisme dan psikologisme yang
berlebihan. Dengan kata lain, hal-hal yang ingin disebutkan di Seni Rupa,
Arsitektur, apa yang mereka tampilkan / visualisasikan adalah ‘nilai-nilai’
yang penting bagi orang banyak, seakan-akan yang dicari adalah jenis ungkapan
bagi nilai/arti, makna yang objektif, sesuatu yang dianggap dapat mengikat
anggota-anggota dari suatu kolektif/komuniti tertentu. Sejauh mana seorang
seniman sanggup memikirkan masalah-masalah zamannya, itulah yang menentukan
keberhasilan karyanya sebagai bahan bacaan/’teks’ yang membawa nafas zaman,
sehingga dapat dimengerti.
Karya seni termasuk
dalam kategori tanda yang sengaja diciptakan sebagai tanda, dalam dua rubrik :
1. untuk merepresentasikan obyek-obyek nyata (seni
sebagai ikonografi, yaitu seni naturalistik, realistik).
2. untuk memvisualisir atau menstimulir
fungsi-fungsi mental tertentu (seni abstrak). Dalam hal ini ikonositas
mempunyai tingkat gradasi yang berbeda pada masing-masing aliran. Sebagai
contoh; sebuah lukisan abstrak atau patung abstrak adalah analog terhadap
karakteristik acuan yang dapat merupakan obyek nyata, atau ide abstrak, ataupun
suasana mental (yang juga nyata).
Seorang seniman
diharapkan menciptakan tanda-tanda visual-estetis yang dalam konsepsinya
kontemporer, yaitu berkaitan dengan problematik/pandangan yang aktuil di
komuniti. Seni mencatat ‘keyakinan’ maupun ‘kegelisahan’ yang dalam hal ini
kata interpretasi dan ruang interpretasi menjadi kata kunci.
e.
Seni Patung Modern
Dalam perkembangan seni
rupa modern, abstrakisme yang menjadi salah satu alur perkembangannya yang
utama, sebenarnya bermula pada patung-patung Pablo Picasso yang mengadaptasi
bentuk-bentuk patung primitif Afrika. Seni patung modern menurut Herberd Read
diawali oleh Auguste Rodin (1840-1971). Loncatan yang berarti terjadi pada
Picasso, terutama pada karya awalnya “Kepala Wanita” yang bercorak kubistis
dan juga pada Henry Matisse dengan karya-karyanya yang bercorak arabeska,
seperti dalam karya “Madeleine I” (1901). Sifat-sifat karya patung
mereka tersebut sudah jauh dari sekedar meniru alam (mimesis). Dalam
sejarah seni rupa modern, patung-patung Picasso yang memperlihatkan deformasi
sangat jauh ini dicatat mempengaruhi kubisme dalam perkembangan seni lukis yang
kemudian disebut-sebut sebagai tonggak penting perkembangan abstrakisme,
sedangkan seni patung yang berperan dalam melahirkan abstrakisme ini tidak
pernah disebut-sebat sebagai perintis.
Sederet nama pematung
modern (berawalnya dari Eropa), adalah Auguste Rodin, Pablo Picasso, Henry
Matisse, Paul Gauguin, Constantin Brancusi, Jean Arp, Naum Gabo dan Pevsner,
Henry Moore. Selanjutnya oleh tokoh-tokoh Kinetic Sculpture seperti;
Len Lye, Lin Emery, Ernest Trova, dan lainnya. Menurut Paul Klee karya-karya
mereka bukanlah sekedar perwujudan bentuk meniru alam atau segala fenomena yang
kasat mata, melainkan lebih banyak menghasilkan sesuatu dari dalam (dari dunia
subyek) menjadi tampak oleh orang lain. Karena yang terungkap adalah dunia subyektif
yang sering sukar terkontrol oleh pengalaman orang lain, maka tidaklah mustahil
terlalu banyak ‘selubung’ yang menghambat terjadinya komunikasi. Pada gerakan Constructivisme
yang dipelopori Naum Gabo dan sejumlah pematung lainnya, terdapat gejala yang
mencoba mengeksploitir bentuk dan gerak.
Dasawarsa 1970 merupakan
masa ‘pemberontakan’ dan ‘gerakan’ dalam seni rupa modern Indonesia, tak
terkecuali didalamnya usaha-usaha untuk mempersoalkan perkembangan seni patung.
Para seniman muncul dengan gejala baru dimana seniman memungut benda keseharian
dan benda temuan seperti benda-benda mainan, boneka, mobil-mobilan, sendal
bekas, kaleng, daun pisang, dan sebagainya, kemudian dimaklumat sebagai ‘benda
estetik’ dan sah untuk ditransformasikan sebagai seni.
2.3
Interpretasi Karya Seni Patung kontemporer
oleh G sidharta
G.Sidharta adalah
pematung modern yang dikenal memberontak pada paham modern dengan mewarnai
karya-karya patungnya (yang dianggap tidak setia terhadap watak bahan).
Sejumlah karyanya juga mengandung cerita yang dihindari oleh umumnya para
seniman modern. Kehadiran ornamen (pola-pola etnik) dan sapuan warna dalam
karya patungnya ternyata tidak saja memperkaya perkembangan, tetapi juga
melahirkan friksi-friksi tajam dalam wacana seni rupa. Karya-karya Sidharta
menyiratkan ‘nafas tradisi’ yang sangat kuat. Perjumpaan Sidharta dengan
modernisme – menimba ilmu di ASRI Yogyakarta dan Jan van Eyck Akademie voor
Beeldende Kunsten Maastricht, Nederland – tak menepis seni tradisi dalam karyanya.
Sebagian besar karya
Sidharta diungkapkan dengan menggunakan sistim penandaan yang bersifat
qualisign dan sebagian lagi dengan memanfaatkan sistem penandaan ikonogafi.
Dalam karyanya yang berjudul “Tumbuh Lima Duabelas Berkembang” (1986)
Sidharta tidak lagi terikat pada media dan rumus-rumus seni yang 
|
konvensional. Ia
berusaha mengungkapkan irama dalam ruang dengan gerak tegak secara legisign
berbentuk tiang dan mengaitkan diri dengan jalur kehidupan tradisi, 
|
yang berukuran 120 x 120
x 120 cm itu berupa semacam gelang raksasa yang tidak bertemu ujung dan
pangkalnya. Pada tubuh gelang menempel empat potongan gelang serupa yang saling
silang. Susunan bentuk mengingatkan orang pada paham yin-yang, yang
tanda-tandanya muncul pada ujung-ujung potongan gelang tersebut.
Disamping Sidharta
memanfaatkan tanda-tanda visual secara qualisign, ia juga banyak menghadirkan
sifat ikonografi atau bahkan gabungan dari kedua sifat tersebut dalam karya
patungnya. Misalnya patung yang bejudul “Keseimbangan dan Orientasi” (1996)
dan “Dewi Kebahagiaan III” (1999). Dalam pengolahan bentuk patung ini
bersifat ikonografi, walau tidak lagi hadir dalam wujud realis. Namun dalam
memanfaatkan warna tidak lagi ikonografi akan tetapi lebih bersifat qualisign.
2.4. Paradigma Perkembangan
Seni patung Kontemporer di Indonesia
Dalam seni
rupa Indonesia, istilah kontemporer muncul awal 70-an, ketika G. Sidharta
menggunakan istilah kontemporer untuk menamai pameran seni patung pada waktu
itu. Suwarno Wisetetromo, seorang pengamat seni rupa, berpendapat bahwa seni
rupa kontemporer pada konsep dasar adalah upaya pembebasan dari kontrak-kontrak
penilaian yang sudah baku atau mungkin dianggap usang. Pendapat lain dari
Yustiono, staf pengajar FSRD ITB, melihat bahwa seni rupa kontemporer di
Indonesia tidak lepas dari pecahnya isu postmodernisme (akhir 1993 dan awal
1994), dimana sepanjang tahun 1993 menyulut perdebatan dan perbincangan luas
baik di seminar-seminar maupun di media massa pada waktu itu. Sedangkan kaitan
seni kontemporer dan (seni) postmodern, menurut pandangan Yasraf Amior
Pilliang, pemerhati seni, pengertian seni kontemporer adalah seni yang dibuat
masa kini, jadi berkaitan dengan waktu, dengan catatan khusus bahwa seni
postmodern adalah seni yang mengumpulkan idiom-idiom baru. Lebih jelasnya
dikatakan bahwa tidak semua seni masa kini (kontemporer) itu bisa dikategorikan
sebagai seni postmodern, seni postmodern sendiri di satu sisi memberi
pengertian, memungut masa lalu tetapi di sisi lain juga melompat kedepan
(bersifat futuris). (sumber : www.sujud.tripod.com; A.Sudjud Darnanto
Personal Website)
2.5 Seniman G Sudharta, Kurator Dan
Hubungannya Dengan Sosial Ekonomi
W.S. Rendra melancarkan kritik pedas
waktu itu. G. Sidharta telah mendahului jamannya. Jadi sebenarnya G. Sidharta
Soegijo adalah pelopor pembaruan di Jogyakarta. Namun karena keadaan di
Jogyakarta itu waktu tidak kondusif maka ia terpaksa harus meninggalkan Jogya,
kota asalnya yang telah memberikan bekal yang sangat berarti bagi perjalanannya
sebagai seniman.
Ia dapat tawaran dari ITB dan
pindahlahlah Sidharta ke Bandung tahun 1965. Bersama But Muchtar dan Rita
Widagdo ia mendirikan jurusan patung di ITB. Sampai pensiun G. Sidharta tak
diangkat menjadi guru besar padahal beberapa rekan dari generasinya telah
menjadi profesor. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah karena ia bukan alumni
ITB namun alumni ASRI Jogya yang merupakan antagonis ITB pada awal sejarah
kedua akademi senirupa tersebut? Kita tahu bahwa di awal berdirinya Akademi
Gambar di Bandung dan ASRI Jogya ada ketegangan antara kedua institusi tsb.
Mereka saling mengritik. Sebab dipandang dari perjalanan akademisnya, keahliannya,
karya-karya seninya, jasanya dalam pendidikan ia pasti memenuhi syarat untuk
diangkat menjadi guru besar. Walaupun G. Sidharta sendiri tak pernah
mempermasalahkan hal ini.
Waktu Museum H. Widayat ingin
menganugerahkan H. Widayat Art Award saya diminta duduk dalam panitya seleksi.
G. Sidharta Soegiyo dipilih secara sebagai favorit untuk mendapat anugerah
tersebut karena perjalanan kesenimannya, kontribusinya terhadap dunia seni-rupa
Indonesia, dedikasinya sebagai pendidik dan keberhasilannya sebagai pemimpin.
Ia seniman senior yang dihormati oleh semua kelompok dalam dunia seni-rupa. Ia
pendiri ASPI (Asosiasi Pematung Indonesia) dan menjabat sebagai ketuanya sampai
achir hayatnya.
Saya beberapa kali duduk bersamanya
dalam penjurian lomba patung publik. Yang terachir adalah dalam tim seleksi
lomba patung yang diadakan P.T. Djarum untuk memilih lima patung yang akan
ditempatkan di lima penjuru kota Kudus untuk merepresentasikan Kudus sebagai
kota Kretek. G. Sidharta mengetuai tim. Ada kritik dari seniman-seniman yang
tak ikut diundang untuk lomba ini terutama seniman lokal dari Kudus dan
sekitarnya. Semua dihadapinya dengan rasional dan dijawab dengan argumen yang
jitu. Ia membuktikan diri sebagai pemimpin yang berani bertanggung jawab. Ia
berpengalaman dalam membuat patung publik maka tahu betul aspek-aspek yang
harus diperhatikan. Ia mengikut sertakan ahli bukan pematung seperti arsitek
kota karena untuk patung publik perlu adanya keserasian dengan lingkungan
dimana patung tersebut ditempatkan..
Keluarga Gregorius Sidharta adalah
keluarga Katolik yang baik, maka bila menyangkut patung-patung yang ada kaitan
dengan agama katolik seperti penyaliban Kristus, G. Sidharta tak ada
tandingannya. Ia sangat menghayati penyaliban Kristus. Sering Sang Penebus tak
dihadirkan secara kasat mata namun spiritNya bisa dirasakan. Maka ia sering
diminta membuat patung Salib Kristus untuk gereja-gereja Katolik dan patungnya
menarik perhatian karena berbeda dengan patung Salib konvensional yang
menghiasi gereja pada umumnya. Patung-patung Salib yang bisa dikoleksi oleh
kolektorpun mempunyai karakter yang sama dan kualitas yang seimbang dengan
patung Salib gereja.
Ia pernah mengeluh ketika pada suatu
waktu melihat karyanya akan dilelang oleh sebuah balai lelang nasional dalam
jumlah banyak. Ia mengannggap balai lelang tersebut tidak peduli akan
senimannya karena dengan demikian harga bisa jatuh, hal mana sangat merugikan
sang seniman. Ia mempunyai wawasan, perhatian dan kepedulian yang sangat luas.
Ternyata yang dikuatirkannya kemudian benar terjadi.
G. Sidhartalah yang pertama kali
menggunakan kata kontemporer dalam pameran pertama Patung Kontemporer Indonesia
di TIM Jakarta tahun 1973. Melihat kembali kiprah G. Sidharta, sebenarnya
dialah pelopor pembaruan seni-rupa Indonesia. Suatu ironi bahwa Jogya yang
sekarang berada di garda depan pembaruan seni-rupa Indonesia, itu waktu belum
bisa menerima Sidharta yang membawa pembaharuan dari Barat, sehingga ia harus
hijrah ke Bandung, walaupun achirnya ia pulang kandang setelah pensiun.
2.6 Gerakan Revitalisasi Dan
Integrasi Etnosentrisme Oleh G. Sidharta Dalam Menghidupkan Kembali Budaya
Asli melalui seni patung
G. Sidharta tidak berhenti dengan
apa yang ia dapat dari Barat, karena ia seorang yang dinamis dan kreatif, tak
pernah berhenti mencari hal-hal baru. Ia kemudian jenuh dengan modernisme yang
diperoleh dari Barat dan menggali kembali tradasi serta mengadopsinya namun
dengan penedekatan dan pengolahan baru. Ia beranggapan bahwa seni rupa modern
Indonesia harus menunjukkan ke Indonesiaannya di samping kemodernannya. Karena
orang tak pernah bisa mengingkari asal-usulnya. Maka muncullah patung-patungnya
dari kayu yang berbalut cat warna-warni yang mengandung elemen tradisi namun
modern. Karya grafisnya menunjukkan perubahan yang serupa.
Pada saat ini seniman-seniman muda
kita malah banyak yang meniru gaya luar negeri baik Barat maupun Timur terutama
Cina dan melupakan tradisinya sendiri. Seniman-seniman kontemporer seperti Heri
Dono, Nindityo Adipurnomo, Ivan Sagito, Nasirun, Putu Sutawijaya, Indiguerillas
yang masih mempertahankan identitas ke Indonesiaannya tidak banyak. Mayoritas
tidak memperlihatkan lagi identitas Indonesia. Dari 15 Oktober 2009 sampai 10
Januari 2010 di Centraal Museum Utrecht, Belanda, berlangsung pameran besar berjudul
“Beyond The Dutch”. Pameran ini menggambarkan perjalanan seni-rupa Indonesia
sejak Raden Saleh, “Mooi Indie”, Zaman Revolusi, Setelah Kemerdekaan sampai
Hari Ini. Pameran tersebut ingin mengatakan bahwa “Indonesia Hari Ini” sudah
melampaui Belanda, tidak ada pengaruh Belanda sama sekali. G. Sidharta yang
pernah belajar di Belanda tahun 50an sebenarnya sudah “Beyond The Dutch”.
G. Sidharta Soegijo tidak pernah
“pensiun”. Setelah pensiun dan kembali ke Jogya ia malah tambah aktif memajukan
dunia patung Indonesia. Ia mendirikan Asosiasi Pematung Indonesia (API) dan
menjadi ketuanya sampai achir hayatnya. Ia tetap mematung pula dan ketika sudah
sakit masih sanggup berpameran tunggal. Saya beruntung diminta G. Sidharta
membuka pameran tunggalnya di Hotel Santrian Bali walaupun ia tak dapat hadir
karena baru selesai mengalami operasi di Singapura. Ini adalah pameran
tunggalnya terachir semasa hidupnya.
2.7 Tradisi dalam
pengkaryaan G sidharta dibalik arus Prinsip Universalisme Seni Dan
Kecenderungan Modernisme Yang Sedang
Dominan.
G Sidharta memiliki
banyak pandangan dan sikap seni yang bisa dinilai ‘orijinal’, dan
kontroversial, pada masanya. Salah satunya yang penting ketika ia mengatakan: “Saya
ingin mengaitkan kembali dengan jalur kehidupan tradisi, di samping sekaligus
tetap berdiri di alam kehidupan masa kini, yang berarti satu keinginan untuk
menghilangkan jarak antara kehidupan tradisional dan masa kini.
Dalam hal ini say
amemilih cara pendekatan melalui pergaulan yang terus menerus, yang dekat dan
akrab, dengan benda-benda, bentuk-bentuk, cerita, jalan pikiran dan segalanya
yang merupakan hasil dan pengungkapan cita-cita dari kehidupan dan pergaulan
tradisional”(1.
Ketika ia meninggalkan
Yogjakarta, awal tahun 1965, persoalan yang ada di benaknya bukan soal tradisi
yang ingin dijadikan pokok gagasan bagi karya-karyanya. Saat itu, ia justru
tengah jengah dengan lingkungan kerja kreatif di Yogjakarta yang dianggapnya kurang
cocok lagi bagi dirinya. Maka ketika ada tawaran untuk membuka dan mengajar di
studio patung di Bandung (seni rupa ITB) ia pun menerimanya. Pandangan Sidharta
di atas itu justru muncul di akhir tahun 1970’an, di Bandung, di tengah gemuruh
prinsip universalisme seni dan kecenderungan Modernisme yang sedang dominan.
Bagi kecenderungan Modernisme, sebagaimana juga dibayangkan oleh Marcel Duchamp
pada awalnya, tradisi adalah pengertian yang tak lagi aci bagi prinsip
kebebasan dan penciptaan seni. Praktek estetika Formalisme sama sekali tak
mengizinkan hadirnya segala jenis bentuk di luar bentuk karena analisa formal
―apalagi bentuk yang ditujukan untuk menyatakan semacam cerita tertentu. Tak
ada patung yang berwarna-warni dengan berbagai ragam bentuk ornamen
(sebagaimana yang dikerjakan Sidharta saat itu), selain sejatinya sebuah karya
dengan bentuk yang jelas, terukur, dan analitis. Tradisi, bagi prinsip
universalisme seni, dianggap ‘hanya’ bisa menyediakan asumsi-asumsi bagi pokok
nilai kebenaran yang bersifat lokal dan sektoral (karena sedemikian banyaknya
tradisi budaya yang ada di seluruh dunia). Karenanya tradisi dianggap gagal
menyiapkan pokok prinsip yang esensial yang dibayangkan mampu dirangkul seluruh
proyek penciptaan seni yang bersifat mendunia
.Kritikus dan sejarawan
seni, Sanento Yuliman, yang juga jadi teman diskusi sekaligus lawan berdebat
Sidharta di Bandung meninggalkan catatan tentang pendirian Sidharta atas nilai
tradisi yang sering salah ditafsirkan banyak orang. Katanya: “ Dharta [begitu,
Sanento memanggilnya] termasuk seniman yang mencari pilihan lain di anatara
pilihan “keuniversalan” yang dominan itu. Tanpa meninggalkan gelanggang ia
salah satu seniman yang masih menyimpan semangat merdeka dan terus berusaha
mencari rumusan lain bagi persepsi kebudayaan dan sikapnya dalam berkarya
Saat ini satu dekade
sudah kita meninggalkan pengalaman perkembangan seni rupa tahun 1990’an. Tentu
kita masih ingat gemuruh arena biennale dan triennale internasional disepanjang
dekade 1990’an. Sejak akhir tahun 1980’an, arus utama perkembangan seni rupa
dunia [dalam hal ini adalah seni rupa Eropa-Amerika] seolah gemar bertakbir
soal pentingnya nilai-nilai ‘perbedaan’ (difference) dan ihwal ‘ekspresi
budaya’ (cultural context) dalam proses penciptaan karya seni rupa. Prinsip
universalisme seni divonis ‘keliru’ dan kecenderungan Modernisme pun dianggap
bangkrut. Tak aneh, ratusan seniman di seluruh penjuru dunia ramai mengamini
sikap kembali ke ekspresi budaya dan segala pikiran maupun cerita yang berwatak
lokal. Toh kini, kita pun juga tak pantas mengatakan bahwa pihak yang berbeda
sikap dan pendirian dengan Sidharta dahulu adalah tak benar, dan ternyata sikap
Sidharta lah yang tak salah. Sesungguhnya, ihwal bangkrutnya Modernisme dan
bergeloranya segala soal yang disebut ekspresi Post-Modernisme adalah masalah
pembacaan mengenai logika perkembangan seni rupa; sedangkan upaya dan
pencapaian prestasi seniman seperti Anis Kapoor atau Yoko Ono, misalnya, tetap
adalah soal peran para inisiator dan pekerja seni yang gigih bagi perubahan.
Jika kita bisa bersikap lebih jernih, maka sesungguhnya tak ada yang lebih
‘benar’ atau lebih ‘salah’ diantara karya-karya yang dikerjakan oleh Henry
Moore dan Anis Kapoor, misalnya. Kita tentu tetap bisa melihat dua jenis
eskpresi ‘seni’ dari kedua pematung itu, meski memiliki dimensi persoalan yang
berbeda.
Bagi saya, ada pokok soal Modernisme yang sering luput diperkarakan para seniman dan pemerhati seni rupa yaitu apa pernah disinggung teoritisi budaya Raymond Williams. Katanya: “Modernism can be clearly identified as a distinctive movement, always more immediately recognized by what they are breaking from than what, in any simple way, they are breaking towards”(3. Sikap ‘anti tradisi’ adalah pandangan yang terlalu menitik-beratkan pada ‘alasan’ (karena tradisi dianggap terlalu memberikan batasan), dibandingkan cara melihat persoalan ‘tujuan’ dari gerakan Modernisme seni. Dalam prinsip Modernisme sebenarnya tak ada yang bisa dipisahkan dari alasan dan tujuan. Sebagian komentator dan teoritisi seni memang mengganggap bahwa alasan dan tujuan Modernisme adalah utopia yang hanya berisi praktek kekuaasaan yang tak berkeadilan dan akhirnya hanya akan menyisakan frustasi dan kemuskilan (nihilisme). Dengan demikian maka gerakan seni Post-Modernisme adalah semacam harapan dan ideologi ‘pembebasan’. Di titik inilah kita temukan nilai penting mengenang sikap dua pesohor seni di atas (Gombrich dan Duchamp), karena dari sikap keduanya itu kita bisa memahami betapa penting dan kritisnya peran inisiatif para seniman. Bagi saya, tanpa ada sikap dan kesungguhan para seniman maka segala soal seni akan ‘melulu’ jadi filasafat dan pemikiran. Bukankah ekspresi seni jadi significant justru karena kita sadar hal itu berbeda dari cara penafsiran a’la filsafat dan pemikiran? Pun kita tak perlu lagi menduga-duga: Apakah ekspresi seni harus mengandung pemikiran atau tidak? Apa yang dipikirkan Duchamp maupun G Sidharta jelas memiliki relevansi dengan nilai ‘ekspresi’ seni yang mereka geluti masing-masing.
Bagi saya, ada pokok soal Modernisme yang sering luput diperkarakan para seniman dan pemerhati seni rupa yaitu apa pernah disinggung teoritisi budaya Raymond Williams. Katanya: “Modernism can be clearly identified as a distinctive movement, always more immediately recognized by what they are breaking from than what, in any simple way, they are breaking towards”(3. Sikap ‘anti tradisi’ adalah pandangan yang terlalu menitik-beratkan pada ‘alasan’ (karena tradisi dianggap terlalu memberikan batasan), dibandingkan cara melihat persoalan ‘tujuan’ dari gerakan Modernisme seni. Dalam prinsip Modernisme sebenarnya tak ada yang bisa dipisahkan dari alasan dan tujuan. Sebagian komentator dan teoritisi seni memang mengganggap bahwa alasan dan tujuan Modernisme adalah utopia yang hanya berisi praktek kekuaasaan yang tak berkeadilan dan akhirnya hanya akan menyisakan frustasi dan kemuskilan (nihilisme). Dengan demikian maka gerakan seni Post-Modernisme adalah semacam harapan dan ideologi ‘pembebasan’. Di titik inilah kita temukan nilai penting mengenang sikap dua pesohor seni di atas (Gombrich dan Duchamp), karena dari sikap keduanya itu kita bisa memahami betapa penting dan kritisnya peran inisiatif para seniman. Bagi saya, tanpa ada sikap dan kesungguhan para seniman maka segala soal seni akan ‘melulu’ jadi filasafat dan pemikiran. Bukankah ekspresi seni jadi significant justru karena kita sadar hal itu berbeda dari cara penafsiran a’la filsafat dan pemikiran? Pun kita tak perlu lagi menduga-duga: Apakah ekspresi seni harus mengandung pemikiran atau tidak? Apa yang dipikirkan Duchamp maupun G Sidharta jelas memiliki relevansi dengan nilai ‘ekspresi’ seni yang mereka geluti masing-masing.
Pameran ini menampilkan
karya-karya yang dianggap bisa mewakili beberapa tonggak pencapaian artistik G
Sidharta, dan tentunya tak semua karya yang pernah dikerjakannya bisa ditampung
oleh presentasi pameran kali ini. Pokok penting yang hendak disasar oleh pameran
ini adalah juga soal peringatan, ihwal memaknai kenangan kerja keras yang
dilakukan seorang seniman. Selebihnya, kita bisa berharap: mudah-mudahan kita
juga bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari pergulatan kreatif sosok
Gregorius Sidharta Soegijo. Karya-karya yang dipamerkan adalah lukisan, patung,
grafis, dan beberapa dokumen visual karya-karya publik yang pernah dikerjakan G
Sidharta selama ia bekerja di Bandung, Yogjakarta, Jakarta maupun di luar
negeri. Kawan-kawan seniman di Asosiasi Pematung Indonesia bahkan berinisiatif
lebih jauh lagi dengan mengumpulkan dan menata barang-barang serta dokumen
pribadi (milik keluarga G Sidharta) untuk ditunjukkan kepada publik seni rupa
secara luas. Judul pameran: “Homage: G Sidharta Soegijo” jelas adalah ungkapan
rasa hormat dan penghargaan dari para seniman yang pernah menjadi sahabat,
kawan, ‘lawan’ diskusi, atau murid G Sidharta, dan tentunya sama sekali tidak
bermaksud untuk mengkultuskan atau mengagungkan ihwal sosoknya.
Saya pikir, G Sidharta
tentu akan merasa bangga jika sikap kepeloporan dan kerja kerasnya bisa jadi
contoh bagi generasi seniman setelahnya. Lebih penting lagi, generasi seniman
setelahnya juga bisa menafsirkan secara positif apa yang telah dikerjakannya.
Di tahun 1970’an, di Bandung, ketika terjadi ‘wacana perselisihan pendapat’
(discourse of discord) soal ‘patung berwarna’ yang dikerjakan G Sidharta,
masing-masing pihak yang pro dan kontra saling menyatakan argumennya dengan
sengit. Tak ada satu orang pun yang merasa sakit hati, setelah itu. Kini momen
‘discorse of discord’ semacam itu jadi kenangan manis dan berharga. G Sidharta
tentu bukannya tak bisa atau tak paham soal mengerjakan karya patung yang
formalistik (pada pameran inipun kita masih bisa menyaksikan contohnya), tapi
ia hendak bergerak terus dan menghidupkan, apa ditandai Sanento Yuliman
sebagai, ‘semangat merdeka dan terus berusaha mencari rumusan lain bagi
persepsi kebudayaan dan sikapnya dalam berkarya’. Tentu era ‘ketegangan
kreatif’ yang dialami oleh G Sidharta berbeda pada gejala dan prakteknya saat
ini. Namun, tidakkah semangat yang dicontohkannya adalah tauladan yang baik
bagi para seniman masa kini? di era ketegangan paradigma pasar seni yang bisa
menghidupkan sekaligus juga menjadikan lelah daya kreatif seorang seniman?
Jika soal teladan
semangat telah dipancangkan, bagi kita pun ‘diwariskan’ jejak-jejak pergulatan
gagasan dan kreativitas G Sidharta dalam berbagai manifestasi karya. Pada
konteks persoalan ini, pandangan Roland Barthes soal ‘kematian sang seniman’
bisa kita pahami secara produktif dan positif. Karya-karya G Sidharta tentunya
telah menyiapkan kita kemungkinan untuk berdialog dan menyatakan pandangan
[yang bisa terpisah dari intensi G Sidharta yang mengerjakannya]. Bagi
kepentingan semacam ini pula dibutuhkan kemauan dan ‘keberanian’ kita untuk
membayangkan-kembali dan menafsirkan secara produktif makna-makna di balik
karya. Lewat lorong penafsiran semacam ini, baik secara literal [dalam bentuk
pensikapan pendapat] maupun visual [dalam tanggapan bentuk penciptaan karya],
dimensi semangat dan kerja G Sidharta itu akan tiba pada lapangan
makna-maknanya yang terus meluas.
Akhirnya, ekspresi seni
memang kadang hadir bagai kabut misteri, yang seakan menunggu untuk disiangi.
Saya hendak menutup tulisan ini dengan ungkapan Mary Anne Staniszewski, seorang
peneliti seni yang rajin menarik kaitan seni dengan nilai budaya. “’Kebenaran’
yang paling kuat dan jelas dalam berbagai kebudayaan”, ungkapnya, “sering
adalah segala sesuatu yang tak terkatakan dan tak dikenal secara langsung. Di
era modern, hal ini adalah kasus [pemahaman kita] tentang seni. Dengan melihat
[karya-karya] seni, kita dapat mulai memahami bagaimana tiap-tiap cara
representasi kita [mengenai berbagai hal] membutuhkan makna dan kekuatan”(4.
Maka dinamika ekspresi karya-karya G Sidharta, sekali lagi, mengajarkan pada
kita ihwal kekuatan dan keteguhan sikap menjadi seorang seniman yang sejatinya
[turut] menentukan perubahan.
2.8 Seni Patung Kontemporer Dan Masyarakat Urban Serta
Pengkultusan Kultur
Seni rupa kontemporer melalui jaringan kebudayaan dan ekonomi
global menyebar ke seluruh dunia. Dibantu oleh kemudahan akses dan penyebaran
informasi melalui teknologi informasi mutakhir, paradigma seni rupa kontemporer
menjadi kesadaran yang melingkupi seniman di segala penjuru dunia, termasuk di
Indonesia. Seni rupa kontemporer Indonesia menjadi bagian dari global
art-world. Belakangan, cukup banyak seniman kontemporer Indonesia yang
diundang pameran di galeri-geleri komersial di luar negeri. Cukup mudah
menjumpai seniman Indonesia hilir mudik di art fair
Internasional. Demikian pula para kolektor selalu meng-update wawasan
seninya dengan hadir di pameran-pameran dan art fair yang penting.
Tentu saja hal ini memberikan pengaruh besar dalam membentuk wajah seni rupa kontemporer
Indonesia.
Patung kontemporer Indonesia tak lepas dari pengaruh patung
kontemporer global. Sebagai mana telah diutarakan bahwa pengertian patung dalam
seni rupa kontemporer hampir tanpa batas. Batasan patung yang inklusif
menjadi pilihan yang masuk akal, sebab batasan yang sifatnya eksklusif dan
otoritatif tentu tak sesuai dengan semangat seni rupa kontemporer yang plural
dan “apapun boleh”. Mengacu pada teks klasik Kantian-Hegelian, Heinrich
Wolfflin, sejarawan seni asal Swiss, sudah sejak akhir abad sembilan-belas
menyebutkan adanya dua “root of style” yaitu,
“These
are the visual or internal root, which is the link with previous art, and the
social or external root, which is the link with the contemporaneous surrounding
culture.”[xi]
Dalam
seni rupa kontemporer tampaknya akar yang lebih dominan adalah social atau
external root. Hal itu dijelaskan oleh Thomas McEvilley dalam bukunya Sculpture
in the Age of Doubt,
“The
many avenues shunned by Modernist art history as growing from the nonvisual
external root are now being explored in art history text and classrooms. These
include the classic social triad (race, class, and gender); political contents
encompassing repressed ideological subtext; difference in general, especially
ethnic differences and community identities; the mystery of representation and
it secret agenda; and so on. Thus the age of doubt has opened itself precisely
to those experiences the previous age of certainty had condemned and avoided.”[xii]
Namun demikian, pengaruh dari akar visual pun agaknya
memainkan peranan penting dalam seni rupa kontemporer. Aspek visual dalam
kebudayaan kontemporer sangat dominan. Dunia kita adalah dunia yang dibentuk
oleh citraan. Sehari-hari kita diserbu oleh beragam citraan, seperti media
massa, dunia hiburan, iklan, televisi, barang cetakan, komoditas produk. Hal
ini tentu saja mempengaruhi pola pikir dan persepsi visual masyarakat masa
kini. Populernya istilah dan kajian visual culture menunjukkan hal
itu. Walaupun visual culture lebih merujuk pada kenyataan dua dimensi,
namun hal itu juga tidak lepas dari realita tiga dimensi. Rangkaian citraan
iklan di ruang urban membentuk persepsi kita mengenai karakter ruang urban.
Demikian pula, aneka produk industri dan iklan-iklan tiga dimensi juga menjadi
kenyataan visual yang menyerbu keseharian kita. Di sisi lain, jika citraan dua
dimensi memang bisa dibilang dominan, bisa jadi kejemuan terhadap dominasinya
memicu transformasi/transmutasi citraan dua dimensi menjadi tiga dimensi.
Setidaknya hal itu tampak dalam seni rupa kontemporer, banyak karya patung yang
merupakan transmutasi dari citraan atau karya dua dimensi.
Pada kenyataannya, baik akar visual maupun akar sosial
menjadi dasar penting bagi perkembangan patung kontemporer Indonesia. Bahkan
dalam beberapa hal, kedua akar tersebut merupakan pengaruh yang telah menyatu.
Misalnya, pada saat warisan kebudayaan material (material culture)
tradisional menjadi sumber atau perkara yang dipersoalkan oleh seniman
kontemporer Indonesia. Budaya material tradisional menawarkan sekaligus
keduanya: aspek visual maupun aspek sosial. Demikian pula dengan tema
kebudayaan popular yang digandrungi oleh seniman kontemporer, sekaligus
menyediakan kedua perkara tersebut: visual dan sosial. Dalam konteks seni
rupa kontemporer, sepertinya istilah “sumber” lebih tepat daripada istilah
“akar”, sebab yang menjadi bahan bakar penciptaan para seniman
kontemporer adalah segala sumber visual maupun (persoalan) sosial.
Setelah “pokok persoalan” dan “genre visual” didapat, maka
yang selanjutnya dibutuhkan oleh seniman untuk menghasilkan karya patung adalah
menetapkan “presentasi” dan materialnya. Kemungkinan presentasi dalam
seni patung bisa cukup luas: monolit atau instalasi; dalam atau luar ruangan; menggunakan
base, atau tidak, atau digantung; di tengah ruang atau menempel di
dinding, interaktif atau tidak; ukuran, dan seterusnya. Demikian pula pilihan
material hampir tak ada batasnya. Setiap material yang ada dalam kebudayaan
manusia mungkin untuk dijadikan material patung kontemporer. Tentu saja
kemungkinan pokok persoalan, presentasi dan pilihan material juga bergantung
pada trend. Setidaknya situasi tersebut tersebut bisa kita runut melalui
perkembangan patung kontemporer Indonesia sejak tahun 90-an.
Tema sosial-politik merupakan subject matter penting dalam
seni rupa kontemporer Indonesia tahun 90-an, pada saat seniman-seniman
Indonesia mulai terlibat dalam gelaran seni rupa Internasional. Karya-karya
instalasi merupakan tampilan yang lebih menonjol dibandingkan lukisan. Hal itu
bisa kita lihat misalnya pada Bienal Jakarta IX, yaitu bienal yang juga
diramaikan dengan polemik seni posmodern. Demikian pula pada pameran “tradition
and tension” di New York tahun 1996 yang menampilkan seni rupa kontemporer
dari lima negara Asia. Hal yang sama tampak pada pameran “Awas :Recent art
from Indonesia”. Konten sosial-politik menjadi tema yang sesuai bagi seni
rupa kontemporer. Hal itu menjadi identitas (lokal) seni rupa kontemporer
Indonesia. Sementara instalasi banyak dipilih karena memang sedang trend dan
merupakan alternatif kritikal bagi seni lukis “dekoratif” yang ketika itu
sedang booming.
Pada paruh pertama dekade awal abad dua puluh satu, seni
lukis kembali dominan. Hal ini tak lepas dari pengaruh tumbuhnya pasar seni
rupa kontemporer Indonesia sebagai bagian dari pasar seni rupa regional dan
global. Bermunculannya galeri komersial baru. Rumah lelang Internasional mulai
melirik seniman-seniman kontemporer Indonesia. Dipicu oleh permintaan yang
tinggi terhadap karya-karya lukis old master—yang suplainya sangat
terbatas—seni lukis kontemporer Indonesia tumbuh pesat. Beragam tema
dengan nyaman diterapkan pada permukaan kanvas. Booming seni lukis
semakin menyuburkan “produksi” seni lukis. Belakangan mulai muncul
“kejenuhan” pada lukisan. Baik pasar maupun seniman sadar akan hal itu. Salah
satu upaya mensikapi situasi tersebut adalah dengan men-diversivikasi
“produk” artistik. Muncul fenomena menarik, para pelukis mulai menghasilkan
karya-karya patung dalam berbagai kemungkinan. Tentu saja hal ini juga dipicu
oleh para seniman yang sukses di pasar yang sejak awal karirnya merupakan
seniman hybrid, menghasilkan baik karya dua dimensi maupun tiga
dimensi.
Semakin cairnya identitas kesenimanan dan batasan seni patung,
menjadi semacam pembenaran bagi para pelukis untuk menghasilkan karya patung.
Hal itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh semakin cairnya batasan seni—dalam
seni rupa kontemporer. Pengaruh pop art, yaitu bocornya cita rasa seni
populer pada seni tinggi, atau tumpang tindih antara pelaku seni popular dengan
seni tinggi, seperti low-brow, mendorong dihasilkannya beragam
karya-karya patung yang jauh dari frame seni patung modern. Karya-karya tokoh
komik, mainan atau produk branded muncul sebagai karya seni—kerap
disebut commodity sculpture—dan meramaikan seni patung
kontemporer Indonesia.
Berbeda
dengan seni lukis yang sangat dibatasi oleh bidang kanvas, maka seni patung
meyediakan alternatif yang sangat luas. Kemungkinan seni patung tidak
didefinisikan oleh pengertian patung, namun oleh kemungkinannya dalam
kebudayaan masa kini, sebagaimana dikatakan Krauss,
“For,
within the situation of postmodernism, practice is not defined in relation to a
given medium—sculpture—but rather in relation to the logical operation on a set
of cultural terms, for which any medium—photography, books, lines on walls,
mirrors, or sculpture itself—might be used.”
Logika yang bisa kita tarik dari pernyataan Krauss adalah
bahwa bukan penetapan karya sebagai karya patung (kontemporer) yang
menjadikannya istimewa, namun relasinya dengan persoalan “kondisi” kultural.
Dalam konteks masa kini, kondisi kultural bisa diartikan segala persoalan dalam
kebudayaan global. Karena itu bisa dikatakan segala ideologi kesenian bisa
diterapkan melalui seni patung kontemporer.
Para pelukis yang menghasilkan karya patung kebanyakan
menerapkan tema dan gaya lukisannya pada karya patungnya. Itu sebabnya, bisa
dikatakan terjadi transmutasi dari karya dua dimensi menjadi karya tiga
dimensi. Saya menyebut karya-karya tersebut sebagai karya patung tanpa “beban”.
Hal ini memunculkan “anggapan” bahwa mudah saja menghasilkan karya patung,
khususnya bagi para pelukis, cukup “men-tigadimensi-kan” object atau subject
matter dalam karya lukisnya. Bagi para seniman tersebut tidak ada aspek
“esensial” atau “konsep dasar” seni patung. Hal ini tentu berbeda dengan
keyakinan para pematung “akademik”, yaitu para pematung lulusan pendidikan seni
patung.
Pada akhirnya, perkara tema dan medium adalah perkara
pilihan. Karena itu, seniman-seniman keramik dan serat, contohnya di
Barat—karena konstruk sejarah (dikotomi art and craft)—dianggap
sebagai bukan bagian dari seni tinggi, di Indonesia dengan mudah menjadi bagian
seni patung. Dalam seni rupa modern dan kontemporer Indonesia seniman keramik
tak mendapatkan stigma sebagai craft-artist sebagaimana dalam medan
seni rupa Barat. Karena itu para seniman keramik, serat, kayu, logam dan
perhiasan yaitu para seniman yang dalam ruang lingkup pendidikan tinggi seni
rupa diletakkan dalam program studi kriya (craft), juga merupakan
seniman-seniman yang memperkaya wajah patung kontemporer melalui karya-karya
non-fungsionalnya. Karya-karya mereka kerap dikategorikan sebagai karya
“objek”, karena memiliki trayek perkembangan di luar seni patung modern.
Wacana
seni patung tak bisa dilepaskan dari perkara ruang (space) dan material. Karena
itu eksistensi seni patung kerap direndengkan dengan bangunan, dan tentunya
keberadaan arsitek. Sudah cukup lama di Barat, para arsitek dan karyanya menjadi
bagian wacana seni patung modern dan kontemporer. Belakangan ini, para arsitek
dan desainer kerap diundang untuk memperkaya wajah patung kontemporer di
Indonesia. Nama-nama seperti Budi Pradono, Leonard Theosubrata mulai akrab
dengan dunia seni rupa. Demikian pula para desainer, baik dari dunia fashion
dan iklan saat ini kerap terlibat dalam pameran seni rupa kontemporer.
Khususnya dalam patung kontemporer keterlibatan para desainer produk atau
interior merupakan kemungkinan yang menantang. Setidaknya istilah furniture-sculpture—yang
sudah lama beredar dalam wacana patung kontemporer Barat—menunjukkan
kemungkinan tersebut.
Kultur, kulturisasi,
inkulturasi, enkulturiasi, akulturasi merupakan proses jejak kebudayaan
manusia.Dinamika kebudayaan telah dan akan melahirkan jejaring dan jaringan
yang berbentuk tatanan-tatanan sesuai dengan tuntutan zaman. Proses
berkebudayaan dapat dengan berbagai bentuk, misalnya bentuk kultur ekstentif
dan kultur jaringan biosif. Kultur ekstensif berwujud strategi pemeliharaan,
pembudidayaan, misalnya kultur pembudidayaan dengan intensitas rendah,
seperti yang dilakukan komunitas kolektif manusia di kalangan bawah, petani,
buruh dan sebagainya. Sedangkan pada kultur jaringan biosif, proses kebudayaan
direkayasa untuk mempercepat pertumbuhan jaringan lewat media tumbuh yang
diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi masyarakat manusia kolektif
tersebut.
Perlu diketahui dalam proses kebudayaan tersebut baik yang
ekstensif dan biosif menimbulkan pola kultus (pengkultusan) kepada seseorang,
yang dianggap memiliki keluhuran, ia bisa berupa para cerdik cendikia, ulama,
pastur, ilmuwan, teknokrat, seniman, raja, presiden. Kultus yang memang
memiliki arti pemujaan, pendewaan terkadang dilakukan dengan sembrono dan
berlebihan. Robertson mengatakan, bahwa kultus adalah terminologi yang
mengklaim kepada seseorang yang dianggap paling benar, terbenar. Yinger
mengatakan, bahwa kultus adalah gerakan new religion pada kelompok tertentu
yang bersifat doktriner, dan terkadang menyimpang atau menyempal dari religi
besar tertentu pula. Pada intinya, munculnya kultusisasi pada diri seseorang,
karena adanya anggapan bahwa seseorang tersebut memiliki tingkat spiritual
revolusioner.
Pada masyarakat yang majemuk, baik yang ortodoks dan protestan, yang modern maupun yang kolot, yang kampungan maupun yang metropolitan, yang mukmin maupun yang kafir, yang konvensional dan kontemporer dipastikan muncul adanya kulturisasi kultus atau pengkultusan yang dikulturisasikan.
Pada masyarakat yang majemuk, baik yang ortodoks dan protestan, yang modern maupun yang kolot, yang kampungan maupun yang metropolitan, yang mukmin maupun yang kafir, yang konvensional dan kontemporer dipastikan muncul adanya kulturisasi kultus atau pengkultusan yang dikulturisasikan.
Dalam peristiwa budaya misalnya, munculnya kulturisasi kultus
disebabkan oleh adanya kekhawatiran pada sebagian besar manusia perihal akan
masa lalu dan masa depannya, ketakutan akan hidup dan matinya, atau jatuh
bangkit bangunnya. Secara umum manusia memang makhluk unik yang dilematis, satu
sisi diciptakan menjadi pemberani, sisi yang lain memiliki ketakutan,
kepengecutan dan kepengkhianatan. Dilema dua muka atau dua sifat inilah, hidup
manusia serba tergesa-gesa, sekaligus ragu-ragu untuk mencapai puncak tangga
tertentu, misalnya. Dan puncak tangga itu adalah kesuksesan hidup material
jasmanial dan spiritual rohanial. Manusia dengan akal dan nafsunya, terkadang
memuji peristiwa budaya ciptaannya dan juga terkadang memaki peristiwa yang
dialaminya. Dalam menghadapi peristiwa- peristiwa utamanya budaya, manusia ada
yang melakoninya penuh dengan ketelatenan dan kejelian. Tetapi juga sering dilaluinya
penuh dengan intrik-intrik yang berlawanan dengan akal sehat, keduanya akan
mempengaruhi proses pelakonan-pelakonan atas peristiwa budaya mulai dari masa
kecilnya sampai masa tuanya. Peristiwa budaya tumbuh bersama pola pikir
dan pola dzikr ( per-ingatan ) seseorang. Dan seseorang tersebut kemudian
diklaim memiliki sesuatu yang dianggap mulia tadi. Dari sini, muncul proses
peristiwa budaya kala kultur kultus. Pengkultusan yang disertai pengkulturan
dapat terjadi pada ranah peristiwa kebudayaan dan cabang-cabang cakupan dan
kajiannya, misalnya pada cabang cakupan dan kajian ekonomi, agama, bahasa,
politik, adat istiadat, mata pencaharian, teknologi, seni dan ilmu pengetahuan
( pinjam urutan versi Koentjaraningrat)
Coba simak peristiwa budaya yang diciptakan manusia yang
mengandung kulturisasi kultus tersebut, misalnya ketika manusia
“terperangkap atau sedang tertarik” pada peristiwa budaya politik, maka
dari waktu kewaktu, yang digagas hanyalah persoalan politik belaka dengan
segala plus minusnya.Dibenak manusia hanya ada satu yang dianggap terpenting
pada saat itu, yakni persoalan politik. Politik akhirnya menjadi kultus, dipuja
dan didewakan. Dari sikap dan sifat “pengelebihan” pada peristiwa budaya
ciptaan manusia, selanjutnya terjadi korelasi dan relasi konsep atau kata
kalimat yang dimainkan, dengan terasa “mengasyikkan sekaligus membingungkan”,
misalnya permainan kata seni politik, politik seni, kesenian politik,
politisasi kesenian, kesenian yang dipolitisir, seni berbau politik yang
menimbulkan permainan kata yang berlebihan yang berbau kultusiasi konsep dan
kata yang dilontarkan seseorang yang ahli politik, misalnya. Belum lagi
misalnya permainan kata yang melahirkan sikap cultism, seperti agama politik,
politik ekonomi, bahasa politik, ilmu politik, sosial politik dan sebagainya.
Keterperangkapan dan ketertarikan pada permainan korelasi dan relasi atas
konsep kata tersebut, kemudia lahirlah ribuan pemikir politik yang “bermain”
menggila dan dicatat oleh sejarah yang cenderung menciptakan kekulturan yang
mengkultus, sebutlah misalnya, mulai dari pemikir politik yang eksentrik
Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, Zeno, Cicero, Seneca, Plotinus,
Agustinus, Salisbury,Ibnu Sina, Ibnu,Khaldun, Prapanca, Machiavelli, Jean
Bodin,Spinoza,Montesque, Rousseau, Immanuel Kant,David Hume,De Bonald,
Hegel,Joan Stuart Mill, Nietzsche, Lenin, Hitler, Mussolini, Salazar, Gandhi,
Mao Tse Tong sampai Sukarno. Orang-orang ini ( yang dikemudian hari dikultuskan
) mengabdikan sepanjang hidupnya untuk mendalami dengan tujuan mempengaruhi
manusia lainnya melalui peristiwa politik.
BAB III
PENUTUP
1.
Kesimpulan
1.
Patung adalah jenis karya seni dalam wujud tiga dimensi. Dalam era industri dan
teknologi yang semakin canggih sekarang ini, karya-karya seni patung hadir dan
ikut memberikan interpretasinya atas dampak era tersebut. kontemporer; masa kini, sewaktu, sejaman, waktu yang sama dengan pengamat
saat ini
2. Berikut ini adalah
karakteristik dari seni rupa kontemporer, yaitu :
a. Adanya pluralism
dalam estetika, dalam prakteknya seniman
mendapatkan
kebebasan untuk berorientasi pada masa depan, masa lalu
ataupun
sekarang.
b.
Berorientasi karya bebas, tidak menghiraukan batasan-batasan kaku seni
rupa yang
dianggap baku.
c.
penggunaan media atau bahan apapun dalam berkarya seni
d. Berani
menyentuh situasi sosial, politik dan ekonomi masyarakat yang
sedang, pernah ataupun
mungkin akan terjadi
3. G Sidharta memiliki
banyak pandangan dan sikap seni yang bisa dinilai ‘orijinal’, dan
kontroversial, pada masanya. Salah satunya yang penting ketika ia mengatakan: “Saya
ingin mengaitkan kembali dengan jalur kehidupan tradisi, di samping sekaligus
tetap berdiri di alam kehidupan masa kini, yang berarti satu keinginan untuk
menghilangkan jarak antara kehidupan tradisional dan masa kini
Akhirnya, ekspresi seni
memang kadang hadir bagai kabut misteri, yang seakan menunggu untuk disiangi.
Saya hendak menutup tulisan ini dengan ungkapan Mary Anne Staniszewski, seorang
peneliti seni yang rajin menarik kaitan seni dengan nilai budaya. “’Kebenaran’
yang paling kuat dan jelas dalam berbagai kebudayaan”, ungkapnya, “sering
adalah segala sesuatu yang tak terkatakan dan tak dikenal secara langsung. Di
era modern, hal ini adalah kasus [pemahaman kita] tentang seni. Dengan melihat
[karya-karya] seni, kita dapat mulai memahami bagaimana tiap-tiap cara
representasi kita [mengenai berbagai hal] membutuhkan makna dan kekuatan”(4.
Maka dinamika ekspresi karya-karya G Sidharta, sekali lagi, mengajarkan pada
kita ihwal kekuatan dan keteguhan sikap menjadi seorang seniman yang sejatinya
[turut] menentukan perubahan.
Patung kontemporer Indonesia tak lepas dari
pengaruh patung kontemporer global. Sebagai mana telah diutarakan bahwa
pengertian patung dalam seni rupa kontemporer hampir tanpa batas. Batasan
patung yang inklusif menjadi pilihan yang masuk akal, sebab batasan yang
sifatnya eksklusif dan otoritatif tentu tak sesuai dengan semangat seni rupa
kontemporer yang plural dan “apapun boleh”.
Kultur, kulturisasi, inkulturasi, enkulturiasi, akulturasi
merupakan proses jejak kebudayaan manusia.Dinamika kebudayaan telah dan akan
melahirkan jejaring dan jaringan yang berbentuk tatanan-tatanan sesuai dengan
tuntutan zaman. Proses berkebudayaan dapat dengan berbagai bentuk, misalnya
bentuk kultur ekstentif dan kultur jaringan biosif. Kultur ekstensif berwujud
strategi pemeliharaan, pembudidayaan, misalnya kultur pembudidayaan
dengan intensitas rendah, seperti yang dilakukan komunitas kolektif manusia di
kalangan bawah, petani, buruh dan sebagainya. Sedangkan pada kultur jaringan
biosif, proses kebudayaan direkayasa untuk mempercepat pertumbuhan jaringan
lewat media tumbuh yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi masyarakat
manusia kolektif tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
https://www.google.co.id/search?q=kritik+atas+patung+karya+G.Sidharta+pdf&ie676