BAHAN BACAAN PENDIDIKAN SENI RUPA
POKOK BAHASAN
RASIONAL PENDIDIKAN SENI
Untuk pokok bahasan “Rasional Pendidikan Seni, ” disiapkan bahan bacaan wajib untuk mahasiswa. Bahan bacaan tersebut adalah sebagai berikut:
- Sofyan Salam. 2003. Memahami Pendidikan Seni. Makassar: FBS UNM.
- Sofyan Salam. 2003. Pendidikan Seni: Untuk Apa? Makassar: FBS UNM
- Janis Boyd. 2002. Myths, Misconceptions, Problems and Issues in Arts Education. Queensland: QSA
- Jenny Aland. 2002. The Arts in Schools: Beyond 2000. Queensland: QSA
- Margaret Barret. 2002. Reconceptualizing the Arts in Education:Questioning Some Answer?. Queensland: QSA.
- Serta semua bahan bacaan yang diberikan bagi mahasiswa semester II Genap tahun 2002.
MEMAHAMI PENDIDIKAN SENI
Sofyan Salam
1. Pendidikan Seni Sebagai Kegiatan yang Bertujuan Ganda
Pendidikan pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang bertujuan ganda yakni untuk mengembangkan kepribadian seseorang dan sekaligus mempersiapkannya untuk menjadi warga masyarakat yang mandiri dan bertanggung-jawab. Kedua tujuan ini tidaklah saling terlepas tetapi terjalin dalam hubungan yang erat dan tak terpisahkan. Dengan mengembangkan kepribadian seseorang, maka sekaligus ia dipersiapkan pula untuk menjadi warga masyarakat di mana ia berada.
Sebagai suatu usaha untuk mencapai kedua tujuan tersebut, pendidikan berlangsung dalam suatu proses pembelajaran untuk mengalihkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Proses ini terjadi dalam suatu situasi yang menyangkut banyak hal seperti pengaruh antara guru dan murid, materi pembelajaran, lingkungan budaya/geografis, dan sebagainya. Kegiatan pendidikan tidak terlepas dari nilai-nilai yang dianut dan dipandang ideal dalam suatu masyarakat. Ia terikat oleh ruang dan waktu. Ini berarti bahwa kegiatan pendidikan yang berlangsung di Indonesia pada masa sesudah diproklamasikannnya kemerdekaan memiliki sifat yang berbeda dengan pendidikan yang berlangsung pada masa penjajahan. Demikian pula, terdapat perbedaan sifat pendidikan yang berlangsung di Indonesia dengan pendidikan di Amerika, Arab Saudi, Cina, India, Rusia, atau di tempat lain.
Bila kita memahami pengertian “pendidikan” seperti yang telah diuraikan di muka, maka dapatlah dikatakan bahwa pendidikan seni adalah upaya untuk mengembangkan kepribadian seseorang dalam rangka mempersiapkannya untuk menjadi warga masyarakat yang mandiri dan bertanggung-jawab melalui kegiatan yang bersangkut paut dengan seni. Seni dalam uraian ini didefinisikan sebagai proses dan atau hasil pernyataan perasaan keindahan manusia dalam berbagai media. Bila kegiatan atau hasil pernyataan keindahan ini diwujudkan melalui media gerak maka disebut seni tari (dance); melalui media bunyi/suara disebut seni musik (music); melalui media lakon/akting disebut seni teater (theatre); melalui media bahasa disebut seni sastera (literature); dan melalui media garis, warna, tekstur, bidang, volume, dan ruang, disebut seni rupa (visual art). Akhir-akhir ini ada kecenderungan untuk menggunakan berbagai media tersebut secara bersamaan. Kegiatan atau hasil pernyataan perasaan keindahan semacam ini disebut sebagai seni rupa pertunjukan atau seni multi-media.
2. Keunikan Pendidikan Seni
Pendidikan seni sebagai upaya pengalihan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan memiliki kesamaan dan kebedaan dengan dengan pendidikan bidang studi lain. Dalam uraian ini, pembahasan akan difokuskan pada kebedaan pendidikan seni dengan bidang studi yang lain. Tujuannya adalah untuk menonjolkan kekhasan pendidikan seni yang menjadikannya unik sehingga kehadirannya dianggap penting dalam kurikulum.
Keunikan pendidikan seni terletak pada kekhasan “seni” itu sendiri. Seni, meskipun terdiri atas berbagai bidang, secara umum memiliki karakteristik yang sama. Karya seni diciptakan oleh manusia dan semuanya merupakan kegiatan estetik, ekspresif, dan kreatif yang dinyatakan dalam berbagai media. Pada seni musik, medianya adalah suara/bunyi; pada seni tari, medianya adalah (gerak) tubuh; pada seni teater, medianya adalah akting/lakon, dan pada seni rupa medianya adalah garis, warna, bentuk, volume, dan ruang.
Ke tiga istilah yang disebutkan di atas ( estetik, ekspresif, dan kreatif), saling berkaitan erat sehingga dalam pembahasannya amat sulit dipisahkan. Berbagai istilah yang dikenal dalam wacana pendidikan seni bersumber dari ke tiga istilah tersebut seperti “pengalaman estetik,” “persepsi estetik,” “tanggapan estetik,” “kreasi artistik,” “ekspresi artistik,” dan semacamnya. Istilah-istilah ini telah lama menjadi bahan perdebatan para filosof dan hingga saat ini tidak ada jawaban yang bersifat konklusif terhadapnya. Oleh karena itu, bila istilah tersebut akan dibahas di sini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan praktis, bukan pendekatan filsafati karena konon “filsafat itu tidak pernah membuat hal menjadi mudah bahkan menjadikannya lebih sulit.”
3. Pengalaman Estetik, Esensial dalam Pendidikan Seni.
Entah siapa yang mulai menggunakan istilah “pengalaman estetik.” Siapa pun pencetusnya, konsep “pengalaman estetik” telah mengalami perkembangan yang matang pada teori John Dewey, art as experience.
Istilah pengalaman estetik dimaksudkan untuk menggambarkan sejenis pengalaman yang didapatkan dari alam atau karya seni. Pengalaman ini merupakan suatu yang spesial karena adanya kualitas pada alam atau karya seni yang secara tradisional disebut “keindahan.” Pengalaman ini akan muncul bila kualitas tersebut dikenal atau disadari. Oleh karena itu, pengalaman estetik menuntut perhatian yang teerfokus.Beardssley (1974; 459) menegaskan:
A person is having an aesthetic experience during a particular strech of time if and only if the greater part of his mental activity during that time is united and made pleasurable by being tied to the form and qualities of a sensously presented or imaginatively intended object on his primary attention is concentrated.
Sejalan dengan penegasan Beardsley di atas, Knieter (tanpa tahun; 430) mengatakan bahwa sebuah pengalaman estetik merupakan pengalaman yang terarah dan tidak terjadi begitu saja. Karya seni merangsang jiwa untuk berdialog. Dengan demikian, menyaksikan suatu karya seni secara tidak sepenuh hati, tidaklah dapat disebut sebagai pengalaman estetik.
Pengalaman estetik, dengan demikian menuntut keterlibatan emosional dan intelektual seseorang. Bila seseorang dengan perhatian yang terfokus mendengarkan musik, menyaksikan sebuah tarian, atau mengamati sebuah lukisan, maka secara alamiah emosi orang tersebut akan terlibat karena karya seni memiliki kemampuan untuk merangsang aspek kejiwaan (menjadikan orang bersedih, marah, atau riang-gembira) dan fisik (mempengaruhi tekanan darah, detak jantung, dan menimbulkan gerakan refleks) manusia.
Keterlibatan intelektual dalam pengalaman estetik terjadi karena pada saat berlangsungnya kontak yang intens dengan karya seni seseorang akan mengadakan analisis, sintetis, abstraksi, dan evaluasi. Intensitas kegiatan intelektual ini tergantung pada pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki seseorang. Dalam konteks pendidikan, aspek pengalaman dan pengetahuan khusus ini menjadi amat penting oleh karena berkaitan erat dengan masalah budaya.
Seseorang belajar tentang hakekat seni adalah dalam konteks budaya masyarakat. Ide tentang “kualitas keindahan” yang menjadi fokus dalam suatu pengalaman estetik ditentukan oleh pengalaman formal dan informal yang didapatkan oleh seseorang dalam masyarakat tempat ia hidup. Nilai atau cita-rasa keindahan yang dimilikinya merupakan sesuatu yang tumbuh secara alamiah (given) dan akan menjadi pengalaman dan pengetahuan khusus. Setiap kali ia mengadakan kontak dengan karya seni. Persoalan akan muncul bila ia berhadapan dengan karya seni yang menawarkan konsep keindahan yang sama sekali lain dari pengalaman dan pengetahuannya yang telah mempribadi. Terhadap karya seni yang baru ini ia menjadi “bingung” karena tidak mampu memahami dan menikmatinya. Persoalan seperti ini hanya dapat diatasi dengan memberinya pengalaman dan pengetahuan baru yang relevan dengan karya seni yang membuatnya bingung tersebut. Tidak jarang, seseorang yang sebelumnya amat tidak dapat menerima secara intelektual dan emosional suatu karya seni kemudian menjadi seorang yang sebaliknya. Perubahan ini terjadi berkat pengalaman atau pengetahuan baru yang didapatkannya sejak kontak pertama kalinya dengan karya tersebut. Bailey (tanpa tahun; 426) menyadari hal ini dalam dunia apresiasi seni musik dengan menuliskan:
The problem, therefore, is not really one of discovering music but rather of discovering new interests in various kinds of music and developing new patterns of response to already familiar music. No adult (or for that matter no teen-ager) can begin to discover music in any literal sense. Most people have heard and responded to music from a very early age, and therefore, a set of responses already exists. The problem is to discover methods through which one’s existing pattern of responses can be enriched, broadened, and then extended to new sets of stimuli.
Jika pengalaman estetik merupakan sesuatu yang esensil dalam pendidikan seni, maka persoalan pokok adalah “bagaimana memberikan kepada anak pengalaman estetik dan sekaligus mengembangkan potensinya agar mampu mendapatkan pengalaman estetik yang lebih kaya dan bermakna.”
4. Bagaimana Mengembangkan Potensi Pengalaman Estetik?
“Kepekaan rasa” atau sensitivitas merupakan aspek yang harus mendapatkan perhatian bila potensi pengalaman estetik seseorang akan dikembangkan. Kepekaan rasa ini dapat terbina melalui tiga kegiatan yakni: kreasi (creation), pelakonan (performance), dan penanggapan (response).
4.1 Kreasi (creation)
Kreasi biasanya dipandang sebagai proses menghasilkan sesuatu yang baru. Pada dunia seni, kreasi atau populer pula dengan istilah “kreasi artistik,” dapat berupa penyusunan komposisi musik, penataan tari, perancangan taman, pembuatan lukisan atau pembangunan monumen. Proses penciptaan dalam dunia seni, menuntut keterlibatan intelektual, emosional, dan fisik secara penuh agar mampu dilahirkan sesuatu yang orisinal. Dengan penciptaan, tersirat adanya kebebasan bagi seseorang dalam menemukan beragam cara atau pendekatan pemecahan masalah.
Sebelum kita membahas lebih jauh, istilah “orisinal” atau “sesuatu yang baru” perlu dijelaskan dalam konteks kegiatan pendidikan. Jika seorang seniman menciptakan sesuatu yang baru yang belum dikenal sebelumnya, maka temuan tersebut disebut temuan kreatif dalam arti yang sesungguhnya. Dalam dunia pendidikan, seorang anak yang menciptakan sesuatu yang baru bagi dirinya (meskipun temuannya tersebut bukanlah hal baru karena telah ditemukan oleh orang lain) dapat disebut sebagai kegiatan kreatif.
Sejumlah pakar telah mencoba untuk mengidentifikasi langkah-langkah utama dalam penciptaan karya seni. Pada umumnya para pakar ini sepakat bahwa proses penciptaan karya seni tidak mengikuti langkah-langkah yang pasti dan beraturan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh seseorang dalam menciptakan karya seni bersifat perseorangan. Langkah yang ditempuh dalam melukis tentu berbeda dengan langkah yang ditempuh dalam merancang sebuah taman; demikian pula dalam menyusun komposisi musik atau menata tarian. Meski demikian, ada dua langkah utama yang umumnya dilewati dalam proses kreasi karya seni yakni penemuan/pengembangan ide, dan pernyataan ide dalam wujud karya.
Langkah pertama, penemuan/pengembangan ide. Yang dimaksudkan dengan ide di sini adalah “apa yang akan diungkapkan.” Ide ini berada dalam benak. Ada yang menemukan ide ini setelah dengan sengaja mencarinya, ada pula yang mendapatkan ide ini secara serta-merta karena mendapatkan inspirasi secara tiba-tiba. Ide yang akan diungkapkan atau dibuat oleh seorang dapat bersumber dari diri sendiri misalnya dari perasaan sedih, rindu, marah, atau riang gembira yang dialami. Bisa juga dari hayalan yang muncul. Ide dapat berasal dari orang lain seperti pengalaman atau riwayat hidup seseorang; Ide dapat bersumber dari lingkungan alam atau buatan manusia seperti laut, api, pepohonan, kehidupan binatang, jembatan, pelabuhan, menara air, dan sebagainya; dan ide dapat lahir dari kebutuhan hidup manusia seperti kebutuhan akan pakaian, perumahan, sistem komunikasi, penyambutan tamu, hiburan, persembahan, dan sebagainya. Penemuan ide ini ditandai oleh adanya keinginan untuk menciptakan karya seni. Ide yang telah ada pada diri seseorang perlu dikembangkan agar memungkinkan untuk dinyatakan sehingga dapat didengar atau dilihat. Pada tahap ini, ide yang telah ada mungkin disempurnakan atau bahkan direvisi. Bagaimana ide tersebut diwujudkan, sudah mulai difikirkan pada tahap ini. Pengembangan ide ini mungkin dilakukan dengan cara mengadakan perenungan, membuat coretan-coretan untuk lebih memberikan gambaran nyata tentang ide yang akan dikembangkan, membuat prototip (bentuk awal) karya, dsb.
Langkah kedua, pernyataan ide dalam wujud karya. Sebuah karya seni barulah tampak bila diwujudkan melalui berbagai media. Proses perwujudan karya ini tidaklah bersifat linear tetapi terkadang bolak-balik tak beraturan. Pada kenyataannya, kegiatan proses penciptaan karya seni amat ditentukan oleh jenis dan bentuk karya yang akan dihasilkan. Sebuah patung cor logam yang berukuran besar tentu memerlukan proses pengembangan dan pernyataan ide yang lama dan rumit dibanding dengan sebuah patung kecil dari bahan tanah liat. Demikian pula sebuah lukisan dinding yang lebar menuntut perencanaan yang lebih matang dibanding dengan sebuah lukisan kecil yang dibuat dengan teknik finger painting. Sebuah pertunjukan kolosal yang melibatkan banyak orang, tentu melewati proses yang lebih rumit dibandingkan dengan pertunjukan solo.
Mengapa kreasi artistik atau biasa pula disebut ekspresi artistik dianggap mampu mengasah kepekaan rasa seseorang? Jawabnya jelas, yakni kegiatan penciptaan memberi kesempatan kepada seseorang untuk mendayagunakan kemampuan intelektual dan emosionalnya untuk menemukan dan menghadirkan solusi artistik. Semakin sering kegiatan kreasi dilakukan oleh seseorang, maka akan semakin peka lah orang tersebut terhadap gejala estetik. Sebagai ilustrasi dapat dicontohkan: seorang yang pernah mengalami bagaimana menggunakan alat canting dalam membatik, akan lebih mudah untuk mengapresiasi sebuah karya batik yang dihasilkan dengan teknik canting. Seorang yang pernah merasakan bagaimana berjalan dengan menggunakan ujung jari kaki akan lebih bisa merasakan kesulitan gerakan yang dipertontonkan oleh seorang penari balet.
Kegiatan kreasi dalam pendidikan seni tentu saja tujuannya bukanlah sekedar melatih kepekaan rasa estetik seseorang agar ia mampu mengapresiasi karya seni akan tetapi pada kemampuan orang tersebut untuk mengaktualisasikan dirinya secara estetik.
4.2 Pelakonan (performance)
Pelakonan merupakan cara lain bagi seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya. Perbedaannya dengan kegiatan kreasi adalah pada pelakonan, seseorang mengulangi sebuah ciptaan yang telah ada sebelumnya sebagaimana yang dilakukan pemain teater, penari, atau pemusik. Meskipun bersifat menghadirkan kembali suatu ciptaan, pelakonan ini tetap dipandang sebagai kegiatan kreatif. Alasannya adalah: seorang pemain teater, penari, atau pemusik tidak begitu saja mengikuti skenario atau pedoman yang ada tetapi secara bebas memberikan penafsiran sendiri. Itulah sebabnya sebuah karya seni yang dimainkan ulang senantiasa hadir secara unik.
4.3 Penanggapan (response)
Bila pada kreasi dan pelakonan seseorang secara aktif menghasilkan atau mempertunjukkan sesuatu, dan karena itu berperan sebagai seniman, maka pada penanggapan, seseorang berperan sebagai pengamat atau penonton yang perhatiannya terpusat pada mendengarkan atau menyaksikan suatu karya seni atau gejala keindahan untuk kemudian memberikan penilaian. Mendengarkan atau menyaksikan suatu karya seni secara terfokus kemudian mengomentarinya, menuntut keterlibatan intelektual dan emosional. Semakin sering seseorang melakukan kegiatan ini, maka akan semakin berkembanglah kepekaan rasa estetiknya.
Pada kegiatan penanggapan, seseorang mulai dengan mencerap dan mengolah data estetik dari suatu gejala atau karya seni yang menjadi sasarannya. Kegiatan menerima dan mengolah data estetik ini populer dengan istilah persepsi estetik (esthetic perception). Pada persepsi estetik, peran alat indera amat penting oleh karena melalui alat indera inilah informasi diterima. Bila alat indera seseorang tidak berfungsi baik atau kurang peka, maka kapasitasnya untuk menerima data estetik menjadi berkurang. Sejak bayi, kemampuan penginderaan ini tumbuh secara alamiah. Sebagai contoh, seorang bayi menanggapi suara/bunyi yang bersifat musikal, warna dan bentuk, serta gerakan yang diperlihatkan padanya. Manusia memang amat bergantung pada kemampuan penginderaannya untuk memperoleh informasi mengenai dunia sekelilingnya.
Menurut teori Gestalt, kemampuan seseorang untuk menerima dan kemudian memilah dan memilih informasi, bertambah sejalan dengan kedewasaan seseorang. Artinya seorang dewasa memiliki kemampuan persepsi yang lebih unggul dibanding dengan anak-anak. Keunggulan kemampuan persepsi ini terutama ditunjukkan oleh para ahli dalam berbagai bidang. Seorang ahli pengecap minuman misalnya, mampu dengan segera membedakan kualitas anggur dengan hanya mencium aroma dan melihat warnanya. Seorang kritikus seni rupa dapat dengan segera mengenal karya seorang pelukis meskipun ia tidak menyaksikan sendiri lukisan tersebut dibuat. Seorang pengamat musikmampu menunjukkan unsur pengaruh luar pada sebuah aransemen lagu. Hal ini terjadi karena pengalaman luas dan intensif yang mereka miliki memberikan pengaruh pada kemampuan persepsinya.
Meskipun anak memiliki potensi persepsi yang secara alamiah dapat berkembang akan tetapi karena gejala estetik merupakan suatu hal yang kompleks, maka diperlukan upaya khusus untuk mengembangkan kemampuan persepsinya.
Dalam pendidikan seni, pengembangan kemampuan persepsi anak dilakukan dengan cara mengintensifkan kontak anak dengan gejala estetik yang ada di sekitarnya. Kontak seseorang dengan gejala estetik sesungguhnya terjadi se tiap saat. Hanya saja kontak tersebut biasanya terjadi tanpa disadari. Dengan latihan memokuskan perhatian secara terarah, kontak seseorang menjadi lebih bermakna. Agar seseorang dapat secara terarah memusatkan perhatian dalam kegiatan pencerapan, ia perlu diberi kerangka acuan (frame of Reference) estetik. Dengan kerangka acuan estetik ini, seseorang diberikan kemampuan untuk mencerap gejala di sekelilingnya dalam kaitannya dengan struktur formal dan tema ekspresif suatu karya seni. Misalnya dalam mengamati suatu karya lukisan, perhatian seseorang diarahkan pada struktur formal suatu lukisan seperti garis, warna, tekstur, volume, komposisi, atau tema yang diekspresikan oleh lukisan tersebut. Dalam mendengarkan karya musik, perhatian seseorang diarahkan pada melodi, harmoni, dan sebagainya.
Pencerapan yang dilakukan terhadap gejala estetik mengantarkan seseorang ke tahap pemberian nilai (valuasi) terhadap hal, obyek, atau peristiwa estetik yang menjadi sasaran perhatian. Pemberian nilai dapat dilakukan secara intuitif maupun secara rasional. Pada pemberian nilai secara intuitif, seseorang memberikan nilai sesuatu secara spontan berdasarkan “kata-hatinya.” Misalnya terhadap beberapa lukisan yang diperlihatkan padanya, seseorang secara serta-merta menunjuk sebuah lukisan sebagai lukisan yang “paling disenanginya” dan lukisan lain yang “paling tidak disenanginya”tanpa berupaya untuk menjelaskannya mengapa demikian. Pada pemberian nilai secara rasional, seseorang berupaya untuk mempertanggung-jawabkan penilaiannya berdasarkan pengetahuan teoritis yang relevan.
Untuk melakukan penilaian yang rasional, seseorang haruslah memiliki kemampuan untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan dalam bentuk penilaian terhadap gejala estetik yang telah dicerapnya. Pada pendiskripsian, seseorang mengidentifikasi karakteristik suatu karya seni. Untuk karya lukisan, misalnya, identifikasi ini mencakup media yang digunakan, corak/aliran karya, tahun pembuatan, dsb. Untuk karya seni musik, identifikasi mencakup jenis musik, karya siapa, di mana, dan kapan. Pada penganalisisan, seseorang membahas suatu karya secara lebih mendalam misalnya dengan mengungkapkan di mana letak kualitas artistik (atau ketidak-artistikan) suatu karya, konteks budaya, sosial, dan politik dari karya tersebut dan sebagainya.
Perlu disadari, bahwa dalam konteks pendidikan, kegiatan penganalisisan ini amat penting oleh karena menawarkan kepada seseoarng “pengalaman menemukan sesuatu” yang dapat menimbulkan kepuasan emosional. Itulah sebabnya, kegiatan in dipandang pula sebagai kegiatan kreatif. Penganalisisan karya tentu saja memerlukan kemampuan intelektual dan kepekaan rasa. Kemampuan yang tak kalah pentingnya adalah keberanian. Feldman (1970; 362) menulis:
This stage of art criticism (baca:penganalisisan/penafsiran) is the most difficult, the most creative, and the most rewarding. It is the stage when you have to decide what your earlier observations mean. Of course, your intelligence and sensitivity are needed; but especially important is courage. You must not afraid to risk being wrong. That is, making an interpretation that does not fit the facts immediately. You can change or adjust your interpretation until it does fit the visual facts, so thereis no harm in being wrong or wide of the mark at your first try.
Kegiatan penganalisisan karya seni yang diakhiri dengan penilaian dapat dilakukan secara terbuka dalam bentuk tulisan atau disampaikan secara lisan. Tetapi dapat pula dilakukan secara pribadi dengan cara berdialog dengan diri sendiri. Cara yang pertama tentu saja yang memberi peluang kepada seseorang untuk mengaktualisasikan diri.
PENDIDIKAN SENI: UNTUK APA?
Sofyan Salam, 2003
Filosofi pendidikan seni tercermin pada jawaban atas pertanyaan: Pendidikan seni,untuk apa? Pendidikan seni dalam bentuk upaya pengalihan pengetahuan, sikap, dan keterampilan seni, dari satu generasi ke generasi berikutnya, telah berlangsung sejak masa awal peradaban manusia. Sebagai suatu kegiatan yang menuntut kerja keras, waktu, dan biaya, upaya pengalihan ilmu seni ini tentu saja dilakukan karena ada maksud tertentu yang mendasarinya. Ringkasnya, ia memiliki Raison d’etre. Ia memiliki justifikasi.
1. Justifikasi Pendidikan Seni Secara Umum
Justifikasi atau alasan keperiadaan pendidikan seni, di manapun kegiatan tersebut dilaksanakan, pada dasarnya dapat dibagi atas 2 kelompok yakni alasan berdasarkan pertimbangan kepentingan masyarakat (social justification) dan alasan berdasarkan kepentingan perseorangan yang bersifat kejiwaan atau fisik(personal justification). Kelompok yang kedua, khususnya yang menyangkut aspek kejiwaan, muncul lebih belakangan sejalan dengan timbulnya pengakuan terhadap kebutuhan pribadi seseorang sebagai akibat dari perkembangan psikologi.
1.1 Berdasarkan Kepentingan Masyarakat
Sebagai konsekuensi dari pola hidup bersama yang dibangun umat manusia, timbullah berbagai kebutuhan kolektif yang menuntut tindakan tertentu untuk memenuhinya. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah pendidikan seni.
Pendidikan seni yang didasari keinginan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini menempatkan segala kegiatan yang dilakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dianggap perlu oleh masyarakat. Berbagai tujuan yang dianggap perlu tersebut, tak lain dari pada “cerminan keinginan untuk melestarikan fungsi seni dalam masyarakat.” Agar seni dapat tetap berfungsi, diperlukan regenerasi pelaku seni.
Agar kita dapat memahami secara lebih baik alasan keperiadaan pendidikan seni dalam konteks memenuhi kepentingan masyarakat, perlulah kiranya kita menengok sejenak fungsi seni dalam masyarakat, mulai dari masyarakat yang kehidupannya sering disebut primitif sampai kepada masyarakat yang berkehidupan maju dewasa ini.
Pada masyarakat penganut animisme/dinamisme yang identik dengan masyarakat primitif, seni difungsikan dalam kegiatan yang amat mendominasi kehidupan mereka yakni pemujaan anima (rokh), khususnya rokh nenek moyang. Tempat pemujaan serta perkakas (termasuk kostum) yang digunakan dalam upacara pemujaan haruslah spesial: monumental, simbolistis, atau indah. Demikian pula halnya dengan gerakan tubuh, tabuhan gendang, tiupan seruling, atau suara yang dilantunkan. Karena seni dalam kehidupan masyarakat primitif amat berkaitan erat dengan reliji, maka sifat sakral pun melekat padanya. Seni bukanlah suatu hal kosong tanpa arti tetapi sebaliknya ia merupakan kegiatan yang sarat makna.
Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang ditandai oleh semakin kompleksnya kebutuhan anggotanya, fungsi seni pun semakin beragam. Diantaranya fungsi ekonomi, politik, edukasi, dan rekreasi.
Fungsi ekonomi seni tercermin pada dimanfaatkannya seni untuk meningkatkan kualitas suatu komoditi sehingga ia memiliki nilai jual yang lebih baik. Komoditi tersebut bisa berupa perabot, kendaraan, atau perkakas yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, karya seni itu sendiri merupakan komoditi yang dapat dijual sehingga memiliki nilai ekonomi seperti lukisan, patung, karya kerajinan/disain produk, berbagai bentuk seni pertunjukan atau rekamannya baik dalam bentuk kaset, CD, atau VCD/DVD.
Fungsi politik seni tercermin pada dimanfaatkannya seni sebagai media propoganda atau kritik dalam upaya mencapai tujuan politik tertentu seperti yang diemban oleh gambar karikatur, poster, lagu/pertunjukan untuk mengkampanyekan ide politik tertentu. Dimanfaatkannya seni untuk menanamkan kesadaran berbangsa melalui upaya penggalian identitas diri, merupakan wujud fungsi politik seni.
Fungsi edukasi seni tercermin pada dimanfaatkannya seni sebagai media untuk mencerdaskan masyarakat melalui gambar, lukisan, foto, lagu, tarian, film, dan sebagainya. Melalui berbagai media tersebut, pesan untuk merubah prilaku masyarakat ke arah yang dicita-citakan, disampaikan.
Fungsi rekreasi seni tercermin pada dimanfaatkannya seni untuk memberi hiburan seperti yang diemban oleh gambar kartun, karikatur, lawak, lagu, tarian; atau dimanfaatkannya seni bagi seseorang untuk sekedar mengisi waktu lowong dengan cara melukis, membatik, menyulam, meniup seruling, menyanyi, dsb.
Keragaman fungsi seni dalam masyarakat secara otomatis melahirkan seniman dalam berbagai bidang spesialisasi seperti pelukis, pematung, pengrajin, arsitek, fotografer, perancang grafis, ilustrator, perancang busana, kartunis, penari, koreografer, gitaris, pianis, drummer, pemain trompet, pelawak, aktor, penata cahaya, sutradara, dan sebagainya. Tentu saja untuk melestarikan keperiadaan seniman dalam berbagai bidang profesi ini diperlukan beragam bentuk pendidikan seni. Selain itu, agar anggota masyarakat non-seniman mampu berpartisipasi dalam mendukung atau mengapresiasi kegiatan seni diperlukan bentuk pendidikan seni dalam konteks pendidikan umum.
1.2 Berdasarkan Kebutuhan Perseorangan
Studi terhadap dunia anak yang secara gencar dilakukan pada penghujung abad ke-19 (Macdonald 38) menyadarkan orang bahwa anak merupakan pribadi yang unik yang memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda dengan orang dewasa. Salah satu bentuk dan kemampuan anak yang khas tersebut adalah dalam hal mengekspresikan diri.
Sejak usia dini, anak telah menunjukkan kebutuhan untuk menyatakan dirinya melalui goresan, suara, atau gerak. Bila anak usia 4 tahun diberi pensil, spidol, atau krayon, maka ia akan secara serta merta membuat goresan yang kita sebut sebagai gambar atau lukisan. Bila kepadanya diperdengarkan alunan musik dan diminta untuk mengikutinya dengan gerakan tubuh, maka dengan luwesnya ia akan bergoyang-goyang. Goresan atau gerakan tubuh anak yang kita sebut sebagai gambar/lukisan atau tarian tentu saja harus dipahami tidak dalam konteks karya seniman dewasa.
Disadarinya kebutuhan anak untuk mengekspresikan rasa keindahan, mendorong pendidik untuk menyediakan fasilitas berupa kegiatan yang memungkinkan anak untuk secara lancar dapat mengungkapkan rasa keindahan serta juga dapat mengapresiasi gejala keindahan yang ada di sekelilingnya. Kegiatan untuk memasilitasi anak dalam mengaktualisasikan diri inilah yang ditawarkan oleh pendidikan seni, khususnya di sekolah. Jelaslah, pendidikan seni dalam konteks ini, hadir untuk memenuhi kebutuhan anak yang asasi yang tidak mampu diemban oleh kegiatan lain.
Uraian di atas menunjukkan kepada kita bahwa ada beragam alasan mengapa pendidikan seni penting untuk dilaksanakan baik ditinjau dari segi kepentingan masyarakat, maupun dari segi kepentingan perseorangan. Konsekuensi dari keberagaman ini adalah beragamnya pula konsep tentang arah dan cara pelaksanaan pendidikan seni dilaksanakan.
2. Justifikasi Pendidikan Seni di Sekolah
Justifikasi pendidikan seni berdasarkan kepentingan masyarakat dan perseorangan secara jelas tercermin pada pendidikan seni di lembaga pendidikan formal yang disebut sekolah. Pada sekolah, justifikasi keperiadaan pendidikan seni dapat ditelusuri pada tujuan pendidikan yang menjadi acuan ke arah mana pendidikan seni di suatu sekolah ditujukan.
2.1 Sekolah Non-Seni
Istilah non-seni yang digunakan di sini mengacu pada sekolah yang program pendidikan yang ditawarkannya tidak secara khusus bertujuan untuk mencetak seniman atau ilmuwan seni (kritikus seni, sejarawan seni). Karena program yang ditawarkannya tidak dimaksudkan untuk mencetak tenaga profesional dalam bidang seni, maka penerimaan murid tidak mengutamakan faktor bakat atau pengetahuan seni. Termasuk dalam kategori sekolah non-seni ini adalah sekolah umum (SD, SLTP, SMU) dan sekolah kejuruan non-seni.
Meskipun sekolah non-seni ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga profesional dalam bidang seni, pada kenyataannya, mata pelajaran yang dikategorikan sebagai mata pelajaran seni seperti menggambar, melukis, mematung, menyanyi, menari, main drama, dan sebagainya, diajarkan.
Diajarkannya mata pelajaran seni di sekolah non-seni didasari berbagai alasan seperti pertimbangan bahwa seni potensial untuk dimanfaatkan mencapai berbagai tujuan, baik demi kepentingan masyarakat atau negara maupun kepentingan perseorangan yang bersifat fisik atau kejiwaan.
2.1.1 Pendidikan Seni untuk Membentuk Manusia Ideal
Manusia ideal yang dimaksudkan di sini mengacu pada pribadi manusia yang oleh masyarakat pada suatu tempat dan kurun waktu tertentu diharapkan untuk dihasilkan setelah melewati suatu proses pendidikan seni. Sosok manusia ideal tersebut dianggap akan mampu memberi sumbangan yang maksimal bagi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, manusia ideal yang diharapkan untuk dihasilkan setelah melewati proses pendidikan seni di sekolah dasar di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh kurikulum 1975 adalah manusia yang dapat: (a) memperkuat kepribadian, kebanggaan, kesatuan nasional; (b) menggali kesenian daerah dalam rangka kesenian nasional; dan (c) menanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia (Djauhar Arifin dkk 3). Contoh yang lain, manusia ideal yang diharapkan untuk dihasilkan setelah melewati proses pendidikan seni (khususnya apresiasi seni) sebagaimana yang diungkap oleh Oscar Neale, seorang pendidik seni dari Amerika, adalah manusia yang mampu menghargai karya-karya seni yang agung yang memungkinkannya untuk mendapatkan pengaruh patriotisme, simpati, keberanian, dan keindahan yang telah dipersembahkan oleh para seniman besar (Eisner dan Ecker 17).
Berikut ini berbagai profil manusia ideal yang telah dijadikan sasaran untuk dicapai dalam kegiatan pendidikan seni di sekolah non-seni:
a. Manusia Terampil
Manusia terampil dalam konteks pendidikan seni adalah manusia yang terampil dalam bidang seni rupa, tari atau musik. Dimasukkannya mata pelajaran seni seperti menggambar, menari, menyanyi atau bermain musik di sekolah umum bermula dari keinginan untuk menghasilkan lulusan yang salah satu kemampuannya adalah terampil dalam bidang seni. Keterampilan bidang seni yang diharapkan tentu saja dalam kerangka pendidikan umum.
Keinginan untuk menghasilkan lulusan yang terampil dalam bidang seni didorong oleh berbagai pertimbangan antara lain agar lulusan tersebut memiliki kemampuan dasar untuk (a) terjun ke dalam masyarakat baik dalam rangka mencari nafkah maupun dalam upaya melibatkan diri dalam kegiatan sosial, atau (b) melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjutan.
Pendidikan seni di sekolah non-seni yang disemangati oleh keinginan untuk mencetak manusia terampil (sekalipun tidak seintensif dengan sekolah khusus seni) memfokuskan perhatiannya pada pelatihan ketrampilan sehingga program pendidikannya berkesan “pendidikan vokasional.” Kesan pendidikan seni di sekolah umum sebagai pendidikan vokasional terlihat pada program pelajaran menggambar yang dilaksanakan di berbagai sekolah di Inggeris, Amerika Serikat, atau Australia pada abad ke-19. Walter Smith, seorang guru gambar untuk industri dan kerajinan dari Inggeris yang kemudian menjadi pengarah pendidikan seni rupa/menggambar di Massacchusets, Amerika Serikat menegaskan bahwa tujuan pelajaran menggambar di sekolah adalah untuk keperluan yang bersifat praktis yaitu untuk memberikan murid keterampilan kerja.
Dijadikannya sekolah umum sebagai ajang pelatihan keterampilan pada masa itu adalah karena desakan para dari pihak industri. Disadari oleh para pengusaha industri pada masa itu bahwa keterampilan menggambar, khususnya menggambar ornamen, sangat dibutuhkan oleh industri mereka setelah melihat bahwa produk mereka tidak mampu bersaing di luar negeri karena mutu disainnya kurang bagus.
Di Indonesia, pelajaran menggambar dan kerajinan tangan di sekolah umum yang dijadikan sebagai ajang pelatihan kerja berlangsung pada sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada masa penjajahan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pemerintah kolonial yakni dihasilkannya pekerja terampil yang dapat dijadikan pegawai pada kantor pemerintahan Hindia Belanda.
b. Manusia Sadar Budaya
Manusia sadar budaya adalah manusia yang menyadari dirinya sebagai bagian dari masyarakat tempat ia hidup. Dengan kesadaran itu, ia memiliki sikap positif terhadap budaya masyarakatnya berupa rasa cinta, bangga, dan keinginan untuk melestarikan budaya tersebut. Di berbagai tempat dan waktu, kegiatan pendidikan seni yang diarahkan untuk menghasilkan manusia sadar budaya ini, dilaksanakan.
Pada abad ke-4 SM, di Peloponesos Yunani, pelajaran menggambar model diajarkan di sekolah umum pada tingkat sekolah dasar. Menurut Hubbard, tujuan menggambar model bagi murid di sekolah dasar ini merupakan bagian dari pendidikan untuk melestarikan budaya klasik Yunani (5). Kita mengetahui bahwa salah satu prestasi budaya bangsa Yunani yang menonjol adalah seni mimesis, atau seni peniruan (penampakan) alam. Dengan diajarkannnya melukis model sebagai salah satu bentuk seni mimesis tersebut, akan tertanam pada diri anak rasa memiliki budaya sendiri.
Upaya untuk menanamkan kesadaran akan budaya sendiri melalui program pendidikan di sekolah umum, juga terlihat di Cina yakni pada pelajaran melukis dan menulis indah (kaligrafi). Menurut Winner, seorang pendidik seni dari Amerika yang pada musim semi tahun 1987 berada di Cina untuk mengamati pelaksanaan pendidikan seni di sekolah, sejak anak berada di kelas satu sekolah dasar, anak telah diajarkan bagaimana menggunakan kuas secara benar, bagaimana cara duduk yang tepat, atau cara mencampur tinta berdasarkan tradisi Cina yang telah mengakar. Alasan guru melaksanakan cara pengajaran seperti itu adalah untuk mengakrabkan anak akan budaya Cina yang mereka anggap unggul sehingga anak memiliki rasa cinta akan budayanya sendiri. Hal ini tentu saja merupakan langkah strategis dalam rangka pelestarikan budaya Cina.
Di Jepang, seni rupa tradisional telah menjadi bagian dari kurikulum sekolah sejak lebih dari seratus tahun yang lalu. Dimulai pada akhir tahun 1880 an ketika seni kerajinan dan seni lukis tradisional Jepang diajarkan di sekolah dasar. Tujuan dimasukkannya seni rupa tradisional Jepang dalam kurikulum sekolah pada masa itu adalah untuk memperkenalkan murid akan tradisi Jepang sehingga mereka akan memiliki kebanggan nasional. Sejak reformasi Meiji, teknik seni rupa Barat memang mendominasi pelajaran seni rupa di sekolah (Masuda 100, 102; Yamada 64) dan ini dianggap kurang kondusif terhadap upaya pengembangan jatidiri bangsa Jepang.
Promosi kebudayaan Jepang kemudian digelorakan lagi pada masa Perang Dunia ke-II (Masuda 101). Pada buku teks yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Jepang pada tahun 1942-1943, guru sekolah dituntut secara tegas untuk mempromosikan teknik tradisional Jepang (Masuda 102). Bagi orang jepang, pengajaran seni di sekolah merupakan suatu cara untuk menanamkan kesadaran budaya dalam upaya mempromosikan identitas nasional Jepang.
Di Australia, Cynthia Ven merancang kegiatan pendidikan seni yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran budaya bagi anak Aborigin bahwa mereka hidup di Australia yang didominasi oleh budaya Barat. Caranya adalah dengan menggabungkan tradisi seni Aborigin dengan tradisi ekspresi-kreatif Barat. Dengan cara tersebut, Cynthia Venn berupaya untuk mengasimillasikan anak Aborigin ke dalam masyarakat Australia yang berkebudayaan Barat.
Di Indonesia, pengajaran seni di sekolah dengan tujuan menanamkan rasa sadar budaya sendiri telah dilaksanakan pada masa penjajahan oleh Ki Hajar Dewantoro di sekolah Taman Siswa yang didirikannya pada tahun 1922. Sekolah ini memang didirikan atas dorongan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia. Di sekolah ini anak tidak hanya dibina aspek kecerdasan dan ketrampilannya saja tetapi juga budi pekerti dan kesadaran budayanya.
Sesudah Indonesia merdeka, pengajaran seni di sekolah dengan tujuan menanamkan kesadaran budaya secara jelas tercermin pada diajarkannya seni tradisional berbagai suku baik dalam bentuk seni tari, seni musik, maupun seni rupa/kerajinan. Diajarkannya seni tradisional di sekolah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada murid tentang budayanya yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya tersebut. Hal ini dimungkinkan karena pengajaran seni tradisional memberikan kesempatan kepada murid untuk menyatakan perasaan keindahannya melalui pendekatan atau cara (gerakan tubuh pada seni tari, alunan suara/bunyi pada seni musik, atau gambaran motif hias pada seni rupa/kerajinan) yang berakar pada budayanya sendiri. Melalui pendekatan atau cara tradisional yang bersifat lokal tersebut murid mempelajari nilai yang melekat pada suatu karya seni tradisional seperti nilai kesabaran atau kepatuhan mengikuti aturan tertentu. Lebih jauh, dengan pengalaman berolah seni tradisional, murid akan lebih bersifat apresiatif terhadap seniman tradisional.
Pendidikan seni sebagai upaya untuk membentuk manusia sadar budaya secara khusus terwadahi pada program muatan-lokal. Pada buku acuan pengembangan program muatan-lokal provinsi Sulawesi-Selatan yang diterbitkan pada tahun 1994, misalnya, direkomendasikan untuk memilih kesenian daerah sebagai pokok bahasan dengan tujuan menumbuhkan kecintaan terhadap hasil kesenian daerah yang pada gilirannya akan menyadarkan murid akan perlunya pelestarian atau perevitalisasiannya.
c. Manusia Peka Rasa
Manusia peka-rasa adalah manusia yang cepat merasakan gejala yang ada di sekelilingnya sehingga menjadi tanggap. Dalam kaitannya dengan pendidikan seni, peka rasa yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan gejala keindahan alam maupun buatan manusia berupa gerak, bunyi, atau rupa.
Kepekaan rasa keindahan seseorang akan mengantarkannya kepada kemampuan apresiatif terhadap nilai keindahan. Dengan demikian, orang yang peka rasa akan memiliki kesadaran penghayatan lingkungan yang tinggi. Orang yang demikian ini akan mampu mencerap berbagai variasi rangsang keindahan dari lingkungannya. Ia dapat merasakan getaran keindahan yang dipancarkan oleh deburan ombak, matahari terbenam, ekspresi wajah pengemis, gerakan penari, alunan seruling, maupun goresan ekspresif pelukis. Sebaliknya orang yang tumpul kesadaran penghayatan lingkungannya akan sukar untuk menemukan atau merasakan rangsang keindahan yang khas, unik, atau menarik. Semua yang diinderanya dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja.
Pentingnya arti kepekaan rasa bagi diri seorang ditegaskan oleh Earl W. Linderman dan Donald W. Herberholz yang menempatkan kepekaan rasa sebagai tahap awal yang penting dalam proses penciptaan karya seni. Artinya, orang yang peka rasa akan mampu menghasilkan karya seni yang bermakna. Kepekaan rasa seseorang tercermin pada kemampuannya dalam menerima, mengamati, dan menghayati rangsang-rangsang dari luar (Linderman, 1974; 18).
Karena orang yang peka-rasa dipandang dapat berbuat positif terhadap lingkungannya, maka kemudian timbul kesadaran bagi pendidik seni untuk mencetak orang yang peka rasa, khususnya terhadap gejala keindahan. Kesadaran pendidik seni untuk membina kepekaan rasa terhadap nilai keindahan telah dilontarkan oleh William Cullen Bryant pada 1370 (Peterakis, 1977; 13) tetapi ide ini barulah mulai mekar pada awal abad ke-20 berkat gencarnya pertukaran ide di kalangan pendidik seni baik melalui jurnal maupun melalui seminar.
Upaya pengembangan kepekaan rasa keindahan ini kemudian menjadi bagian penting dari pendidikan seni di sekolah umum. Dalam pendidikan seni rupa populer kegiatan “pembahasan foto” berupa pengenalan karya-karya agung dari seniman besar dunia melalui foto reproduksi. Menyertai pengenalan karya tersebut, diceriterakan hal-hal yang menarik baik menyangkut karya maupun latar belakang kehidupan seniman penciptanya.
Dalam pendidikan seni musik, kegiatan mendengarkan musik (vokal atau instrumen) diperkenalkan. Mendengarkan musik di sini bukanlah asal mendengarkan begitu saja, akan tetapi mendengarkan secara terarah dengan penuh perhatian. Dalam pendidikan seni tari, anak diarahkan untuk mengamati gerakan hewan, tanaman, manusia, dan tentu saja gerakan penari.
Program pengembangan kepekaan rasa ini kemudian populer dengan istilah pendidikan apresiasi seni yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti eksplorasi alam, kunjungan ke museum, sanggar, atau galeri, serta koleksi berbagai benda yang relevan seperti gambar, foto, kaset, dan sebagainya. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk menghasilkan manusia yang peka rasa.
d. Manusia Kreatif
Manusia kreatif identik dengan manusia yang mampu menawarkan suatu gagasan atau karya yang unik, orisinal, baru, dan segar. Manusia kreatif memiliki kepercayaan diri, tanggap terhadap keadaan sekelilingnya, menonjol rasa ingin tahunya, senang melontarkan gagasan baru, bersikap luwes, berani untuk tampil beda, dan siap menerima risiko.
Gambaran tentang manusia kreatif di atas dianggap sosok yang ideal untuk mendorong kemajuan bangsa. Tidak mengherankan, bila kemudian manusia kreatif dijadikan sasaran yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan.
Di Amerika Serikat, Ide tentang pendidikan seni untuk menghasilkan manusia kreatif gencar diperkenalkan pada masa 1920-1930 an. Tokoh pendidik seni seperti Margaret Mathias, Bella Boas, Florence Cane, dan Victor D’Amico berpendapat bahwa pendidikan seni potensial untuk mencetak manusia kreatif (Eisner, 1966; 9). Tujuan pendidikan seni untuk menghasilkan manusia kreatif kembali gencar dikampanyekan pada akhir 1950 an saat bangsa Amerika dikejutkan oleh kemampuan teknologi ruang angkasa Uni Soviet yang dicapai pada masa itu. Bangsa Amerika ingin segera dihasilkannya orang kreatif terutama dalam bidang IPA dan teknik agar mereka mampu menyaingi, bahkan mengungguli Uni Soviet. Kongres Amerika pun meyetujui penyediaan dana yang besar untuk merealisasikan keinginan tersebut.
Agar tidak ketinggalan dalam upaya besar untuk mencetak manusia kreatif, beberapa tokoh pendidik seni tampil dengan gagasan yang mengaitkan antara kekreatifan dalam bidang seni dan kekreatifan secara umum. Gerakan pendidikan seni untuk mempromosikan kekreatifan segera menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal ini berkat peran UNESCO melalui berbagai seminar yang disponsorinya.
Di Indonesia, pendidikan seni dalam rangka mencetak manusia kreatif gencar dipromosikan oleh pendidik seni, khususnya yang berkiprah di berbagai IKIP pada tahun 1970 an. Promosi ini tidak terlepas dari pengaruh pemikiran yang berlangsung di luar negeri terutama di Amerika dan Eropah.
e. Manusia Bugar dan Elegan
Manusia bugar dan elegan secara khusus merupakan sosok yang diharapkan untuk dicapai melalui pendidikan seni tari. Hal ini logis karena secara umum seni tari berkaitan dengan gerakan tubuh yang giat dan bersemangat yang menunjang kebugaran tubuh. Seni tari berperan penting dalam mengembangkan ketahanan, kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh yang pada gilirannya menjadikan gerakan seseorang tampak elegan.
Karena keterkaitan antara seni tari dengan kebugaran jasmani inilah maka di berbagai sekolah, seni tari ditempatkan pada bagian pendidikan jasmani. Bahkan di Amerika Serikat, pada suatu masa, seorang yang akan diangkat menjadi guru seni tari di sekolah lanjutan diwajibkan untuk memiliki sertifikat pendidikan jasmani (Kraus 603).
Sesungguhnya, dalam bidang seni rupa dan seni musik keaktifan fisik anak juga terjadi seperti dalam menggoreskan warna, membentuk tanah liat, meniup terompet, atau memukul gendang, tetapi keaktifan fisik tersebut tidaklah seintensif dengan apa yang tejadi pada seni tari sehingga kebugaran tubuh tidak menjadi tujuan yang secara khusus dirumuskan dalam pendidikan seni rupa dan musik.
2.1.2 Pendidikan Seni untuk Memenuhi Kebutuhan Aktualisasi Diri
Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri anak seperti yang diungkap di muka (lihat butir 2.1) dipandang perlu untuk difasilitasi di sekolah, khususnya di sekolah non-seni yang tidak dibebani tugas untuk menghasilkan seniman profesional.
Melalui kegiatan seni anak akan memperoleh pengalaman estetis yang oleh John Dewey disebut sebagai “sesuatu yang memberikan kegairahan dan menimbulkan kesadaran akan suatu pengalaman khas dalam kehidupan.” Bila matematika dan ilmu pengetahuan alam memberikan pengalaman bagi anat untuk berfikir secara sistematis dan rasional, maka seni memberikan pengalaman bagi anak untuk menanggapi dan menyuguhkan sesuatu dengan perasaan sensitif. Bila matematika dan ilmu pengetahuan alam membantu anak untuk memahami dunia secara intelektual, maka seni membantu anak untuk memahami dunia secara emosional. Manusia yang berkepribadian utuh adalah mereka yang memiliki kematangan intelektual dan emosional sekaligus.
Pendidikan seni sebagai bentuk kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang sebagai manusia (karena itu, sering disebut sebagai kegiatan untuk memanusiakan manusia) secara gencar diadvokasi oleh kaum humanis. Kaum humanis mengakui bahwa kegiatan pendidikan adalah untuk menyediakan pengalaman intrinsik yang menyenangkan yang akan memberi sumbangan bagi perkembangan dan pembebasan pribadi seseorang. Bagi mereka, tujuan pendidikan adalah untuk membantu anak mengaktualisasikan dirinya agar dapat tumbuh menjadi manusia yang utuh (McNeil 5-6).
2
POKOK BAHASAN
PENDIDIKAN SENI
DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
Untuk pokok bahasan “Pendidikan Seni dalam Perspektif Sejarah, ” disiapkan bahan bacaan wajib untuk mahasiswa. Bahan bacaan tersebut adalah sebagai berikut:
- Sofyan Salam, Pendidikan Seni sebagai Pendidikan Profesi (Tinjauan Kesejarahan).
2. Sofyan Salam, Pendidikan Seni dalam Konteks Pendidikan Umum (tinjauan Kesejarahan);
PENDIDIKAN SENI SEBAGAI PENDIDIKAN PROFESI
(Tinjauan Kesejarahan)
Sofyan Salam
1. Sistem Magang di Rumah, Sanggar, dan Gilde.
Telah disinggung di muka, bahwa profesi sebagai pelukis, pematung, atau pengrajin pada masa Yunani Klasik umumnya diturunkan dari ayah ke anak atau melalui kegiatan pemagangan (apprentisceship system)di rumah atau di sanggar. Pendidikan seni semacam ini, yang alasan keperiadaannya adalah untuk menghasilkan seniman profesional yang dapat melestarikan kebudayaan dan sekaligus memenuhi kebutuhan praktis masyarakat akan karya seni, dilaksanakan berdasarkan konsep “bekerja sambil belajar.” Dengan cara ini, pendidikan berlangsung secara alamiah dan dalam suasana yang tidak formal.
Karena kehidupan seniman mengalami gangguan akibat kekacauan yang terjadi pada Abad Pertengahan, maka pendidikan seni secara magang di rumah atau sanggar seniman menghilang. Sebagai gantinya, pendidikan seni berlangsung dalam kompleks gereja. Meskipun tujuan pendidikan seni yang dilaksanakan dalam lingkungan gereja ini adalah untuk mencetak manusia yang dapat secara penuh mengagungkan Tuhan, lulusan yang dihasilkannya, berkat latihan keterampilan yang ketat, dapat dikategorikan sebagai seniman.
Menjelang berakhirnya Abad Pertengahan di Eropah, bermunculan gilde yakni organisasi pengrajin untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya. Kemunculan gilde ini dipicu oleh bangkitnya kehidupan ekonomi kota yang disertai oleh kebutuhan jasa pengrajin/tukang. Pada gilde inilah berlangsung kegiatan pendidikan dalam berbagai bidang kerajinan/ketukangan dengan sistem magang yang telah dikenal sebelumnya. Tujuan pendidikan yang dilaksanakan pada gilde adalah untuk membentuk pengrajin profesional melalui pelatihan keterampilan yang intensif dan ketat-aturan (misalnya dalam menjaga rahasia teknik berkarya, atau dalam menerima pesanan). Pendidikan dalam lingkungan gilde yang berlangsung sekitar 5-6 tahun ini diawasi oleh seorang ahli yang dibantu oleh beberapa orang asisten. Dibanding dengan sistem magang yang secara tradisional dilaksanakan dalam lingkungan rumah atau sanggar, pendidikan yang juga menganut sistem magang di gilde berlangsung secara lebih terencana.
Renaisan Italia yang merupakan babakan baru setelah berakhirnya abad pertengahan, sangat penting dalam sejarah kebudayaan Barat karena kaum humanis yang muncul pada masa ini meletakkan dasar-dasar konsepsi tentang seni dan pendidikan seni (berkat studi mereka terhadap kebudayaan Klasik) yang pengaruhnya amat signifikan terhadap kebudayaan Barat di kemudian hari.
Bagi kaum humanis Renaisan, pendidikan yang diberikan oleh gilde untuk mencetak pengrajin terampil tidaklah cukup untuk mencetak seniman yang berwawasan ideal yang mereka cita-citakan. Kaum humanis melihat perbedaan yang nyata antara “seni murni” sebagai karya intelektual dan “seni pakai” sebagai produk ketrampilan tangan. Sebelumnya, pemisahan antara seni murni dan seni pakai tidak dikenal dan karya seni rupa dianggap sebagai hasil ketrampilan tangan (Macdonald; 17). Kaum humanis memandang karya-karya Leonardo da Vinci, Michaelangelo, dan Raphael bukanlah sekedar hasil ketrampilan tangan. Pemisahan antara seni murni dan seni pakai pada masa ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan pendidikan seni rupa. Kaum humanis mempertanyakan kompetensi gilde untuk menghasilkan seniman besar yang tidak hanya terampil dalam berkarya tetapi juga memiliki wawasan yang luas. Bagi kaum humanis, pengetahuan tentang filsafat, sejarah, dan sastra klasik mestilah dimiliki oleh seorang seniman. Akademi seni rupa, tempat seniman perupa dapat mempelajari teori-teori yang relevan dengan bidangnya, menjadi sebuah kebutuhan.
Untuk itulah lahir gagasan untuk mendirikan akademi, tempat untuk mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan tentang teori dan filosofi seni. Istilah akademi sendiri diambil dari nama tempat Plato dan muridnya berdiskusi.
2. Pendidikan di Akademi Seni
Bentuk akademi seni yang pertama bukanlah akademi seni dalam pengertiannya yang modern yang dilengkapi dengan kurikulum formal yang dirancang oleh dosen (kurikulum akademi ini, bila akan dikatakan demikian, hanyalah merupakan teori yang dikembangkan oleh anggotanya berkaitan dengan prinsip matematis seni, anatomi, atau sejarah seni antik). Akademi seni yang disponsori oleh orang yang berpengaruh ini sesungguhnya hanyalah merupakan tempat berkumpulnya sekelompok seniman dari berbagai usia (ada seniman pemula, ada seniman senior) untuk berkarya, menyaksikan orang lain memeragakan teknik/prinsip baru, atau mendiskusikan teori seni/kebudayaan. Trend ke arah naturalisme memberi pengaruh yang kuat terhadap kegiatan seni rupa di akademi. Pada tulisan Alberti, Della Pictura, secara jelas terungkap prinsip pengajaran seni rupa kaum humanis. Disebutkan pada tulisan tersebut bahwa: sebuah lukisan mestilah menerapkan teori perspektif dan sistem proporsi; mempunyai thema, penggambaran dramatis atau mengangkat peristiwa sejarah yang bersumber dari karya sastera atau kitab Injil; dan mampu menggerakkan hati penikmat ke arah sikap moral dan keagamaan yang positif (Efland; A History 28).
Sekilas tentang Kaum Humanis Renaisan
Kaum humanis Renaisan mempelajari secara mendalam karya sastra klasik meliputi sejarah, filsafat, dan puisi. Dari hasil studinya itu, mereka menyadari bahwa pendidikan umum merupakan suatu yang diperlukan bagi setiap orang, tidak hanya bagi biarawan atau dokter. Hal ini disebabkan karena mempelajari pengetahuan umum yang pada dasarnya merupakan pengetahuan yang benar tentang pengalaman manusia, dapat menanamkan moral dan kesadaran sebagai warga masyarakat.
Gagasan kaum humanis ini menyebar dengan luas berkat didirikannya sekolah yang berbeda dengan sekolah yang ada pada Abad Pertengahan. Sekolah kaum humanis ini secara ekstensif menggunakan karya tulisan sebagai sumber informasi bagi murid, dibanding dengan penggunaan ceramah pada Abad pertengahan.
Teori tentang seni pun dituliskan seperti prinsip seni lukis yang dikemukakan oleh Alberti pada karyanya yang bertahun 1453, Della Pictura: (1) Sebuah lukisan mestilah membangkitkan kenyataan ruang dan historis dengan menggabungkan antara perspektif dengan sistem proporsi dan ukuran yang mengacu pada tubuh manusia. (2) Sebuah lukisan haruslah memiliki istoria(tema), situasi dramatis atau episod sejarah dari karya sastra klasik/injil. (3) Tema lukisan haruslah dinyatakan dengan warna, pencahayaan, proporsi, dan komposisi yang tepat agar dapat menyatakan suasana secara hidup dan dramatis, yang dapat menimbulkan rasa takut, rasa senang, atau dapat mendidik orang yang menyaksikannya.
Pada tahun 1563, Akademi del Dissegno, akademi seni rupa yang bersifat formal didirikan di Florence dibawah perlindungan Cosimo dei Medici (Macdonald; 24). Menyusul akademi ini, Akademi St. Luke di Roma didirikan pada tahun 1593. Akademi-akademi ini menjadi penting oleh karena mendominasi kebijakan-kebijakan kesenirupaan seperti penentuan arah pengembangan seni rupa, perumusan kriteria pemberian penghargaan kepada perupa, pelaksanaan pameran dan juga penyampaian kritik seni rupa (Hauser; 132).
Pada tahun 1648 Akademi Royal Perancis didirikan di Paris. Seperti akademi-akademi yang lebih dahulu didirikan di italia, Akademi Royal Perancis mendidik mahasiswanya melalui ceramah dan praktek studio. Metode ceramah diberikan untuk mengajarkan tentang prinsip-prinsip seni rupa berdasarkan pendekatan naturalisme, sedangkan praktek studio diberikan melalui menggambar model. Ketika dipimpin oleh Le Brun, akademi ini mengembangkan kurikulum yang amat kaku yang mengatur secara ketat mengenai karya seni yang dianggap standar yang harus diikuti oleh murid. Teori seni yang dijadikan pijakan oleh pihak akademi yakni teori yang dikembangkan oleh Nicolas Poussin (baca: Nikolas Poosan).
Dalam pelajaran menggambar, pada tingkat permulaan, murid harus meniru gambar yang dibuat oleh dosen. Tingkat selanjutnya adalah menggambar dengan menggunakan model patung. Pada tingkat akhir, murid menggambar dengan menggunakan model manusia. Program yang ditawarkan terdiri atas pengetahuan teori dengan metode kuliah serta latihan teknis yang mengikuti cara yang diterapkan pada metode magang yang telah populer sebelumnya. Subyek yang dapat diangkat sebagai tema lukisan, disiapkan oleh pihak akademi.
Seperti yang dilakukan pada akademi-akademi seni rupa di Italia sebelumnya, menggambar model dibina oleh professor-professor yang ditugaskan secara bergantian setiap bulan. Dengan cara ini mahasiswa mendapatkan pengalaman diajar menggambar oleh professor-professor yang tentu saja memiliki cara mengajar sendiri-sendiri
Selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan seni rupa, Akademi Royal Perancis juga menangani penyeleksian seniman untuk diberikan proyek-proyek seni rupa serta mengawasi pembuatan benda-benda seni yang akan digunakan sebagai hiasan pada istana raja dan bangunan publik. Tidak mengherankan bila akademi ini kemudian menjadi lembaga yang berpengaruh yang mampu mendiktekan pandangan estetisnya kepada seniman. Akademi Royal Perancis menjadikan tradisi klasik sebagai dasar pandangan keseniannya. Mahasiswa yang belajar di akademi ini diwajibkan untuk mengkopy karya-karya antik Yunani (Myers; 556) karena dipandang bahwa prinsip-prinsip seni rupa klasik menjadi dasar bagi dihasilkannya keindahan yang agung (Macdonald; 54). Istilah “prinsip-prinsip akademis” dalam dunia seni rupa bersumber dari prinsip-prinsip pelatihan seni rupa yang dilaksanakan di akademi-akademi pada masa ini yang meliputi studi anatomis, perspektif, teori-teori komposisi, dsb. Belajar seni rupa melalui peniruan alam mewarnai pelatihan seni rupa di akademi-akademi seni rupa hingga abad ke-19.
Seperti halnya dengan Akademi del Dissegno dan Akademi St. Luke, Akademi Royal Perancis memainkan peran yang penting dalam sejarah seni rupa oleh karena menjadi model bagi akademi-akademi seni rupa yang bermunculan sesudahnya di seluruh Eropah (Cornel; 279). Menurut perhitungan Pevsner, hingga pertengahan abad ke-18 ada 25 akademi seni rupa yang didirikan di Eropah termasuk akademi-akademi seni rupa yang ada di Florence, Roma, Bologna, Milan, Vienna, St. Petersburg, Toulouse, dan Edinburg (Efland; A History 44).
Munculnya akademi-akademi seni rupa di Eropah ini kemudian disusul pula oleh Amerika. Yang pertama didirikan di Mexico pada tahun 1785 dan di Philadelphia pada tahun 1791 (Efland; A History 44). Meskipun akademi-akademi seni yang baru ini mendapat pengaruh yang kuat dari Akademi Royal Perancis amatlah kuat, motivasi pendiriannya tidaklah persis sama. Bila Akademi Royal milik Kerajaan Perancis didirikan terutama karena alasan politis yakni ingin mengontrol seni buat kepentingan istana, pendirian akademi seni yang lain terutama karena pertimbangan ekonomi sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan akan karya seni rupa (khususnya menggambar/disain) sejalan dengan perkembangan dunia industri.
Nicolas Poussin
Poussin berasal dari sebuah kampung di Normandia. Ia ke Paris untuk belajar melukis. Subyek lukisannya bertemakan agama, alegori, atau mitologi. Komposisi lukisannya bersifat formal dengan struktur yang stabil. Ia berpendapat bahwa penikmat lukisan haruslah mampu untuk menangkap isyarat atau simbol pada lukisan dan karena itu tema lukisan mestilah dinyatakan secara jelas dan logis. Menurutnya, “Lukisan seyogyanya lebih merangsang fikiran dari pada perasaan.” Pendapat Poussin ini sesungguhnya bukanlah hal baru oleh karena Leonardo da Vinci telah menyatakan bahwa “tujuan yang paling utama dari lukisan adalah menyatakan keinginan jiwa manusia” (Janson, History 441).
Metode Poussin dalam melukis dimulai dengan membuat sket kasar sebuah subyek dengan mengatur model lilin kecil yang diletakkan pada kotak menyerupai panggung. Dengan cara ini, pencahayaan dapat dikontrol. Peletakan model serta pencahayaan dirubah hingga komposisi yang diinginkan dicapai. Menurut Poussin, ia tidak melukis dengan model hidup karena ia ingin menjaga idealisme bentuk. Pandangan Poussin tentang lukisan ini merupakan sumber penting bagi teori seni yang diajarkan di Royal Academy di Perancis dari pertengahan abad ke-17 hingga terjadinya Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18.
Abad ke-19 Revolusi Perancis mempunyai pengaruh yang amat kuat bagi kehidupan masyarakat. Tuntutan yang semakin kuat akan kebebasan individual diikuti oleh kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Dengan hilangnya kekuasaan besar dari raja-raja yang secara tradisional menjadi pemesan utama karya-karya seni rupa, seniman perupa menjadi tergantung pada pembeli baru dalam situasi pasar bebas.
Sanggar-sanggar seni rupa (dikenal dengan istilah atelier) menawarkan kesempatan belajar bagi perupa muda yang berbakat . Untuk dapat diterima pada sebuah atelier, seseorang harus menunjukkan portfolio (contoh-contoh karya terbaik) kepada pemimpin sanggar. Bila portfolionya dinilai mengesankan, maka ia kemudian diminta untuk menggambar model. Diterimanya seorang calon anggota sanggar tergantung pula pada pendapat anggota sanggar lainnya. Sanggar-sanggar yang melaksanakan pendidikan ini pada mulanya mengikuti cara yang dilaksanakan oleh akademi-akademi seni rupa yang telah ada yakni pemberian pengalaman studio serta pengajaran teoritis berdasarkan aturan-aturan yang telah baku. Sanggar-sanggar ini kemudian secara bertahap tampil dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimental.
Sementara itu, sehubungan dengan kondisi masyarakat yang telah berubah ini, akademi-akademi seni rupa diperhadapkan dengan tantangan-tantangan baru. Tantangan pertama adalah adanya tuntutan agar sistem pengajaran di akademi memberi ruang yang lebih leluasa kepada mahasiswa untuk mengembangkan corak pribadinya dalam berkarya sehingga tidak hanya terbelenggu dengan aturan-aturan akademis yang kaku. Di Paris, tempat yang memiliki tradisi akademis yang amat kuat, tuntutan ini tidak begitu membawa hasil. Upaya untuk mengakomodasi tuntutan akan pemberian kebebasan kepada mahasiswa ditunjukkan oleh sebuah akademi seni rupa di Jerman, tepatnya di Dusseldorf, yang memberi kesempatan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan tahap pendidikan tertentu untuk memilih seorang professor yang disenanginya sebagai pembimbing hingga akhir studinya (Efland; A History 54).
Tantangan kedua yang dihadapi oleh akademi-akademi seni rupa pada masa ini adalah adanya kebutuhan yang luar biasa akan tenaga disainer bagi industri yang sedang berkembang pesat. Seperti diketahui, akademi-akademi seni rupa ini, sejak awal tidak diarahkan untuk melahirkan perupa siap pakai untuk kebutuhan industri tetapi pada dihasilkannya seniman-seniman perupa intelektual yang bergelut dengan seni murni. Maka sekolah-sekolah khusus semacam politeknik untuk mencetak disainer pun dibangun di mana-mana. Di Perancis misalnya, pada dekade awal abad ke-19, terdapat 80 sekolah tinggi disain semacam ini. Karena tujuan dari sekolah-sekolah khusus ini adalah menghasilkan disainer siap pakai untuk dunia industri, maka pendekatan pengajaranya pun berbeda dengan akademi-akademi seni rupa yang ada. Menggambar model yang begitu penting pada akademi-akademi seni rupa tidak menjadi bagian dari kurikulum sekolah-sekolah disain ini (Efland; A History 54-61). Sementara itu, di Amerika Serikat dibangun sekolah tinggi seni rupa yang sekaligus menawarkan program seni murni dan disain industri seperti the Cooper Union, the Pratt Institute, dan The Rhode Island School of Design.
Salah satu perkembangan yang berarti dalam hal pelaksanaan pendidikan seni rupa di perguruan tinggi pada masa ini adalah diajarkannya mata pelajaran seni rupa di universitas. Seni rupa sebagai mata pelajaran yang diberikan di Universitas bermula di Inggeris pada penghujung abad ke-19. Dimulai oleh John Ruskin yang memberi kuliah mengenai seni murni di Universitas Oxford. Disebutkan bahwa kuliah John Ruskin diikuti oleh banyak orang. Untuk membuat kuliahnya menarik, ia memperagakan koleksi-koleksi karya seni rupa.
Usaha Ruskin untuk mengajarkan mengenai seni rupa di universitas segera ditiru oleh universitas-universitas di Amerika. Universitas Harvard, Yale, dan Princeton adalah universitas-universitas Amerika pertama yang memasukkan seni rupa dalam kurikulumnya. Di Universitas Harvard, pengajaran seni rupa dimulai pada tahun 1874 oleh Charles Eliot Norton seorang kawan dekat Ruskin. Tujuan pengajaran seni rupa yang diberikan oleh Norton adalah untuk memperkenalkan seni rupa Barat khususnya dari masa Yunani klasik ke Renaisans dan mengembangkan kepekaan artistik mahasiswa. Untuk itu pelajaran yang ditawarkan adalah sejarah seni rupa dan praktek menggambar dan melukis cat air. Norton berkeyakinan bahwa pelajaran teori mestilah dilengkapi dengan pengalaman studio. Logan menulis tentang Norton sebagai berikut: “Norton was eager to define the arts, to create in the student’s thinking a place for the arts as a historical record. He wanted to direct an interest in the arts in such a fashion as to be acceptable to most academically minded” (Logan; 65). Meskipun kegiatan studio merupakan bagian penting dari pengajaran Norton, mahasiswa tidaklah diharapkan untuk menjadi seorang seniman perupa profesional. Kegiatan studio dimaksudkan hanyalah sebagai cara untuk mengembangkan kepekaan artistik.
Di Universitas Yale, program seni rupa yang ditawarkan lebih mementingkan aspek pengalaman studio meskipun sejarah dan kritik seni rupa juga ditawarkan. Sementara itu, Di Princeton, programnya difokuskan pada studi sejarah seni rupa. Program-program seni rupa yang ditawarkan di 3 universitas Amerika di atas kemudian menjadi model bagi universitas-universitas lain yang menawarkan program seni rupa.
PENDIDIKAN SENI DALAM KONTEKS PENDIDIKAN UMUM
(Tinjauan Kesejarahan)
Sofyan Salam
Pendidikan seni dalam konteks pendidikan umum berpijak pada asumsi bahwa seni, sebagaimana dengan bidang studi lain, potensil untuk membentuk manusia ideal yakni manusia yang memiliki kepribadian paripurna sebagaimana yang dicita-citakan oleh suatu kelompok masyarakat. Di sini, manusia merupakan hal yang utama sedangkan seni hanyalah alat belaka. Praktik pendidikan seni berdasarkan asumsi ini telah berlangsung sejak lama dan telah melahirkan beragam konsep. Tulisan ini meninjau konsep tersebut dalam perspektif kesejarahan dengan pembagian kurun waktu: (1) masa pramodern dan (2) masa modern yakni masa diakuinya anak sebagai pribadi yang unik yang berbeda dengan orang dewasa.
1. Masa Pramodern
Melalui tulisan tentang politik yang dihasilkan Plato dan Aristoteles dapat diketahui bahwa pendidikan seni di Yunani dilaksanakan dalam upaya melestarikan budaya Yunani. Kebudayaan Yunani dapat dilestarikan bila manusia Yunani yang dicita-citakan dapat dibentuk yakni manusia yang memiliki kesempurnaan fisik serta kehalusan jiwa (intelektual, estetis, moral). Konsep manusia ideal Yunani tersebut, terancam oleh kehadiran kaum Sofis yang berusaha untuk mendidik kaum muda agar menjadi pemimpin politik melalui pemberian keterampilan dalam menggunakan kata-kata (retorika).
Gimnastik dan musik merupakan mata pelajaran yang dianggap penting dalam membentuk manusia ideal yang dimaksud. Gimnastik melatih kekuatan dan keanggunan, sedang musik melatih kepekaan jiwa. Perlu diketahui bahwa istilah “musik” yang kita kenal dewasa ini tidak persis sama maknanya dengan istilah “mousike” yang digunakan oleh masyarakat Yunani. Istilah mousike lebih luas maknanya yakni mencakup puisi, sejarah, lagu, tari, komedi yang kesemuanya berada di bawah perlindungan Dewi Kesenian (Efland, A History 12). Plato dan Aristoteles dengan giat menganjurkan pengajaran musik dan gimnastik dalam kaitannya dengan pembentukan manusia Yunani yang ideal. Mereka tidak mendukung pendidikan gimnastik dan musik bagi murid untuk menjadikan sang murid sebagai tenaga profesional. Kecenderungan pelatihan profesional inilah yang kemudian menjadikan seni musik dan gimnastik kehilangan status sebagai media pendidikan umum ketika dimasukinya zaman Romawi.
Bagi bangsa Yunani pada zaman Klasik, seni rupa memiliki kedudukan yang lebih rendah dibanding dengan musik dan puisi. Hal ini disebabkan karena profesi sebagai pelukis, pematung, arsitek, atau pengrajin kurang bergengsi dan dianggap tidak selayaknya menjadi profesi para kaum bangsawan. Profesi sebagai pelukis, pematung, atau pengrajin pada umumnya diturunkan dari ayah ke anak atau melalui kegiatan pemagangan di sanggar. Meskipun demikian, diperoleh informasi bahwa pendidikan seni rupa dalam bentuk menggambar diberikan di sekolah umum tingkat dasar. Disebutkan bahwa di Sicyon, Peloponesus, pada pertengahan abad ke-4 SM, di sekolah dasar yang hanya diikuti oleh murid laki-laki, diberikan pelajaran menggambar dengan obyek figur manusia (Hubbard 5).
Menurut Aristoteles, pelajaran menggambar merupakan mata pelajaran ekstra, sebagai tambahan dari mata pelajaran pokok seperti sastra, gimnastik, dan musik dengan tujuan menjadikan murid mampu menilai keindahan tubuh manusia. Diajarkannya menggambar figur manusia atau lazim pula dikenal sebagai “menggambar model” di sekolah umum ini tentunya tidak lepas dari pandangan bangsa Yunani yakni: “seni rupa sebagai tiruan alam” dan “manusia adalah bentuk alam yang paling sempurna.”
Plato tentang Pendidikan Seni
Cemas menghadapi pengaruh kaum sofis, Plato menulis bukunya yang terkenal Republic yang berisi sarannya untuk mereformasi masyarakat melalui pendidikan “pengawal republik.” Menurutnya, negara hanya mungkin dipimpin oleh orang yang paling sanggup secara fisik dan kejiwaan. Bukan karena keturunan atau kekayaan, tetapi karena pendidikan yang komprehensif.
Plato menempatkan seni sebagai bagian integral dari upaya pendidikan pengawal republik tersebut. Tetapi sebelum kita menyimak pandangannya tentang pendidikan seni, perlu kita memahami keterbatasan pandangannya tentang seni.
Bagi Plato, realitas yang hakiki adalah yang dapat ditemukan di dalam wujud ideal yang bersifat abadi dan hanya dapat dipahami melalui latihan nalar. Ia memberi contoh dengan ilustrasi “tiga tempat tidur.” Ide tentang tempat tidur bersifat abadi dan diciptakan oleh tuhan dan karena itu merupakan wujud yang paling benar. Tempat tidur yang kedua adalah yang diciptakan oleh tukang kayu yang kita lihat pada dunia kenyataan. Tempat tidur yang ketiga adalah yang tampak pada lukisan. Tempat tidur yang dibuat oleh tukang kayu bersifat nyata tetapi sesungguhnya hanyalah merupakan tiruan dari tempat tidur ideal yang tak dapat dilihat. Dengan demikian, tempat tidur yang tampak pada lukisan, tak lebih dari “tiruan dari tiruan,” dan karena itu ia jauh dari bentuk ideal. Itulah sebabnya ia merupakan “sesuatu yang tak layak dipercaya sebagai pengetahuan yang benar.”
Mengapa Plato berpendapat bahwa seni seharusnya menyatakan “kebenaran”? Jawabnya: karena kebenaran sangat penting dan penelitian secara rasional amat diperlukan oleh penjaga republik agar dapat berlaku arif terhadap negara. Plato menyadari bahwa mendengarkan puisi atau menyaksikan karya arsitektur dan patung merupakan suatu kenikmatan yang dapat dirasakan oleh warga negara tetapi hal itu tidaklah cukup untuk dijadikan dasar bagi keefektifan karya seni. Kenyataan bahwa seni merupakan “tiruan dari tiruan” seperti yang ditunjukkan oleh lukisan dan, karena itu dicurigai. Hanyalah seni musik yang bukan merupakan tiruan dari tiruan karena musik tidak meniru alam tetapi meniru kebenaran yang hakiki secara langsung. Itulah sebabnya seni musik menduduki posisi yang terhormat dalam dunia pendidikan.
Meskipun seni rupa potensial uantuk menyesatkan, Plato tidak berupaya untuk menghilangkan seni rupa dalam kegiatan pendidikan. Seni yang tepat, dianggap dapat berdampak positif bagi perkembangan anak. Ia menyadari bahwa kemampuan rasional anak tidak cukup kuat untuk memungkinkan mereka berhubungan dengan kebenaran yang hakiki. Karya seni yang menirukan kebenaran tersebut dapat memberi manfaat karena ia dapat memasuki jiwa melalui perasaan sebelum kematangan kemampuan rasional anak terbentuk. Plato menyatakan: “Let our artists be those who are gifted to discern the true nature of the beautiful and the graceful. Then will our youth dwell in the land of health, amid fair sights and sounds, and receive the good in everything (Republic III, 400-01) (Efland, A History, 15).
Aristoteles tentang Pendidikan Seni
Pandangan Aristoteles tentang seni berpijak pada konsepsi mengenai realitas yang berbeda dari pandangan Plato yang menjadikan pandangannya tentang pendidikan seni berbeda pula. Bagi Aristoteles, tidak ada dunia yang berbeda bagi setiap wujud. Segala sesuatunya di alam ini memiliki sifat yang universal yang dapat dipersepsi secara langsung. Karakter universal ini adalah kualitas yang secara bersama dimiliki oleh suatu kelompok wujud (misalnya manusia, kambing, pohon, dsb). Selain itu, Aristoteles juga menyadari adanya sifat khas dari setiap wujud. Untuk manusia misalnya, keunikan ini membentuk kepribadian seseorang. Seseorang dapat memiliki hidung yang lebih mancung dari pada orang lain, telinga yang lebih lebar, rambut yang lebih ikal, dsb. Meski demikian, ia masih dikenal sebagai manusia.
Aristoteles menyanggah tuduhan Plato bahwa puisi dan jenis seni yang lain kurang layak sebagai sumber kebenaran. Bagi Aristoteles, dengan menyajikan pengalam universal, seorang penyair memokuskan pada pengetahuan yang sungguh penting.
Dalam kaitannya dengan proses artistik, berikut ini adalah perbandingan antara pendapat Plato dan Aristoteles. Bagi Plato, proses artistik berarti meniru sesuatu yang telah ada sebelumnya. Peniruan itu sendiri tidak pernah secara penuh menyamai model yang ditiru. Bagi Aristoteles, seniman adalah peniru yang terampil. Meskipun karya seni meniru alam, karya tersebut bersifat unik. Seni bukanlah “tiruan dari tiruan” sebagaimana yang diyakini Plato tetapi merupakan tempat representasi yang sesungguhnya dapat terjadi. Untuk menciptakan suatu karya seni, seorang haruslah mengetahui dinamika alam dan psikologi. Pemberian keterampilan dalam seni adalah lebih dari sekedar penguasaan media. Seniman mestilah juga mengetahui sebab akibat di alam, motivasi, serta akibat dari tindakan manusia. Bila tidak, mereka tidak dapat menghasilkan tiruan yang meyakinkan.
Aristoteles juga menyadari efek karya seni. Ia menyadari bahwa penonton memperoleh rasa nikmat dari drama meskipun drama tersebut menampilkan hal yang menakutkan dan menyedihkan. Kegiatan tersebut bahkan dapat berfungsi melepas ketegangan yang ada dalam diri penonton.
Aristoteles memandang musik dan puisi bersifat mendidik moral manusia. Sekalipun demikian ia tidak membatasi pada pendidikan bagi orang muda tetapi juga bagi manusia dewasa. Aristoteles memandang kebudayaan yang mencakup drama, sastra, dan musik sebagai wahana pendidikan kewarganegaraan serta pengisi waktu luang.
Pada bukunya Politics Aristoteles mengidentifikasi empat cabang pengajaran yakni membaca, menulis, gimnastik, musik, dan menggambar. Pengajaran membaca/menulis dan menggambar dianggap penting karena manfaatnya dalam kehidupan. Latihan gimnastik penting karena kemampuannya untuk menumbuhkan keberanian. Sedangkan pengajaran musik penting karena ia memberikan kenikmatan intelektual yang bersifat intrinsik. Meskipun Aristoteles sependapat dengan anggapan yang berkembang pada zamannya bahwa nilai musik terletak pada kenikmatan intelektual yang ditawarkannya, Aristoteles menganggap perlu untuk mencari alasan yang lebih bermakna dalam pengajarannya (tidak hanya sekedar demi kenikmatan), tetapi lebih jauh, tujuan sesungguhnya dari pendidikan musik adalah kebaikan moral.
Pada masa Romawi, amat sedikit pembahasan mengenai pendidikan musik atau seni rupa. Dalam diskursus pendidikan di Romawi digunakan istilah ars atau artes yang mengacu pada berbagai kegiatan profesional. Istilah pendidikan liberal arts yang populer dewasa ini (bersumber dari istilah artes liberales) mencakup disiplin ilmu pengobatan, retorika, musik, ilmu ukur, berhitung, dialektika, astronomi, sastra, dan hukum. Menggambar dan mematung tidak termasuk di dalamnya.
Keruntuhan Romawi menandai dimulainya Abad pertengahan. Kekacauan yang terjadi karena tidak adanya pemerintahan yang kuat membawa pengaruh bagi dunia kesenian. Penguasa yang menjadi sponsor karya seni menghilang yang menjadikan kehidupan seniman morat-marit. Untungnya pada masa ini, gereja tampil sebagai pusat kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan terutama untuk mencetak biarawan (meskipun juga menerima putra bangsawan untuk dididik). Kegiatan pendidikan di lingkungan gereja yang berkaitan dengan seni yakni pelatihan dalam hal menulis indah, menghiasi halaman buku, menjilid buku, dan mengerjakan kerajinan emas. Metode pendidikan yang diterapkan sangat menekankan pelatihan teknik dengan tujuan membentuk pribadi yang terampil yang dapat menggunakan keterampilannya untuk mengagungkan Tuhan; bukan demi ekspresi atau kepentingan pribadi (Efland, A History 21).
Pendidikan seni dalam konteks pendidikan umum pada masa Renaisan tercermin pada sekolah lanjutan yang disponsori oleh kaum humanis. Kaum humanis sangat menghargai seni karena ia merupakan salah satu aspek yang penting dalam tradisi klasik. Di sekolah kaum humanis ini, pendidikan estetis diberikan dengan tujuan agar murid dapat mengapresiasi keindahan karya sastera, arsitektur, atau drama dari masa lalu (klasik), suatu hal yang tidak terjadi pada Abad Pertengahan. Pendidikan apresiasi seni inilah kemudian yang mendorong timbulnya penghargaan terhadap seniman perupa yang sebelumnya hanya dipandang sebagai tak lebih dari tukang yang terampil. Maka pembagian “seni murni” dan “seni pakai” pun kemudian digunakan. Kaum humanis sangat berhasil dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya mempelajari kelompok ilmu humaniora. Diyakini oleh mereka bahwa ilmu humaniora penting dalam rangka pendidikan moral dan kewarganegaraan.
Pandangan bahwa seorang yang berpendidikan seyogyanya memiliki dasar pengetahuan seni (dan juga ilmu humaniora lainnya) sebagaimana yang dianjurkan oleh kaum humanis tetap berpengaruh kuat pada masa sesudahnya. John Locke yang hidup pada abad ke-17 misalnya, merekomendasikan bahwa seorang jentelmen perlu memiliki kemampuan menggambar yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-harinya. Kemampuan menggambar yang dianjurkannya tidaklah mesti sempurna (Efland, A History 49). Pada abad ke-17 di Eropah memang meluas anggapan di kalangan elit bahwa seorang gadis tidaklah lengkap pendidikannya bila ia tidak mengecap pelatihan yang mengarahkannya untuk menjadi seorang wanita yang beretiket dan terampil untuk hal-hal tertentu. Sebagai seorang yang akan terjun dalam pergaulan kaum terhormat, maka ia harus tahu bagaimana cara yang sopan untuk duduk, makan, berdansa, dan terampil mengerjakan hal yang agung dan halus seperti menggambar, menyulam, atau merancang busana. Pandangan ini kemudian menyebar pula di Amerika-Serikat terutama di kalangan menengah ke atas.
Pandangan bahwa menggambar merupakan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seseorang dalam upaya kelengkapan pribadinya, kembali ditegaskan oleh Benyamin Franklin dari Amerika Serikat seabad kemudian. Franklin tidak membatasi bagi kaum elit saja, tetapi bagi semua orang. Baginya kemampuan menggambar amat diperlukan bagi seseorang untuk mengomunikasikan ide. Hanya saja, gagasan ini tidak terimplementasikan di sekolah di Amerika Serikat pada masa itu.
Awal abad ke-19 di Eropah dan Amerika Serikat merupakan masa yang penting dalam dunia pendidikan formal sehubungan dengan diperkenalkannya sekolah umum negeri (public school) yang didirikan oleh pemerintah dalam upaya pemberian pendidikan massal untuk mencerdaskan warganegara. Pada sekolah negeri ini, pendidikan seni yang mencakup musik vokal dan menggambar termasuk dalam kurikulum. Horace Mann, seorang tokoh pendidik di Amerika-Serikat menuliskan: Drawing may go hand in hand with music; so may the cultivation of libraries and the cultivation of a taste for reading, etc, Every pure taste implanted in the youthful mind becomes a barrier to resist the allurement of sensuality” (Efland, A History 74). Jelaslah, pendidikan seni dipandang sebagai bagian dari pembentukan pribadi ideal.
Pengajaran menggambar dan seni musik di sekolah negeri pada masa ini amat dipengaruhi oleh pandangan Johann Heinrich Pestalozzi. seorang tokoh pendidik dari Swiss. Metode pengajaran menggambar yang
Pestalozzi tentang Pendidikan Seni
Pestalozzi meyakini bahwa orang belajar dengan cara “mendengarkan suara,” baik yang diucapkan maupun yang dinyanyikan; “mempelajari bentuk” yang mencakup pengukuran dan menggambar; dan akhirnya “mempelajari angka.” Pada setiap kegiatan terdapat perkembangan alamiah dari rasa yang sederhana ke yang abstrak. Pengukuran amat penting artinya dalam memperjelas rasa tersebut. Dari pengukuran suara seorang akan menuju pada upaya mempelajari irama musik, sedang dari pengukuran bentuk, ia akan mempelajari geometri dan menggambar.
Pestalozzi berusaha untuk menemukan metode pengajaran yang dapat mengembangkan potensi semua anak. Ia setuju dengan Rousseau yang beranggapan bahwa “alam adalah guru yang terbaik.” Menurutnya, dasar dari kegiatan belajar adalah mengembangkan rasa, suatu yang yang diterima seseorang dari alam. Alam baginya adalah sumber kebenaran, dan kebenaran tersebut ditangkap melalui rasa. Lebih lanjut ia meyakini adanya perkembangan alamiah yang memungkinkan seseorang, dalam proses belajarnya, untuk mencerna alam.
diperkenalkan oleh Pestalozzi di sekolah didasarkan pada prinsip pemberian latihan dari yang sederhana ke yang rumit. Menurutnya, dalam pelajaran menggambar murid harus menguasai elemen-elemen yang sederhana dalam menggambar seperti membuat garis, sudut, dan lengkungan sebelum menggambar obyek yang rumit. Ia mengeritik metode menggambar dengan langsung meniru karya-karya seniman besar seperti yang umum dilakukan di akademi-akademi seni rupa di Eropah pada masa itu. Dengan metodenya itu, ia berharap semua anak, tanpa kecuali, mampu mengembangkan kemampuannya dalam menggambar. Ilmu perspektif (ilmu tentang cara menggambarkan sesuatu sehingga tampak sebagaimana yang dilihat oleh mata) amat penting dalam metode menggambar Pestalozzi. Bila murid telah menguasai teknik-teknik dasar menggambar dasar, barulah ia diberi kesempatan untuk menggambar secara langsung benda-benda yang ada di alam sekitar. Metode menggambar Pestalozzi pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan murid dalam menggambarkan apa yang dilihat oleh matanya. Jadi melatih koordinasi tangan dan mata. Metode menggambar seperti ini amat populer di dalam pelajaran menggambar di sekolah dasar pada masa permulaan abad ke-19. Dengan metode ini, menggambar mencontoh yakni menggambar berdasarkan contoh gambar yang ditunjukkan oleh guru dianggap positif oleh karena amat efektif untuk melatih koordinasi mata dan tangan. Adapun penilaian terhadap gambar anak didasarkan pada keakuratan dan kebersihan gambar.
Asselbergs dan Knoop (1995; 5) menuliskan tentang apa yang dilakukan oleh murid dalam kegiatan menggambar di sekolah di Belanda berdasarkan pendekatan ini, sebagai berikut:
“...mereka belajar menggambarkan garis lurus, sudut, segi empat, lengkungan, dan lingkaran untuk kemudian menggambarkan bentuk tiga-dimensional yang lebih rumit... Karena guru pada umumnya tidak cukup terampil dalam hal menggambar seperti yang harus dilakukan ini, maka mereka sangat tergantung pada buku pegangan yang berfungsi sebagai alat bantu mengajar.”
Buku pegangan yang diungkap oleh Asselbergs dan Knoop tersebut meluas digunakan di Amerika dan Eropah. Gaitskell dan Al Hurwitz (1975; 34) menulis tentang tujuan yang ingin dicapai buku pegangan guru semacam ini sebagai berikut:
(1) Melatih mata dalam hal keakuratan pengamatan terhadap bentuk, ukuran, dan proporsi serta ketepatan penggambaran berdasarkan jarak dan sudut pandang.
(2) Melatih tangan utuk menggores secara bebas dan cepat.
(3) Melatih ingatan dalam menggambarkan secara akurat bentuk dan pengaturan obyek.
(4) Mempertajam kepekaan terhadap bentuk.
Buku pelajaran menggambar dengan tujuan seperti disebutkan di atas tidak hanya digunakan di Eropah dan Amerika saja, tetapi juga di Asia seperti misalnya di Jepang, khususnya pada tahun 1872-1885 saat berbagai buku yang mempromosikan teknik menggambar pensil corak Barat, marak digunakan di sekolah (Foster; 1992, 104).
Froebel yang mendapat pengaruh dari Pestalozzi, kemudian mengembangkan metode pengajarannya sendiri yang dianggap cocok untuk murid Taman Kanak-kanak dan sekolah dasar. Dalam metode pengecatan yang diajarkannya, anak diminta untuk mengisi warna pada pola-pola tertentu. Warna yang diberikan diharapkan jelas, rata, dan tidak melewati garis batas pola (Tarr 117).
Di Inggris, Australia, Swedia, Belanda, dan Amerika-Serikat, pengajaran menggambar kemudian lebih diarahkan pada upaya memberikan keterampilan yang relevan dengan tuntutan industri misalnya keterampilan merancang berbagai bentuk produk sehingga murid kelak dapat bekerja di pabrik (Kauppinen x). Lahirlah istilah “menggambar industri (industrial drawing)” yang mengacu pada gambar teknik yang dibuat dengan menggunakan alat bantu semacam mistar, jangka, dsb., atau gambar bebas yang yang diniatkan sebagai motif-hias untuk barang produksi/industri. Salah seorang tokoh pengajaran menggambar untuk keperluan industri ini adalah Walter Smith dari Inggeris yang juga membantu pelaksanaan pengajaran menggambar di Amerika-Serikat.
Walter Smith tentang Menggambar
Walter Smith, seorang ahli dalam bidang menggambar industri dari Inggeris, diundang ke Amerika-Serikat pada tahun 1871untuk memimpin pelaksanaan pelajaran menggambar di sekolah di Massachusetts, sebuah negara bagian yang pada tahun 1864 mewajibkan pelajaran menggambar di sekolah umum(Eisner dan Ecker, Readings 3).
Menurut Walter Smith, fungsi menggambar dalam pendidikan umum adalah untuk mengembangkan keakuratan persepsi dan mengembangkan imajinasi. Oleh karena itu, ia akan menghasilkan keteraturan dan keorisinilan. Pelajaran menggambar yang bersifat edukatif merupakan cara untuk mendalami mata pelajaran lain seperti geografi, sejarah, mekanika, dan disain. Pada pendidikan umum, gambar seharusnya dipandang sebagai alat dan bukan hiasan.
Dalam kaitannya dengan menggambar industri, praktik menggambar perlu dimiliki oleh seseorang agar ia memiliki keterampilan industri serta cita-rasa yang baik. Gambar menurut Smith adalah cerminan dari fikiran. Gambar yang bagus atau buruk bukanlah suatu kebetulan karena apa yang terlihat itulah yang ada dalam fikiran yang kemudian tersalurkan melalui goresan tangan di atas kertas atau kanvas.
2 Masa Modern
2.1 Pendidikan Seni Rupa
Lahirnya konsepsi baru tentang anak di penghujung abad ke-19 yang memandang anak sebagai pribadi yang unik yang berbeda dengan orang dewasa, membawa konsekuensi bagi pengajaran menggambar di sekolah. Metode pengajaran menggambar yang menekankan pada koordinasi mata dan tangan yang populer pada masa itu kemudian dipertanyakan. Metode ini dianggap memperlakukan anak sebagai mana layaknya orang dewasa. Kebutuhan untuk mengembangkan program pengajaran menggambar yang mengacu pada perkembangan alamiah anak, kemudian dirasakan.
Terbitnya berbagai jurnal ilmiah dalam bidang pendidikan seni rupa pada masa itu merangsang terjadinya pertukaran ide yang pada gilirannya memberi dampak bagi perkembangan dunia pengajaran menggambar. Sejalan dengan dimasukinya abad ke-20, pengajaran menggambar yang pada mulanya hanya menekankan pada pelatihan keterampilan koordinasi mata dan tangan, mulai ditinggalkan.
Pendekatan baru ini mencoba untuk menawarkan program yang mengacu pada perkembangan alamiah anak. Istilah pengajaran menggambar kemudian dirasa tidak sesuai lagi dan digantikan dengan istilah pendidikan seni rupa. Dengan istilah pendidikan seni rupa, cakupan pembinaan tidak lagi pada kegiatan menggambar semata, tetapi juga pada kegiatan mematung, mencetak, dan sebagainya, dan fokus pembinaan tidak lagi ditekankan pada aspek keterampilan saja tetapi juga pada pengembangan fungsi jiwa seperti kesensitifan dan kekreatifan.
Untuk melatih kesensitifan anak terhadap gejala keindahan, khususnya keindahan karya seni rupa, disiapkanlah buku yang berisi reproduksi karya seniman besar untuk diamati dan dibahas oleh anak. Oscar Neale, seorang pengembang buku apresiasi seni semacam ini dari Amerika Serikat merumuskan tujuan kegiatan apresiasi seni dalam konteks pendidikan seni rupa di sekolah sebagaimana yang dikutip oleh Eisner dan Ecker (1966, 6) sebagai berikut:
...untuk mengembangkan apresiasi pada diri anak kita di sekolah terhadap karya agung (masterpieces)dalam bidang seni rupa agar mereka merasakan kenikmatan yang lahir dari apresiasi semacam itu sehingga cita-citanya dipengaruhi oleh rasa patriotisme, simpati, keberanian, dan keindahan yang telah disumbangkan oleh seniman dari berbagai masa.
Kecenderungan baru yang terjadi dalam dunia pendidikan seni rupa di awal abad ke-20 tidak hanya dipengaruhi oleh ide-ide yang berkembang dalam dunia pendidikan sehubungan dengan banyaknya studi tentang dunia kejiwaan anak, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi dalam dunia kesenian, khususnya seni rupa.
Dalam dunia seni rupa, terjadi perubahan yang drastis pada penghujung abad ke-19 yang ditandai oleh lahirnya berbagai corak lukisan dan patung yang sama sekali berbeda dengan corak lukisan dan patung mimesis atau “peniruan alam” yang telah mentradisi. Perubahan yang terjadi ini didorong oleh semangat para pelukis dan pematung untuk tampil secara bebas. Ide kebebasan bagi anak untuk menyatakan diri ini, memberi inspirasi bagi pendidik dalam merancang kegiatan seni rupa anak di sekolah. Ide “eksperimen dengan berbagai bahan” yang diperkenalkan oleh kelompok perupa Bauhaus dari Jerman, juga amat berpengaruh terhadap pendidikan seni rupa. Menurut kelompok ini, seniman perupa amat perlu untuk bereksperimen dengan beragam bahan dalam rangka mengasah kekreatifannya. Pengaruh ide kelompok Bauhaus ini terhadap pendidikan seni rupa di sekolah terlihat pada diperkenalkannya berbagai bahan untuk dieksplorasi oleh murid.
Meningkatnya apresiasi terhadap seni modern pada waktu itu mengantarkan pada diakuinya karya seni rupa anak (gambar, patung, cetak) sebagai karya seni dalam arti yang sesungguhnya. Frank Cizek, seorang seniman dan pendidik seni rupa dari Austria, merupakan orang yang pertama kali mengakui secara terbuka nilai intrinsik karya seni rupa anak (Efland; 1990, 195). Cizek meyakini bahwa karya seni rupa anak adalah karya seni yang hanya mampu dihasilkan oleh anak. Untuk itu, karya anak semestinya dibiarkan tumbuh bagaikan bunga tanpa pengaruh orang dewasa (Macdonald; 1970, 341- 342). Ide bahwa anak seharusnya dibebaskan dari pengaruh orang dewasa dalam kegiatan penciptaan karya seni rupa agar dapat mengaktualisasikan dirinya, kemudian populer dengan istilah “pendekatan ekspresi-bebas” atau “pendekatan berbasis-anak.”
Bertolak dari pandangan di atas, pendidik seni rupa kemudian mulai menyadari bahwa metode yang harus digunakan dalam membimbing anak adalah metode yang mampu menyiapkan pengalaman belajar yang dapat merangsang ekspresi pribadi anak. Kegiatan pendidikan seni rupa kemudian dipandang sebagai alat untuk mengembangkan potensi ekspresi kreatif anak.
Pendekatan ekspresi-bebas kemudian dipromosikan secara luas oleh oleh dua orang tokoh pendidik seni rupa yang dikenal dalam dunia internasional yakni Herbert Read dari Inggris dan Viktor Lowenfeld dari Amerika Serikat. Herbert Read, dalam bukunya Education Through Art menegaskan bahwa ekspresi-bebas tak dapat diajarkan dan peranan guru hanyalah pendamping dan pemberi inspirasi. Viktor Lowenfeld dalam Creative and Mental Growth menekankan bahwa seni rupa bagi anak adalah media untuk menyatakan diri. Ide pendekatan ekspresi bebas yang mulai diperkenalkan oleh Cizek pada awal abad ke-20 kemudian menjadi populer di seluruh dunia, khususnya setelah Perang Dunia II (Kauppinen ; 1995, x-xi).
Pada tahun 1960 an, sebuah pendekatan baru yang dikenal dengan nama “pendekatan disiplin” (discipline-based art education approach yang biasa disingkat dbae) berkembang di Amerika Serikat. Berkembangnya pendekatan ini tidak terlepas dari gerakan pembaruan pendidikan di Amerika Serikat yang menginginkan lulusan yang berkualitas. Seperti diketahui, pada akhir tahun 1950 an, Amerika Serikat dikagetkan oleh kemampuan teknologi ruang angkasa Uni Soviet. Didorong oleh keinginan untuk menyaingi prestasi Uni Soviet pada waktu itu, bangsa Amerika ingin segera dihasilkannya orang yang berkualitas dalam berbagai bidang ilmu.
Dalam kaitannya dengan pendidikan seni rupa, disadari bahwa program pendidikan seni rupa di sekolah hanyalah asyik pada kegiatan ekspresi-bebas dan melupakan upaya mempelajari ilmu seni rupa, khususnya sejarah dan kritik seni rupa. Chapman (1978, 17) pendukung pendekatan baru ini, meyakini bahwa “pengembangan pribadi melalui ekspresi-bebas sama pentingnya dengan mempelajari ilmu seni rupa.” Pendekatan baru ini memandang seni rupa sebagai disiplin ilmu yang perlu dikuasai oleh murid dan pengajaran yang dilakukan seyogyanya disusun secara sistematis. Karena pendekatan ini berhasrat untuk meningkatkan kualitas pendidikan seni rupa melalui penguasaan disiplin ilmu seni rupa secara komprehensif, maka berbagai nama lain yang melekat padanya antara lain: pendekatan “pendidikan seni rupa berbasis isi,” “pendidikan seni rupa berkualitas,” dan “pendidikan seni rupa komprehensif.”
Greer (1987; 227) dari Universitas Arizona menyarankan agar isi dan praktik pendekatan disiplin ini: (1) menempatkan pendidikan seni rupa dalam konteks pendidikan umum dengan empat disiplin utama yakni estetika, kritik, sejarah, dan kreasi seni rupa; (2) menggunakan kurikulum yang sistematis dan berkelanjutan; dan (3) mengacu pada konteks kabupaten/distrik.
Rumusan tujuan umum pendidikan seni rupa di sekolah yang disusun oleh sebuah komite pendidik seni rupa yang diketuai oleh Brent Wilson dan dilegasisasi oleh Asosiasi Pendidik Seni Rupa Amerika (NAEA) pada tahun 1971, sebagaimana yang dikutip oleh Toffolon(1981,14-15) mencerminkan pandangan pendekatan disiplin:
Setelah mengikuti pendidikan seni rupa di sekolah, anak diharapkan untuk dapat:
(1) Mencerap dan menanggapi berbagai aspek seni rupa
(2) Menghargai seni rupa sebagai bentuk pengalaman manusia yang penting
(3) Menciptakan karya seni rupa
(4) Memiliki pengetahuan tentang seni rupa
(5) Memberikan penilaian terhadap kualitas artistik berbagai karya seni rupa.
Pendekatan disiplin segera menjadi populer terutama atas dukungan sebuah yayasan yang berkantor pusat di California yakni The Getty Center for Education in the Arts. Yayasan ini menyiapkan dana yang besar untuk mengembangkan teori dan kurikulum pendekatan disiplin, serta melatih guru dan pelaksana pendidikan lainnya dalam hal implementasi pendekatan disiplin di sekolah.
Kepopuleran pendekatan disiplin tidak hanya di Amerika tetapi juga di berbagai negara. Di Australia misalnya, pendekatan disiplin diterapkan di berbagai sekolah meskipun sedikit agak berbeda dengan yang diterapkan di Amerika Serikat. Di Australia, meskipun komponen yang mendukung disiplin ilmu seni rupa seperti sejarah dan kritik seni rupa diajarkan bersama-sama dengan praktik studio, kegiatan praktik studio lah yang paling dominan. Di Indonesia, meskipun istilah pendekatan disiplin tidak begitu populer di kalangan pendidik seni rupa, pada kenyataannya, kurikulum pendidikan seni rupa untuk sekolah umum (terutama kurikulum 1975) secara nyata merefleksikan ide pendekatan disiplin baik dari segi kekomprehensifan materi maupun dari segi struktur program.
Seiring dengan munculnya posmodernisme, sebuah pendekatan baru dalam pendidikan seni rupa tampil yakni “pendekatan pendidikan seni rupa multikultural.” Kaum posmodernis yang berupaya untuk mempromosikan keberagaman sosial-budaya dan kontekstualisme, keberatan dengan pendekatan disiplin yang mendasarkan program pendidikannya pada tradisi seni rupa Barat. Bagi mereka, tradisi seni rupa Barat tidak seharusnya menjadi satu-satunya acuan kebenaran. Bagi pendukung pandangan posmodernisme, keberagaman sosial-budaya harusnya menjadi pijakan pendidikan seni rupa. Menarik untuk dicatat, bahwa untuk merespon terhadap kritikan ini, pendukung pendekatan disiplin kemudian memperkenalkan “pendekatan disiplin generasi baru” yang berupaya untuk mengakomodasi keragaman budaya.
Benih-benih pendekatan pendidikan seni rupa multikultural sesungguhnya telah muncul di Amerika pada sekitar tahun 1920 an yang tercermin pada diperkenalkannya berbagai bentuk seni rupa etnis dalam program pendidikan seni rupa di sekolah. Tetapi upaya pengenalan itu hanyalah sekedar selingan saja, dan dalam konteks seni rupa modern. Dimasukkannya seni rupa tradisional pada kurikulum sekolah di beberapa negara Asia seperti yang diungkap pada butir 2.2 di atas, pada sisi lain, bertujuan untuk membangun kesadaran murid akan budaya mereka sendiri.
Upaya kaum posmodernis untuk mempromosikan seni rupa multikultural didukung oleh suasana yang kondusif yakni disadarinya perubahan komposisi penduduk yang amat drastis di berbagai negara, terutama di kota besar. Di New York pada awal tahun 1990 an, misalnya, murid sekolah dasar dan lanjutan dari kelompok etnis minoritas, telah mencapai 40% dan diperkirakan dalam waktu 10 tahun akan mencapai 50% (Sahasrabudhe; 1992. 42).
Meskipun pendekatan pendidikan seni rupa multikultural menolak dominasi tradisi seni rupa Barat, ia tidak berupaya untuk menghilangkan seni rupa Barat di sekolah. Pendekatan multikultural, menurut pendukungnya, tidaklah untuk mempersempit cakupan pendidikan seni rupa, tetapi memperluasnya dengan cara memasukkan berbagai tradisi seni rupa yang beragam. Itulah sebabnya, pendekatan pendidikan seni rupa multikultural akan memanfaatkan tradisi seni rupa dari manapun datangnya asalkan sesuai dengan konteks budaya lokal. Dengan demikian, pendekatan pendidikan seni rupa multikultural bersifat eklektik dalam pengembangan programnya.
Berikut ini adalah tujuan pendidikan seni rupa berdasarkan pendekatan multikultural yang dirumuskan oleh Carmen Armstrong (1990, 101):
(1) Untuk mengeksplorasi ide tentang posisi seni rupa dalam kehidupan masyarakat, dan kriteria yang digunakan dalam menilai karya seni rupa
(2) Untuk memahami posisi kesejarahan seni rupa dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, fantasi, dan keagamaan masyarakat
(3) Untuk memberi inspirasi dan mengarahkan cara berkreasi seni rupa
(4) Untuk memahami hubungan antara lokasi geografis dan media yang dipilih dalam menyatakan ide estetis
(5) Untuk mengenal hubungan yang memberi sumbangan bagi kualitas estetis karya seni rupa yang membentuk dan mengkomunikasikan makna.
Di Amerika Serikat, pendidik seni rupa pendukung pendekatan multikultural dengan amat bergairah memasukkan seni rupa etnik/tradisional dalam program pendidikannya. Berbagai program pendidikan seni rupa multikultural diperkenalkan. Fearon Teacher Aids dari Pitman Inc, sebagai contoh, menerbitkan pedoman kurikulum yang berjudul Native American Crafts Workshop untuk membantu guru memperkenalkan berbagai aspek budaya Indian Amerika di dalam pengajarannya. Program ini meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indian seperti kerajinan, musik, masakan, permainan dan upacara tradisional. Davis Publications Inc, menerbitkan Art from Many Hands: Multicultural Art Projects yang berisi berbagai gagasan pengajaran seni rupa tradisional dari berbagai penjuru dunia untuk mempromosikan pemahaman budaya di antara murid. Scholastic Inc, menerbitkan Crafts of Many Cultures yang berisi program pengajaran siap pakai bagi guru untuk memperkenalkan berbagai kegiatan studio dan apresiasi seni rupa tradisional.
Di Inggeris, wacana pendidikan seni rupa multikultural mewarnai dunia pendidikan seni rupa di sekolah sejak dekade 1990 an. Karena pendidikan seni rupa multikultural dianggap penting dan menyangkut hal yang sensitif dan tidak mudah dilaksanakan, beragam pedoman penyelenggaraan serta perangkat kurikulum diterbitkan. Berbagai pusat pendidikan seperti sekolah, museum atau galeri seni rupa merekrut seniman dari kaum minoritas untuk dijadikan sebagai nara sumber. Menurut Allison ( 1995, 148) di banyak kota besar di Inggris, sekolah yang jumlah muridnya dari kelompok minoritas cukup signifikan, umumnya melaksanakan program pendidikan seni rupa multikultural.
Di Australia, pendidik seni rupa pendukung pendekatan multikultural mengembangkan program yang relevan dengan kondisi Australia yang kehidupannya didominasi oleh budaya Barat sementara masyarakat asli Australia sendiri yakni aborigin, dalam berbagai hal terpinggirkan. Menarik untuk dicatat, bahwa pendidikan seni rupa dalam masyarakat aborigin merupakan hal yang sakral yang tidak memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur untuk ikut serta karena mereka tidak diperbolehkan untuk membuat motif-motif sakral dan simbolistis (Crosskell, Condous, dan Schapel; 1984, 167). Karena alasan inilah, program pendidikan seni rupa di sekolah untuk anak aborigin dibatasi pada pengetahuan dan teknik seni rupa non-sakral. Cynthia Venn, seorang pendidik seni rupa dari Pulau Elcho di Teritori utara, merancang program pendidikan seni rupa yang menggabungkan teknik seni rupa aborigin dengan gagasan ekspresi-bebas yang berakar pada budaya Barat. Tujuan program pendidikan seni rupa yang dirancang oleh Venn ini adalah untuk menjadikan anak aborigin ini mengenal cara berfikir orang Barat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka tanpa melupakan akar budaya aborigin sendiri. Di berbagai sekolah, seniman aborigin diundang untuk mendemonstrasikan keahliannya di kelas.
3
POKOK BAHASAN
PARADIGMA PENDIDIKAN SENI
BERBASIS ANAK, DISIPLIN, DAN KONTEKSTUAL
Untuk pokok bahasan “Paradigma Pendidikan Seni Berbasis Anak, Disiplin, dan Kontekstual, ” disiapkan bahan bacaan wajib untuk mahasiswa. Bahan bacaan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sofyan Salam, Pendidikan Seni Berbasis Anak;
2. Sofyan Salam, Pendidikan Seni Berbasis Disiplin;
3. Sofyan Salam, Pendidikan Seni Berbasis Kontekstual/Multikultural.
4. Sofyan Salam, Pendidikan Seni Kontekstual
Pengantar Diskusi
Untuk Sub Pokok Bahasan:
“PENDIDIKAN SENI BERBASIS ANAK”
(catatan: Meskipun tulisan ini hanya membahas secara spesifik salah satu jenis pendidikan seni yakni seni rupa, ide yang termuat di dalamnya pada dasarnya
juga teraplikasikan pada jenis pendidikan seni musik, seni tari, dan seni teater)
Pendidikan Seni Berbasis Anak,
tercermin pada “Pendekatan Ekspresi Bebas”
1. Pengantar
Pendekatan Ekspresi Bebas dalam Pendidikan Seni Rupa amat populer di Indonesia, khususnya di kalangan pendidik seni rupa. Istilah ini mendominasi wacana pendidikan seni rupa terutama pada dekade 1970 an sejalan dengan digantinya nama mata pelajaran “menggambar” menjadi “seni rupa” pada kurikulum sekolah. Perubahan nama ini dianggap perlu untuk disosialisasikan terutama menyangkut latar-belakang penggantian nama itu. Salah satu alasan utama mengapa mata pelajaran menggambar digantikan namanya karena pada mata pelajaran menggambar melekat citra sebagai pelatihan teknik ketrampilan belaka yang tidak peduli akan kebutuhan kejiwaan anak. Sesungguhnya ada upaya sebelumnya dari pendidik untuk menghilangkan citra pelajaran menggambar sebagai hanya sekedar pelatihan keterampilan seperti yang terungkap dalam buku Ekspresi dan kemungkinannya di SR tetapi upaya ini kurang begitu berdampak terhadap praktik pengajaran menggambar di kelas. Dengan nama seni rupa, diharapkan lebih mudah untuk memunculkan citra baru sebagai kegiatan pembelajaran yang peduli akan kebutuhan kejiwaan anak. Hal ini dimungkinkan karena seni rupa menawarkan beragam kegiatan.
2. Apakah Pendekatan Ekspresi Bebas Itu?
Pendekatan ekspresi bebas bercirikan pemberian kesempatan bagi anak untuk menyatakan dirinya secara tak terganggu melalui seni rupa dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini tidak lahir begitu saja. Ada keadaan yang melatarbelakanginya. Sebelum membahas konsep pendekatan ekspresi bebas, terlebih dahulu akan dibahas keadaan yang melatarbelakangi tersebut yang mencakup pendekatan yang lazim digunakan di sekolah sebelumnya, serta kondisi yang mendorong lahirnya pendekatan ekspresi bebas.
2.1 Latar Belakang Kelahiran
Ketika seni rupa untuk pertama kalinya diajarkan di sekolah umum dalam bentuk mata pelajaran “menggambar” pada permulaan abad ke-19, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan anak pandai menggambar yang tercermin pada kemampuannya untuk menirukan wujud apa yang terdapat di alam ini ke dalam bidang datar (Salam, 2001). Itulah sebabnya, pelajaran menggambar di sekolah mengutamakan koordinasi mata dan tangan. Apa yang diamati oleh mata dapat secara akurat diterjemahkan oleh tangan melalui goresan pensil atau pewarna lain. Semakin akurat citra yang digoreskan, semakin berhasillah gambar tersebut. Untuk itu, guru berupaya sekuat tenaga untuk menjadikan anak terampil menerjemahkan apa yang diamatinya ke atas bidang gambar melalui pemberian beragam latihan. Bagi anak yang duduk di kelas permulaan, latihannya berupa pembuatan goresan sederhana dalam berbagai variasinya seperti garis lurus, garis lengkung, segi tiga, segi empat, lingkaran, dan sebagainya. Bagi anak yang duduk di kelas lanjutan, diperkenalkan ilmu perspektif dan kegiatan menggambar alam secara langsung. Diyakini secara meluas pada abad ke-19 bahwa sifat keluguan gambar anak disebabkan karena mereka belum mendapatkan latihan yang sesuai yang memungkinkan berkembangnya keterampilan serta ketajaman matanya dalam mengamati obyek sehingga mampu melahirkan karya seni rupa yang bersifat naturalistis yang menjadi kecenderungan pada masa itu (Efland, tanpa tahun).
Ketika dunia industri memerlukan keterampilan menggambar untuk keperluan disain, maka pengajaran menggambar di sekolah pun mengikuti tren ini dengan pemberian materi pelajaran untuk keperluan industri. Di balik pergeseran orientasi ini, metode pengajaran menggambar yang digunakan pada dasarnya sama yakni bersifat direktif dengan latihan yang ketat agar anak terampil menggambar.
Metode pengajaran menggambar seperti disebutkan di atas, lambat laun dianggap tidak layak untuk dilakukan. Berbagai faktor yang menjadi pemicu lahirnya anggapan tersebut, antara lain temuan berbagai studi tentang anak, pengaruh pandangan Freud serta terjadinya gerakan pembaruan dalam dunia seni rupa.
2.1.1 Temuan Berbagai Studi tentang Anak.
Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ditandai oleh timbulnya perhatian peneliti untuk memahami dunia anak. Hasil temuan mereka membuka mata para pendidik, termasuk pendidik seni rupa. Henry Turner Bailey (Efland, tanpa tahun), seorang tokoh pendidik seni rupa pada masa itu menulis:”Paidology (ilmu tentang anak) mengungkapkan banyak hal kepada kita. Kini kita mulai menapaki jejak anak dalam pendidikan.” Uhlin (1972) menunjuk Corrado Ricci, seorang penyair Italia, sebagai pelopor penelitian terhadap karya seni rupa anak. Laporan Corrado Ricci tentang gambar anak yang diamatinya di bawah jembatan layang saat berteduh dari hujan di musim dingin 1882, merangsang minat peneliti untuk menelusuri makna ekspresi seni sebagai cerminan pengalaman anak. Khusus menyangkut perkembangan anak dalam menggambar, studi awal yang dilakukan oleh Lichtwark pada tahun1887 dan Baldwin pada tahun 1898 mencoba untuk menemukan kesamaan antara perkembangan anak dalam menggambar dengan teori evolusi umat manusia yang populer pada masa itu. Perkembangan kemampuan anak dalam menggambar disejajarkan dengan gambar di gua yang dibuat oleh manusia prasejarah dengan asumsi bahwa perkembangan kemampuan anak selanjutnya akan mengikuti pola perkembangan seperti yang secara evolusioner terjadi pada umat manusia.
Pada tahun 1892, James Sully seorang filosof dan psikolog Inggris, memulai memperkenalkan istilah skema (bagan) untuk menamai pola gambar anak yang sederhana sebagai simbol dari sesuatu. Selanjutnya pada tahun 1893, Earl Barnes dalam laporannya tentang gambar anak mencatat adanya fase perkembangan kemampuan anak dalam menggambar yang dikaitkan dengan usia. Tetapi, Herman Lukenslah pada tahun 1896 yang mula pertama menyusun fase perkembangan anak dalam menggambar berdasar perkembangan usia dengan uraian sebagai berikut: (1) Hingga masa 4 tahun anak berada pada tahap coreng-moreng; (2) Usia 4 hingga 8 tahun merupakan masa keemasan yang bercirikan menggambar sambil berceritera; (3) Usia 9 hingga 14 tahun merupakan masa kritis yang ditandai oleh timbulnya kesadaran baru anak yang membuatnya tidak lagi puas dengan gambar yang dihasilkannya. Perkembangan menggambarnya kemudian menjadi mandek; dan (4) Usia 14 tahun yang merupakan masa kelahiran kembali oleh munculnya kemampuan kreatif dari beberapa orang anak yang berbakat (Uhlin, 1972; 19). Peneliti yang lain, juga mencoba untuk menggambarkan pola perkembangan menggambar anak dengan versi yang berbeda antara lain oleh Max Verwon pada tahun 1907 dan Cyril Burt pada tahun 1921.
Selain pola perkembangan menggambar anak. Berbagai konsep kemudian lahir dari upaya penelitian terhadap dunia seni rupa anak. Sigfried Levenstein dari Leipzig memperkenalkan konsep “berceritera” (storytelling) bagi gambar anak, Max Verwon memperkenalkan istilah ideoplastik dan fisioplastik ( ideoplastic and physioplastic) dalam menggambarkan perkembangan gambar anak, William Stern menunjuk adanya hubungan antara menggambar dan perkembangan berbahasa.
Studi terhadap dunia seni rupa anak segera menyebar luas berkat terbitnya berbagai jurnal pendidikan seni rupa. Gagasan yang dimuat pada jurnal ini tentu saja merangsang terjadinya pertukaran fikiran diantara pendidik seni rupa yang kemudian menimbulkan kesadaran bahwa metode pengajaran menggambar di sekolah seyogyanya memperhatikan temuan ilmiah seperti adanya keunikan serta pola perkembangan anak dalam berkarya seni rupa. Kegiatan pembelajaran di sekolah hendaknya mempertimbangkan keunikan dan pola perkembangan tersebut. J.L Todd (dalam Logan, 1955), seorang kepala sekolah seni rupa di Philadelphia Amerika Serikat, misalnya, mempertanyakan mengapa anak tidak dibiarkan menggambarkan gajah, ayam, atau ikan jika memang mereka bisa melakukannya? Mengapa mereka harus diikat dengan aturan harus menggambarkan kubus, bulatan, atau berbagai bentuk abstrak lainnya?
2.1.2 Pengaruh Freud
Pandangan Freud, seorang psikolog terkemuka, yang memostulasikan bahwa alam bawah sadar dari seseorang merupakan sumber nyata dari motivasi, mendorong lahirnya pandangan di kalangan pendidik bahwa tugas utama sekolah adalah tidak menekan perasaan anak dan sebaliknya menyalurkannya ke arah yang positif. Margaret Naumberg, salah seorang pendidik seni rupa yang amat terpengaruh oleh pandangan Freud, menyatakan bahwa setiap larangan yang bersifat menekan bertentangan dengan temuan baru dalam bidang biologi, psikologi, dan pendidikan. Untuk itu, diperlukan cara yang bersifat konstruktif dan kreatif untuk mengarahkan kekuatan vital sang anak (Efland, 1990).
2.1.3 Terjadinya Gerakan Pembaharuan Seni Rupa
Pembaruan dalam dunia seni rupa yang besar dampaknya dalam pendidikan seni rupa pada akhir abad ke-19 adalah gerakan ekspresionisme. Ekspresionisme timbul sebagai reaksi terhadap seni rupa mimesis yang telah mentradisi didunia Barat sejak zaman klasik Yunani. Seni rupa mimesis berpijak pada pandangan bahwa seni rupa merupakan tiruan alam. Ini berarti, kualitas suatu karya seni rupa ditentukan oleh kepersisasannya dengan wujud yang ada di alam ini. Itulah sebabnya, karya seni rupa mimesis kemudian digolongkan sebagai karya naturalisme/realisme. Ekspresionisme menantang pandangan yang telah mentradisi ini dengan mengatakan bahwa seni rupa adalah wujud pernyataan perasaan atau isi batin. Pada ekspresionisme, isi batin dinyatakan secara emosional melalui goresan yang “liar” serta warna yang mencolok sebagaimana yang terlihat pada karya lukisan Vincent Van Gogh atau Henri Matisse (cek). Warna yang digunakan untuk menyatakan suatu bentuk tidaklah mesti sesuai dengan warna alamiah bentuk tersebut. Sang seniman bebas untuk memilih warna sesuai dengan keinginan subyektifnya sebagai cerminan dari kecemasan atau suasana hatinya yang bergelora. Semangat “kebebasan untuk menyatakan perasaan” yang digelorakan oleh kaum ekspresionis menyadarkan para pendidik seni rupa bahwa bila seniman dewasa dapat secara bebas menyalurkan perasaannya melalui goresan, warna, atau bentuk, mengapa anak dalam kegiatan menggambar atau melukisnya harus diatur secara ketat? Mengapa guru di sekolah tidak berusaha untuk mengikuti perubahan orientasi dalam dunia seni rupa dari upaya meniru gejala alam ke pemberian kebebasan untuk menyatakan perasaan secara subyektif? Bukankah masyarakat luas tampaknya juga dapat menerima perubahan ini? Akhirnya, karya seni rupa/gambar anak yang spontan dan naif, diakui sebagai karya seni rupa yang sejajar dengan karya orang dewasa (Wilson, 1997). Sesungguhnya, pengakuan terhadap karya seni rupa anak telah ada pada tahun 1830 an seperti yang terungkap pada tulisan Rodolpho Topffer yang mengatakan bahwa anak menggambarkan alam bukanlah sebagai representasi dari alam yang dipandang sebagai keindahan tetapi sebagai cerminan dari keinginan yang meskipun kelihatannya kasar tetapi ia lahir dari kekuatan fikiran (Leeds, 1989). Hanya saja pengakuan Topffer yang sangat maju pada zamannya ini relatif tidak memberi pengaruh terhadap dunia pendidikan seni rupa.
Ketiga faktor yang telah disebutkan di atas, secara bersama-sama melahirkan kesadaran baru di kalangan pendidik untuk mengadakan reformasi terhadap praktik pengajaran seni rupa/menggambar yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi alamiah anak. Maka lahirlah pendekatan baru yang kemudian populer dengan nama pendekatan ekspresi bebas.
2.2. Konsep Dasar Pendekatan Ekspresi Bebas
Perlunya ekspresi anak untuk disalurkan dalam kegiatan pendidikan telah banyak disuarakan oleh peneliti dan pendidik seni rupa pada akhir abad ke-19 sebagai dampak dari temuan ilmiah dan perkembangan dunia seni. Tetapi Franz Cizek lah yang disebut sebagai bapak dari pendekatan ekspresi bebas dalam pendidikan seni rupa. Franz Cizek lahir pada tahun 1865 dan memasuki Vienna Academy of Fine Art pada usia 20 tahun. Sejak masih kuliah, ia telah mulai tertarik pada seni rupa anak seperti yang tercermin pada koleksinya. Ketertarikan Cizek pada seni rupa anak erat hubungannya dengan pandangan pribadinya sebagai seniman yang mendapatkan pengaruh pandangan modernisme yang memang mulai bangkit pada masa itu. Ia bersama kelompoknya melakukan pembangkangan terhadap seni rupa yang bersifat akademik dan memperjuangkan kehadiran seni rupa non-realistis yang kreatif (Efland, tanpa tahun). Pada tahun 1897 ia berhasil mendapatkan izin untuk mendirikan lembaga pendidikan seni rupa untuk anak yang kemudian diintegrasikannya pada Vienna School for Arts and Crafts (Kunstgewerbeschule) pada tahun 1904. Ia mengajar di tempat ini hingga pensiun pada usia 73 tahun (Efland 1990).
Franz Cizek dipandang sebagai bapak dari pendekatan ekspresi bebas berkat pandangan dan apa yang dipraktikkannya di tempat ia mengajar. Ia mengatakan bahwa “seni rupa anak adalah seni rupa yang hanya bisa diciptakan oleh anak” dan “gambar anak haruslah diberi kebebasan untuk tumbuh bagaikan kembang, bebas dari gangguan orang dewasa “ (Macdonald, 1970) Pernyataan Franz Cizek yang mengatakan “metode adalah racun bagi seni rupa” merupakan tonggak bagi pendekatan ekspresi bebas. Di kelas yang dibinanya, ia tidak memberi petunjuk kepada anak kecuali mereka memintanya. Apa yang diberikannya hanyalah simpati dan pengertian untuk merangsang imajinasi anak. Cizek tidak setuju bila anak meniru bentuk alam atau pergi ke museum untuk mengamati karya seniman terkemuka oleh karena menurutnya, ekspresi kreatif haruslah berasal dari dalam diri anak sendiri (Efland, tanpa tahun).
Pandangan Franz Cizek tentang “kegiatan-sendiri” anak dalam berkarya seni rupa sangat berpengaruh di Amerika Serikat dan Eropah pada tahun permulaan abad ke-20. Ide bahwa anak harus dibebaskan dari pengaruh orang dewasa dalam proses berkaryanya, kemudian menjadi populer dengan nama “pendekatan ekspresi bebas” atau “pendekatan ekspresi kreatif.” Dengan pendekatan ekspresi bebas, tugas guru adalah memberikan pengalaman kepada anak yang dapat merangsang munculnya ekspresi pribadi sang anak. Cara yang ditempuh oleh guru antara lain dengan memberikan beragam pengalaman atau membantu anak untuk mengingat pengalaman pribadinya yang tersembunyi.
Pendekatan ekspresi bebas yang diperkenalkan oleh Cizek kemudian dikembangkan dan lebih dipopulerkan oleh dua orang tokoh pendidik seni rupa yang juga memiliki reputasi internasional yakni Viktor Lowenfeld dan Herbert Read.
Amat sulit untuk meringkaskan pandangan Viktor Lowenfeld tentang pendidikan seni rupa. Lowenfeld melaui bukunya yang terkenal The Nature of Creative Activity dan Creative and Mental Growth, pada dasarnya memusatkan perhatiannya pada pertumbuhan mental dan kreatif anak dan memandang bahwa seni rupa merupakan suatu wahana yang dapat digunakan untuk memudahkan pertumbuhan tersebut. Viktor Lowenfeld sangat dipengaruhi oleh pandangan Freud yang menempatkan seni rupa sebagai wujud ekspresi dari dorongan alam bawah sadar. Seni rupa berdasarkan pandangan ini dapat dianggap sebagai indikator kesehatan jiwa dan ekspresi seni rupa merupakan terapi pembersihan jiwa. Bagi Lowenfeld, ekspresi seni rupa yang dilaksanakan secara alamiah berdampak positif bagi perkembangan intelektual, emosional, kreatifitas dan perkembangan sosial anak. Pendidikan seni rupa menurut Lowenfeld seyogyanya menjadi ajang pemberian pengalaman yang menarik yang menyadarkan anak akan lingkungannya. Pendidikan seni rupa, sebagaimana dikatakannya hendaknya memperhatikan proses pembelajaran yang terjadi pada diri anak. Pendidik harus mengamati apa yang terjadi pada anak saat ia sedang bergelut dengan media seni rupa. Anak adalah yang utama sedang seni rupa sendiri hanyalah suatu alat. Lowenfeld juga memandang bahwa lomba seni rupa selayaknya tidak dilakukan (Eisner, 1966: 12). Dilontarkannya gagasan yang menghubungkan antara seni rupa dan kesehatan mental ini timbul oleh karena disadari bahwa melalui kegiatan berolah seni rupa, seseorang dapat menyalurkan perasaan, keprihatinan, dan kecemasannya melalui media seni rupa yang mungkin tidak dapat tersalurkan melalui media yang lain. Lowenfeld mengatakan bahwa anak yang mengalami frustasi pada mata pelajaran lain seperti membaca, mengarang. Atau berhitung, dapat mengalihkan kegiatannya pada seni rupa untuk melepas frustasinya itu oleh karena pada seni rupa tidak dikenal jawaban yang benar atau salah (1972; 8).
Herbert Read terkenal dengan gagasannya education through art yang menekankan bahwa naluri berolah seni rupa bagi anak adalah suatu yang universal, sesuatu yang tumbuh secara alamiah pada diri anak dalam mengomunikasikan dirinya. Orang dewasa atau pendidik, tidak seyogyanya mengintervensi hal tersebut melalui berbagai dalih seperti demi “adat-istiadat,” “persaingan kerja,” “pembentukan karakter,” atau “pendisiplinan jiwa.” Menurutnya, semua itu akan secara nyata menggusur minat alamiah anak yang akan berarti merusak kebahagiaan dan kesenangan anak dalam menikmati kebebasan (Read, 1978: 10). Pendeknya, ekspresi-diri tak bisa diajarkan dan peranan guru hanyalah sebagai fasilitator.
2.3 Implementasi Pendekatan Ekspresi Bebas
Pendekatan ekspresi bebas secara murni diimplementasikan oleh pendidik seni rupa yang dalam merancang kegiatannya pembelajarannya menggunakan model emerging curriculum yakni kegiatan pembelajaran yang tidak dirancang sebelumnya tetapi berkembang sesuai keinginan anak. Dengan cara ini, guru menanyakan kepada anak kegiatan apa yang ingin dilakukannya dan kemudian menyiapkan segala sesuatunya untuk memberikan kemudahan bagi anak dalam melaksanakan kegiatannya itu. Ada kemungkinan, oleh karena satu dan lain hal anak tiba-tiba berubah fikiran, maka guru pun harus segera menyesuaikan diri dengan keinginan sang anak. Implementasi pendekatan ekspresi bebas semacam ini tentu saja cocok dilakukan di sanggar seni yang bersifat non-formal Untuk sekolah formal yang memiliki kurikulum serta jadwal yang ketat, sulit untuk dilakukan.
Karena menyadari sulitnya menerapkan pendekatan ekspresi bebas secara murni di sekolah, maka pendidik seni rupa mengembangkan pendekatan ekspresi bebas yang bersifat “terarah.” Dengan pendekatan yang terarah ini, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tetapi dengan siasat tertentu agar supaya anak dapat mengekspresikan dirinya sesuai dengan apa yang diharapkan. Siasat tersebut berupa kegiatan “pemanasan” untuk merangsang dan memberikan motif berekspresi kepada anak. Kegiatan pemanasan atau biasa pula disebut pemberian motivasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: (1) Berceritera atau berdialog dengan anak untuk membangkitkan perhatian dan merangsang lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya. Tema ceritera atau dialog tentu saja yang menyentuh kehidupan anak. Ceritera atau dialog akan menarik bila guru memperlihatkan foto, gambar, atau film; (2) memberikan anak pengalaman kontak langsung dengan alam secara sadar misalnya dengan mengajak anak untuk mencermati keadaan sekelilingnya yang mungkin selama ini diabaikan seperti detail bunga-bungaan yang tumbuh di sekeliling sekolah, kawat listrik dan telpon yang simpang-siur, pejalan kaki serta kendaraan yang lalu-lalang. Untuk mengarahkan perhatian anak, guru dapat mengajukan pertanyaan seperti: “berapa meter tinggi tiang listrik?” “”bagaimana sikap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan?” atau “berapa centimeter diameter kembang matahari yang ada di halaman sekolah?” (4) mendemonstrasikan proses poenciptaan karya seni rupa yang akan diajarkan. Pemberian motivasi kepada murid dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat (kurang dari 5 menit) akan tetapi dapat pula dilaksanakan dalam waktu 10-15 menit. Pembangkitan motivasi dalam bentuk kontak langsung dengan alam memerlukan waktu yang relatif lama akan tetapi kegiatan ini dapat dirangkaikan dengan kegiatan lain (misalnya darmawisata) sehingga tidak perlu mengambil waktu yang tersedia untuk praktik di kelas. Pada saat menjelang praktik, guru tinggal memancing ingatan murid tentang apa yang telah diamatinya untuk membangkitkan motivasinya.
Setelah anak termotivasi, maka anak pun diminta untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. Peran guru pada saat berlangsungnya ekspresi tersebut adalah mendampingi murid untuk memberikan bantuan dan pujian bila diperlukan. Dalam kaitannya dengan penilaian karya anak, maka tentu saja guru harus kembali ke filosofi pendekatan ekspresi bebas yakni “ekspresi anak bersifat unik dan alamiah dan tidak ada istilah benar dan salah dalam mengekspresikan dirinya melalui seni rupa.” Penilaian yang diberikan bersifat apresiatif, yakni bersifat menerima dan menghargai apa yang diungkapkan atau diciptakan oleh anak dengan menunjukkan kemungkinan peningkatan kualitas dari karya yang diciptakannya tersebut.
Topik Diskusi:
Persoalan dalam Penerapan Pendidikan Seni Berbasis Anak (pendekatan Ekspresi Bebas)
Harap mempersiapkan diri untuk diskusi dengan topik tersebut di atas!
Pengantar Diskusi
Untuk Sub Pokok Bahasan:
“PENDIDIKAN SENI BERBASIS DISIPLIN”
(catatan: Meskipun tulisan ini hanya membahas secara spesifik salah satu jenis pendidikan seni yakni seni rupa, ide yang termuat di dalamnya pada dasarnya
juga teraplikasikan pada jenis pendidikan seni musik, seni tari, dan seni teater)
1. Pengantar
Sebagai istilah, “Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin” yang dalam literatur berbahasa Inggris dikenal dengan nama Discipline Based Art Education (DBAE) kurang begitu dikenal di Indonesia. Hal ini tercermin secara jelas pada wacana pendidikan seni rupa di Indonesia yang mulai bergairah sejak dekade 70 an sejalan dengan digantinya istilah “Menggambar” pada kurikulum sekolah menjadi “Seni Rupa.” Dalam wacana tersebut, istilah “Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin,” absen. Para pendidik seni rupa, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, begitu terpesona dengan “Pendidikan Seni Rupa Ekspresi Bebas” dan dengan bersemangat mempopulerkannya di mana-mana. Begitu asyiknya mengkampanyekan pendekatan ekspresi bebas ini, sehingga mereka tidak menyadari bahwa kurikulum pendidikan seni rupa di sekolah, khususnya Kurikulum 1975, sesungguhnya berpijak pada pendekatan yang berbeda yakni pendekatan Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin. Kurangnya bahan referensi di Indonesia menyangkut pendekatan ini, merupakan faktor utama ketidakpopulerannya.
2. Apakah Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin itu?
2.1 Latar Belakang Kelahiran
Meskipun semangat Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin mendasari dimasukkannya mata pelajaran seni rupa (mulanya hanya mata pelajaran menggambar) di sekolah pada permulaan abad ke-19, istilah Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin belumlah dikenal. Istilah ini barulah digunakan pada dekade 1960 an menandai munculnya ketidakpuasan sebagian pendidik seni rupa di Amerika Serikat terhadap Pendekatan Ekspresi Bebas yang mendominasi kegiatan pendidikan seni rupa di Amerika Serikat sejak maraknya Gerakan Pendidikan Progresif pada dekade 1920 an. Pendekatan Ekspresi Bebas memandang fungsi seni rupa di sekolah adalah untuk memberi kesempatan yang luas kepada anak untuk menyatakan kekreatifan dan melepaskan emosinya. Seni rupa dipandang bukan sebagai subject-matter untuk dipelajari tetapi merupakan media untuk menyehatkan pertumbuhan mental dan kreatif anak. Ketidakpuasan sebagian pendidik seni rupa ini lantaran Pendekatan Ekspresi Bebas dianggap telah menjadikan praktik pendidikan seni rupa hanya sebagai ajang bagi anak untuk sekedar bermain-main sehingga malas untuk berfikir serta mempelajari ilmu seni rupa secara lengkap. Bahkan lebih jauh, pendekatan ekspresi bebas dipandang telah menjerumuskan pendidikan seni rupa ke lembah anti estetis. Demi menyalurkan emosi anak melalui seni rupa secara bebas, kualitas artistik karya anak tidak lagi dipedulikan.
Lahirnya pendekatan Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin pada dekade 1960 an tidak terlepas dari suasana batin bangsa Amerika, yang pada akhir tahun 1950 an, dikejutkan oleh prestasi Uni Sovet dalam teknologi ruang angkasa dengan diluncurkannya pesawat Sputnik. Prestasi Uni Sovet ini mendorong bangsa Amerika untuk segera menghadirkan pendidikan yang berkualitas dalam berbagai disiplin ilmu. Terhadap pelaksanaan pendidikan seni rupa di sekolah yang pada masa itu hanya dipandang sekedar memberikan keasyikan kepada anak untuk bermain sambil berekspresi, reformasi terasa amat perlu dilakukan. Greer dan Silverman (1987/1988; 11) membandingkan antara pelaksanaan pendidikan seni rupa dengan pendidikan bidang studi lain di sekolah dasar sebagai berikut:
Mata pelajaran di sekolah dasar umumnya diajarkan secara konsisten, berkelanjutan, dan peduli pada materi pelajaran; dan guru mendorong anak untuk mempelajarinya secara sungguh-sungguh. Tetapi untuk mata pelajaran seni rupa, bila itu ada, biasanya digunakan sebagai kegiatan selingan dari mata pelajaran yang menuntut keseriusan. Guru pun tidak begitu peduli untuk mengembangkan pemahaman dan apresiasi anak terhadap dunia seni rupa.
Rendahnya pengetahuan anak tentang seni rupa terungkap pada laporan penelitian Elliot Eisner terhadap 1000 orang siswa sekolah lanjutan yang berasal dari berbagai daerah di Amerika Serikat. Pada penelitian ini, terungkap bahwa sebagian besar siswa tidak memahami makna istilah yang paling elementer dalam seni rupa seperti hue, value, medium, opaque; serta tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang seniman perupa dunia yang terkenal seperti Rembrandt, Picasso, atau Matisse (Barkan, 1966). Opini mereka pun tentang seni rupa amat mengecewakan. Dua pertiga dari siswa yang diteliti berpendapat bahwa karya seni rupa yang bermutu hanyalah ditentukan berdasarkan selera pribadi; dan 35% siswa ragu atau tak yakin bahwa seni rupa penting bagi kemajuan bangsa (Barkan, 1966).
Untuk mengembalikan pendidikan seni rupa ke khittahnya, maka lahirlah pendekatan “ Discipline Based Art Education (DBAE) ” atau pendekatan “Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin.” Pendekatan ini mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh Pendekatan Ekspresi Bebas dengan menawarkan program pendidikan seni rupa yang lebih komprehensif yakni tidak hanya terbatas pada kegiatan mengekspresikan diri atau menciptakan karya seni rupa saja, tetapi juga pada kegiatan mempelajari ilmu seni rupa secara teoritis serta membahas dan menilai karya seni rupa secara kritis dan apresiatif. Itulah sebabnya pendekatan yang menampilkan multi-wajah seni rupa ini biasa pula disebut sebagai “Pendekatan Komprehensif.” Karena pendekatan ini didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seni rupa, maka ada pula yang menyebutnya sebagai “Pendekatan Kualitas.” Nama lain yang diberikan adalah “Pendekatan Isi.” Nama ini didasari pertimbangan bahwa pendekatan ini banyak bergelut pada isi ilmu seni rupa. Masih ada nama lain yang diberikan kepada pendekatan ini yakni “Pendekatan Rasional Ilmiah.” Nama yang terakhir ini diberikan oleh Arthur Efland ( 260) dengan alasan, pendekatan ini memandang seni rupa sebagai sebuah rumpun ilmu atau disiplin yang mesti dikuasai, dan pengajaran seni rupa mestilah terstruktur secara sistematis.
2.2 Konsep Dasar
Dipandangnya seni rupa sebagai disiplin ilmu, merupakan asumsi pokok yang mendasari konsep pendekatan ini. Disiplin ilmu dalam pengertian ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dobbs (1992; 9) adalah bidang studi yang bercirikan: (1) memiliki isi pengetahuan (body of knowledge), (2) adanya masyarakat pakar yang mempelajari ilmu tersebut, serta (3) tersedianya metode kerja yang memasilitasi kegiatan eksplorasi dan penelitian. Bagi pendukung Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin, seni rupa sangat pantas diposisikan sebagai sebuah disiplin ilmu.
Pendukung Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin berpendapat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Chapman (1978), bahwa pendidikan seni rupa yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan emosinya adalah penting, tetapi jangan karena itu, kegiatan mempelajari ilmu seni rupa diabaikan. Untuk itulah cakupan pendidikan seni rupa perlu diperluas. Eisner (1987/1988) dalam suatu wawancara yang dimuat pada Educational Leadership, sebuah jurnal pendidikan terkemuka di Amerika, menegaskan bahwa Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin bertujuan untuk menawarkan program pembelajaran yang sistematik dan berkelanjutan dalam empat bidang yang digeluti orang dalam dunia seni rupa yakni bidang penciptaan, penikmatan, pemahaman, dan penilaian. Keempat bidang ini terjabarkan pada mata ajaran: studio/produksi seni rupa, kritik seni rupa, sejarah seni rupa, dan estetika. Keempat bidang tersebut haruslah tercermin pada kurikulum. Anak hendaknya tidak hanya diberi kesempatan untuk berekspresi/ menciptakan karya seni rupa tetapi mereka juga perlu mempelajari bagaimana caranya menikmati suatu karya seni rupa. Tidak hanya itu, mereka juga perlu memahami konteks dari sebuah karya seni rupa dari berbagai masa. Lebih jauh, Eisner mengemukakan bahwa keempat mata ajaran tersebut tidaklah mesti diajarkan secara terpisah. Bahkan disarankan untuk mengajarkannya secara terpadu. Sebagai contoh, dalam kegiatan pembelajaran untuk memperkenalkan anak tentang teknik koil dalam pembuatan pot tanah liat, misalnya, guru dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk mengembangkan kepekaan anak akan proporsi, teknik, serta karakter ekspresif dari sebuah karya pot. Selanjutnya, pot tanah liat yang dibuat oleh anak dapat dikaitkan dengan pot yang dihasilkan oleh berbagai budaya (Cina, Jepang, Yunani, Aztecs, Perancis, dsb.). Dengan cara tersebut, melalui kegiatan yang relatif sederhana yakni membuat pot dengan teknik koil, wawasan seni rupa anak akan diperkaya dan diperluas.
Karena Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin merupakan suatu pendekatan dan bukan merupakan suatu metode yang spesifik, maka ia tampil dalam wujud yang bervariasi. Dibalik sifatnya yang bervariasi, Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin memiliki ciri khusus yakni: (1) seni rupa diajarkan sebagai sebuah subyek dalam konteks pendidikan umum dengan kurikulum yang tertulis serta disusun secara sistematis mencakup kegiatan ekspresi/kreasi, teori, dan kritik/apresiasi seni rupa. Pelajaran tersebut membangun pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam disiplin seni rupa yang memungkinkan untuk dievaluasi secara tepat; (2) Kemampuan anak dikembangkan untuk mampu menghasilkan karya seni rupa (studio/produksi seni rupa); menganalisis, menafsirkan, dan menilai kualitas karya seni rupa (kritik seni rupa); mengetahui dan memahami peran seni rupa dalam masyarakat (sejarah seni rupa); serta memahami keunikan karya seni rupa dan bagaimana orang memberikan penilaian dan menguraikan alasan penilaian tersebut (estetika); dan (3) Seni rupa diimplementasikan pada tingkat kabupaten dengan dukungan masyarakat, staf pengembang, nara sumber, dan program penilaian (Dobbs, 1992).
Dobbs (1992; 71- 76) menguraikan secara terinci cakupan keempat mata ajaran yang disebutkan di atas yang seyogyanya mendapatkan perhatian guru: (1) Studio/produksi seni rupa adalah disiplin dalam hal penciptaan seni rupa yang merupakan proses kreatif melalui pengolahan beragam materi untuk menciptakan efek rupa (visual) yang diinginkan. Amat banyak aspek produksi seni rupa yang dapat dieksplorasi, dipelajari, dan dialami oleh anak seperti pengenalan alat/bahan/teknik; motivasi, sikap kerja seniman dalam berkarya, pengekspresian rasa keindahan rupa, serta pembahasan karya seniman; (2) Kritik seni rupa adalah disiplin yang memokuskan perhatian pada persepsi dan deskripsi untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang diamati pada suatu karya seni rupa; analisis dan penafsiran untuk menjelaskan makna dari apa yang diamati tersebut, serta penilaian yang menggambarkan kualitas karya yang diamati; (3) Sejarah seni rupa adalah disiplin yang memokuskan perhatian pada peran seni rupa dan seniman dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Beragam aspek yang tercakup dalam sejarah seni rupa yang dapat dieksplorasi seperti fungsi dan corak karya, ikonografi, perkembangan, saling keterpengaruhan, riwayat hidup seniman, dsb; (4) Estetika adalah disiplin yang mendiskusikan hakikat dan makna seni rupa, pengalaman keindahan dan sumbangannya terhadap kehidupan dan kebudayaan manusia. Estetika dalam konteks pembelajaran di sekolah haruslah disesuaikan dengan tingkat kematangan intelektual dan kejiwaan anak. Bahasa yang digunakan bukanlah bahasa canggih sebagaimana yang lazim digunakan oleh filosof.
Dari uraian singkat tentang Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin di atas, terlihat dengan jelas bahwa perbedaan antara pendekatan Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin dengan pendekatan Ekspresi Bebas tidak hanya terletak pada kekomprehensifan cakupan kegiatan yang ditawarkan, tetapi juga pada bagaimana filosofi program dan cara membelajarkan anak. Pada pendekatan Ekspresi Bebas, anak diperlakukan secara istimewa dengan membiarkannya untuk secara bebas menyatakan apa yang ingin diekspresikannya. Guru tidak diizinkan untuk mengadakan intervensi. Peran guru hanyalah memberi kemudahan bagi anak dalam berekspresi. Maka lahirlah kurikulum yang dikenal dengan nama emerging curriculum, suatu kurikulum yang tidak siap pakai tetapi disusun mengikuti keinginan anak pada suatu kegiatan pembelajaran. Anaklah yang menentukan mengenai pengalaman belajar apa yang akan dilakukannya. Berdasarkan keinginan sang anak, maka guru pun menyiapkan fasilitas. Pada Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin, seperti yang telah disebutkan, kurikulum yang digunakan bersifat siap pakai dengan program yang tersusun secara sistematis. Dengan mengacu pada kurikulum siap pakai inilah, guru melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Jeffers membandingkan kedua pendekatan ini dengan menggunakan metafora “pertumbuhan alamiah” dengan metafora “pembentukan.” Metafora pertumbuhan alamiah mengandaikan anak sebagai sekuntum bunga atau tanaman, guru sebagai tukang kebun, dan sekolah sebagai kebun (18). Guru sebagai tukang kebun haruslah menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga anak sebagai tanaman tumbuh secara subur dan alamiah. Pada sisi lain, metafora pembentukan memandang anak sebagai tanah liat dan guru adalah pematung. Gurulah yang amat menentukan bentuk dari sang tanah liat. Anak sebagai tanah liat tidak berada pada posisi untuk memilih atau menolak bentuk akhir dari dirinya sendiri.
Pengaruh pendekatan Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin di Amerika Serikat amat luar biasa. Hal ini terlihat pada diadopsinya dasar pemikiran pendekatan ini pada tujuan pendidikan seni rupa di sekolah. Rumusan tujuan umum pendidikan seni rupa di sekolah yang disusun oleh sebuah komite pendidik seni rupa yang diketuai oleh Brent Wilson dan dilegasisasi oleh Asosiasi Pendidik Seni Rupa Amerika (NAEA) pada tahun 1971, sebagaimana yang dikutip oleh Toffolon(1981,14-15) mencerminkan pandangan pendekatan Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin yang berhasrat untuk menawarkan program yang komprehensif yang mencakup kegiatan studio/produksi seni rupa, kritik seni rupa, sejarah seni rupa, serta estetika. Pada rumusan tujuan tersebut secara tegas dinyatakan bahwa pendidikan seni rupa mengharapkan anak untuk dapat: (1) Mencerap dan menanggapi berbagai aspek seni rupa; (2) Menghargai seni rupa sebagai bentuk pengalaman manusia yang penting; (3) Menciptakan karya seni rupa; (4) Memiliki pengetahuan tentang seni rupa; (5) Memberikan penilaian terhadap kualitas artistik berbagai karya seni rupa.
Diadopsinya dasar pemikiran pendekatan Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin dalam perumusan tujuan pendidikan seni rupa di sekolah yang bersifat nasional di Amerika serikat yang kemudian berdampak terhadap program pendidikan seni rupa di kelas, tidak terlepas dari kesesuaiannya dengan tuntutan masyarakat Amerika akan pendidikan yang berkualitas dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Masyarakat telah mengalami ketidakpercayaan terhadap lembaga pendidikan dan karena itu menuntut agar uang yang telah dibelanjakan oleh sekolah sebanding dengan kualitas lulusan yang dihasilkan.
Pengaruh Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin di Amerika Serikat tidak terlepas pula dari peran The Getty Center for Education in the Arts, sebuah yayasan dengan dana yang luar biasa besar yang memiliki kepedulian terhadap upaya pengembangan pendidikan seni. Dalam upayanya mengembangkan pendidikan seni, The Getty Center for Education in the Arts yang didirikan pada tahun 1982, memiliki kebijakan khusus yakni memilih sebuah pendekatan dalam pendidikan seni yang direkomendasikan oleh penasihatnya, dan memberikan bantuanya sepenuh hati. The Getty Center for Education in the Arts memilih pendekatan Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin dan memberikan bantuanya untuk memajukan pendekatan ini melalui kegiatan advokasi, pengembangan kurikulum, implementasi program di sekolah, pengembangan profesional bagi guru dan staf administrasi baik melalui pendidikan prajabatan maupun penataran guru, dan yang tak kalah pentingnya adalah pengembangan teori melalui kegiatan penelitian dan publikasi.
Kepopuleran pendekatan Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di berbagai negara. Di Australia misalnya, pendekatan disiplin diterapkan di berbagai sekolah meskipun sedikit agak berbeda dengan yang diterapkan di Amerika Serikat. Di Australia, meskipun komponen yang mendukung disiplin ilmu seni rupa seperti sejarah dan kritik seni rupa diajarkan bersama-sama dengan praktik studio, kegiatan praktik studio lah yang dominan. Di Indonesia, seperti telah disinggung di bagian awal tulisan ini, meskipun istilah pendekatan Pendidikan Seni Rupa Berbasis Disiplin tidak populer di kalangan pendidik seni rupa, pada kenyataannya, kurikulum pendidikan seni rupa untuk sekolah umum (terutama kurikulum 1975) secara nyata merefleksikan ide pendekatan ini baik dari segi kekomprehensifan materi maupun dari segi struktur program.
Topik Diskusi:
Persoalan dalam Penerapan Pendidikan Seni Berbasis Disiplin
Harap mempersiapkan diri untuk diskusi dengan topik tersebut di atas!
Pengantar Diskusi
Untuk Sub Pokok Bahasan:
“PENDIDIKAN SENI BERBASIS MULTIKULTURAL”
(catatan: Meskipun tulisan ini hanya membahas secara spesifik salah satu jenis pendidikan seni yakni seni rupa, ide yang termuat di dalamnya pada dasarnya
juga teraplikasikan pada jenis pendidikan seni musik, seni tari, dan seni teater)
1. Pengantar
Akhir-akhir ini, konsep pendidikan multikultural semakin gencar dipromosikan. Ia merupakan wujud dari keinginan untuk merayakan keragaman budaya dan sosial. Keinginan ini memang sangatlah beralasan terutama dalam ruang lingkup pendidikan formal yang sejak dari awalnya diwarnai oleh budaya Barat, khususnya budaya renaisan dan modernisme. Warna budaya Barat pada pendidikan formal merupakan sesuatu yang alamiah karena secara historis pendidikan formal memang dilahirkan, tumbuh, dan berkembang dalam tradisi Barat. Ketika bentuk pendidikan formal ini kemudian diadopsi di berbagai belahan dunia yang lain termasuk Indonesia, warna budaya Barat yang melekat padanya ikut pula teradopsi.
Hasrat untuk merayakan keragaman budaya dalam dunia pendidikan tidak lahir begitu saja. Ada berbagai faktor yang mendorongnya. Demikian pula ketika hasrat tersebut terkristalisasi dalam konsep “pendidikan multikultural,” berbagai faktor penghambat menghadang implementasinya. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti pendidikan multikultural dalam bidang pendidikan seni rupa dengan fokus pada konsep dan persoalannya.
2. Apakah Pendidikan Seni Rupa Multikultural itu?
Sebelum menjawab pertanyaan mengenai apakah pendidikan seni rupa multikultural itu, pertama-tama penulis akan menjelaskan istilah “pendidikan multikultural” yang merupakan payung dari “pendidikan seni rupa multikultural.” Istilah “pendidikan multikultural” telah banyak didefinisikan orang. Bullivant (dalam Davidman, 1996/1997: 67) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai: “…to teach about the many social groups and their different designs for living in a pluralistic society.” (untuk mengajarkan tentang banyak kelompok sosial dan perbedaan cara hidupnya di dalam masyarakat yang pluralistik). Definisi tersebut di atas, berpijak pada pengertian budaya yang dianut oleh Bullivant sebagai “… a social group’s design for survival in and adaptation to its environment.” ( Cara suatu kelompok sosial untuk mempertahankan diri dan beradaptasi dengan lingkungannya). Definisi Bullivant tersebut dikeritik oleh Davidman sebagai definisi yang sempit dan mengingkari sejarah, khususnya sejarah pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Menurut Davidman, pendidikan multikultural bukanlah berangkat dari definisi budaya ke konsepsi dan operasionalisasi pendidikan multikultural tetapi ia lahir dari perjuangan terhadap ketidakadilan ekonomi, rasial, dan jender. Atas dasar inilah, Davidman menyetujui definisi pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Banks yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah “ an educational reform movement that is concerned with increasing educational equity for a range of cultural and ethnic groups” (Gerakan reformasi pendidikan yang memberikan perhatian kepada peningkatan kesamaan dalam bidang pendidikan terhadap beragam kelompok budaya dan sosial) (dalam Davidman, 1996/1997:68).
Kedua definisi tersebut di atas pada dasarnya memiliki semangat yang sama yakni keduanya ingin melepaskan lembaga pendidikan dari dominasi satu budaya (yang secara tradisional diperani oleh budaya Barat) dan selanjutnya berupaya mempromosikan keragaman budaya dengan cara membuka diri terhadap berbagai budaya lain yang lahir atas dasar suku, ras, agama, kelas sosial, jenis kelamin, pandangan, atau kondisi tertentu.
Bertolak dari esensi pendidikan multikultural tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa pendidikan seni rupa multikultural merupakan “sebuah pendekatan pendidikan untuk mempromosikan keragaman budaya melalui kegiatan penciptaan, penikmatan dan pembahasan keindahan rupa (visual).
2.1 Latar belakang kelahiran
Pendidikan seni rupa multikultural lahir sebagai salah satu bagian dari pendidikan multikultural. Ada berbagai faktor yang secara bersama-sama melatar belakangi kelahiran pendidikan multikultural yakni:
2.1.1 Ketidakadilan dalam Masyarakat
Pendidikan multikultural lahir di awal tahun 1960 an di tengah gencarnya gerakan hak sipil di Amerika Serikat (Efland, Freedman, dan Stuhr, 1996). Gerakan hak sipil ini berlangsung secara besar-besaran melalui demonstrasi di jalan-jalan setelah perjuangan melalui kantor pemerintah, lembaga legislatif, dan ruang pengadilan tidak membuahkan hasil. Mereka memperjuangkan persamaan hak, keadilan politik, dan kemudahan untuk mereformasi keadaan. Pendidikan multikultural dipandang sebagai cara yang tepat untuk mereformasi sistem pendidikan agar mampu merespon tuntutan masyarakat akan pendidikan yang adil bagi semua kelompok ras, suku, dan budaya. Seperti diketahui, kehidupan sosial di Amerika Serikat pada masa itu sangat didominasi oleh orang kulit putih, sementara orang kulit hitam dan kulit merah, terpinggirkan. Dominasi ini tentu saja tidak terlepas kemampuan orang kulit putih dalam membangun supremasinya di Amerika Utara sejak kedatangan mereka dari Eropa ratusan tahun yang lalu.
Dominasi suatu suku, ras, atau golongan tertentu inilah yang juga menjadi pemicu lahirnya gerakan pendidikan multikultural di berbagai belahan dunia yang lain. Allison (1995: 145), seorang pendidik seni rupa dari Inggris menuliskan:
In the late 1960s and early 1970s, my dissatisfaction with the then-current conception of art education, based predominantly on peculiarly western notions of child art and creativity, led me to look to art as it was produced and experienced in the “real world,” that is the world outside of schools as I felt that it was on this that an education in art should properly be based…People’s actual and potential involvement in or experiences with art are diverse. (Di penghujung tahun 1960an dan awal tahun 1970an, ketidakpuasan saya terhadap konsep pendidikan seni rupa pada masa itu, yang berpijak pada pandangan barat tentang seni rupa anak dan kekreatifan, mendorong saya untuk mengamati seni rupa sebagaimana yang dihasilkan dan dialami dalam “dunia nyata” yakni dunia di luar sekolah, yang saya rasakan seharusnya menjadi dasar bagi pendidikan seni rupa…Keterlibatan atau pengalaman orang secara aktual dan potensial dalam seni rupa adalah beragam).
Karena ketidakadilan yang ikut merasuk ke dunia pendidikan ini tidak juga pupus, meskipun diakui terjadi perbaikan kondisi di sana-sini, konsep pendidikan multikultural terus tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika perkembangan zaman pada dekade 70 an, 80 an, 90 an, hingga dewasa ini. Ia dikembangkan dan diperjuangkan tidak hanya oleh pendidik dari kelompok yang tertindas tetapi juga dari mereka yang secara kebetulan memiliki latar belakang kelompok dominan.
2.1.2 Kebutuhan akan Identitas-diri
Sejalan dengan keinginan untuk menciptakan sistem kehidupan politik, sosial, dan ekonomi yang lebih adil bagi semua, muncul pula kebutuhan akan identitas-diri bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan peluang untuk menyatakan identitas-dirinya. Kebutuhan akan identitas-diri ini disuarakan oleh budayawan dan pendidik yang semakin menyadari bahwa lembaga pendidikan mestilah menghormati warisan budaya muridnya dan bahwa murid mempunyai hak untuk mengetahui warisan budayanya dan membangun rasa kebanggaan akan budayanya itu. Para budayawan dan pendidik ini mencemaskan pengaruh budaya global yang secara sistematis menggusur budaya lokal atau kelompok yang senantiasa terpaksa harus menerima standar atau nilai yang didiktekan oleh budaya global agar bisa bertahan hidup. Kecemasan ini dapat dipahami oleh karena budaya lokal memiliki keunikan masing-masing karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebutuhan dan cara kelompok pendukungnya mengatur dan memecahkan persoalan hidupnya. Pemaksaan standar atau nilai global ini sangat dirasakan di dunia ketiga yang lantaran kemiskinan dan ketidakberdayaannya terpaksa membiarkan budaya, kepercayaan, dan pandangan yang secara tradisional diyakininya terpinggirkan oleh nilai baru yang asing.
Salah satu peluang untuk menyatakan identitas-diri ini adalah melalui kegiatan seni rupa. Kegiatan seni dianggap potensil oleh karena ia mampu mengekspresikan identitas-diri kelompok secara alamiah. Melalui seni rupa, simbol budaya, mitos, keyakinan, ketakutan, dan harapan dari suatu kelompok dapat dinyatakan secara efektif dan otentik. Seni rupa juga mencerminkan kecerdasan lokal dalam pemanfaatan bahan dan teknik yang tersedia untuk menafsirkan pengalaman budaya yang khas. Identitas-diri sebagai cerminan suatu budaya, memanglah dibangun melalui proses pendidikan. Salah satu faktor yang melatari kelahiran pendidikan seni rupa multikultural adalah dirasakannya kebutuhan, bagi kelompok yang secara budaya tersisih, untuk mengenal dan menjadikannya bangga akan identitas-dirinya.
2.1.3 Keadaan Demografis yang Berubah.
Mobilitas penduduk yang terjadi secara besar-besaran dewasa ini sebagai akibat kebijakan politik (internasional, nasional, lokal) dan desakan ekonomi yang ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi/komunikasi, berpengaruh besar terhadap perubahan komposisi penduduk terutama di negara maju dan di kota besar. Negara maju dan kota besar dengan berbagai fasilitas yang ditawarkannya, menjadi tujuan pemukiman yang menarik bagi orang yang ingin mengembangkan karirnya ataupun sekedar mengadu nasibnya. Tidak mengherankan bila kemudian negara maju dan kota besar mengalami perubahan komposisi penduduk. Amerika Serikat sebagai sebuah negara maju yang memiliki kebijakan keimigrasian yang relatif terbuka, khususnya sebelum peristiwa 11 September yang menimpa WTC, menunjukkan perubahan komposisi penduduk yang amat dinamik. Sebagai gambaran, jumlah murid sekolah dasar dan menengah yang dikenal sebagai kelompok minoritas di Amerika Serikat, telah mendekati jumlah 50% pada penghujung dekade 90 an (Schults, 1996/1997).
Gambaran komposisi penduduk di kota besar, seperti yang terlihat di Jakarta, menunjukkan semakin beragamnya latar belakang budaya, ras, suku, agama, dari penduduk dan semakin terdesaknya penduduk asli (Betawi).
Perubahan komposisi penduduk ini berdampak terhadap dunia pendidikan. Program pendidikan yang ditawarkan diharapkan seyogyanya peduli terhadap kondisi dan latar belakang murid. Kesadaran akan perlunya mempertimbangkan latar belakang budaya murid, secara alamiah melahirkan pendidikan seni rupa multikultural di sekolah.
2.1.4 Keinginan untuk Menghilangkan Prasangka Buruk
Disadari bahwa dalam masyarakat, terdapat persepsi yang tidak valid terhadap kelompok etnis atau budaya tertentu. Kesadaran ini, misalnya, disuarakan oleh Dewan Nasional untuk Studi sosial di Amerika Serikat dengan menyebutnya sebagai salah satu faktor mengapa pendidikan multikultural penting dilaksanakan (NCSS, 1996/1997). Ketidakvalidan persepsi ini diyakini akan melahirkan prasangka buruk terhadap anggota dari kelompok etnis atau budaya tersebut. Hal yang keliru ini tidak seharusnya dibiarkan karena akan berpengaruh bagi terbukanya kesempatan bagi anggota kelompok etnis atau budaya yang diprasangkai dalam mengembangkan diri dan karirnya. Lebih jauh, hal ini akan menciptakan ketidakharmonisan suasana pergaulan antarkelompok dalam masyarakat. Kesadaran akan perlunya menghilangkan prasangka buruk terhadap suatu kelompok etnis dan budaya inilah, merupakan salah satu pendorong kelahiran pendidikan seni rupa multikultural. Seorang kepala sekolah, sebagaimana dikutip oleh Nieto (1996/1997: 59) mengatakan:” Hadiah yang paling berharga yang dapat diberikan kepada murid (melalui pendidikan multikultural) adalah sikap toleransi terhadap perbedaan.”
2.1.5 Konsekuensi Munculnya Seni Rupa Posmodernisme
Secara historis, pendidikan seni rupa di lembaga formal berpijak pada (1) konsep seni rupa mimesis yang berakar dari tradisi klasik/renaisan Eropa dan kemudian disusul dengan (2) konsep seni rupa modern. Konsep seni rupa mimesis terimplementasikan dalam bentuk pembelajaran yang bersifat penciptaan, penikmatan, dan pembahasan karya seni rupa tiruan alam (naturalistis/realistis) sedang konsep seni rupa modern terimplementasikan dalam bentuk pembelajaran yang bersifat penciptaan, penikmatan, dan pembahasan karya seni rupa kreatif (formalistis atau ekspresionistis).
Munculnya seni rupa posmodernisme melahirkan tuntutan bagi dunia pendidikan untuk mengakomodasi konsep ini dalam program pembelajarannya. Posmodernisme yang kelahirannya juga didorong oleh keinginan untuk merayakan keragaman sosial dan budaya, menolak dominasi seni rupa mimesis dan modern dalam pembelajaran di sekolah. Bagi pendukung seni rupa posmodernisme, tidak ada makna atau kebenaran tunggal, kecuali yang dibangun oleh semua pihak yang berusaha untuk memahami seni rupa (Neperud 7). Atas dasar pandangan ini, dengan hati yang ringan, pendukung posmodernisme bersedia untuk menerima segala hal yang ditolak oleh seni rupa modern.
Karena posmodernisme kemudian diterima secara meluas di kalangan pendidik seni rupa, maka konsekuensinya adalah program pembelajaran yang membuka diri terhadap berbagai tradisi seni rupa, yang pada dasarnya sama dengan pendekatan pendidikan seni rupa multikultural, dianggap sebagai kebutuhan sehingga perlu untuk diimplementasikan. Tidak mengherankan bila Efland, Freedman, dan Stuhr (1996)mengidentifikasi adanya pihak yang menyamakan posmodernisme dengan pendidikan multikultural meskipun menurut mereka, pada kenyataannya tidak dapat dikatakan demikian karena hanya sebagian model pembelajaran yang disebut sebagai pendidikan multikultural yang sejalan dengan gagasan posmodernisme, sebaian yang lain justru tidak sejalan.
2.2 Konsep Dasar
Pendidikan seni rupa multikultural pada dasarnya merupakan sebuah filosofi, gagasan besar, atau pendekatan, di atas mana beragam program pembelajaran dikembangkan. Karena sifat yang demikian ini, maka pendidikan seni rupa multikultural tidak identik dengan satu model program pembelajaran tertentu. Cirinya yang esensil hanyalah pada semangat untuk mempromosikan keragaman budaya melalui kegiatan kesenirupaan.
Keragaman model pembelajaran seni rupa multikultural merupakan cerminan dari keragaman konsep pendidikan multikultural secara umum yang oleh Nieto (1996/1997) digambarkan sebagai serangkaian pilihan model atau strategi pembelajaran dari suatu spektrum yang luas. Spektrum pendidikan multikultural yang diuraikan di atas, secara faktual tercermin dalam kegiatan pendidikan seni rupa multikultural yang dalam tulisan ini dikelompokkan atas tiga model yakni model pengenalan, model pengamalan, dan model perombakan.
2.2.1 Model Pengenalan
Model Pengenalan bertujuan untuk memperkenalkan seni rupa secara teoritis, apresiatif, dan praktis dari berbagai kelompok suku, ras, agama, kelas sosial, jenis kelamin, pandangan, atau kondisi tertentu. Pengenalan ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan murid agar ia dapat memahami “orang lain” dan karya seni rupa yang diciptakannya, yang mungkin saja sangat berbeda dengan keyakinan dan tradisi yang dianut oleh sang murid. Pembelajaran yang dilaksanakan dapat berupa kegiatan kurikuler, atau ekstra kurikuler. Demikian pula, pembelajaran ini dapat diterapkan pada sekolah atau kelas yang bersifat monokultur maupun kelas yang muridnya memiliki latar belakang suku, ras, agama, atau kondisi sosial yang beragam (multietnis/multikultur). Berbagai metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru untuk memperkenalkan seni rupa dengan segala aspeknya dari berbagai kelompok masyarakat ini antara lain ceramah yang dilengkapi dengan media pandang-dengar (foto, slaid, film, atau video), diskusi, praktik studio, studi lapangan, dan sebagainya.
Melihat sifatnya yang sekedar memperkenalkan berbagai dunia seni rupa kepada murid, maka model ini termasuk dalam kategori additive approachnya Banks, inclusion levelnya Gay, tolerance levelnya Nieto, dan single group studiesnya Sleeter dan Grant.
2.2.2. Model Pengamalan
Model pengamalan secara khusus diterapkan pada kelas yang bersifat multikultur. Disebut model pengamalan, karena model ini mengakui adanya keragaman dan berusaha untuk mengamalkan ide “persamaan” dalam keragaman tersebut secara sistemik dan sistematis dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya dirancang sedemikian rupa sehingga setiap murid yang berasal dari berbagai latar belakang suku, ras, agama, kelas sosial, jenis kelamin, pandangan, dan kondisi tertentu, mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Bila pada model pengenalan guru masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tradisional karena ia sekedar memperkenalkan wajah seni rupa dari berbagai latar, maka pada model pengamalan, guru ditantang untuk tidak hanya memperkenalkan keragaman serta “persamaan hak dalam keragaman” yang diperjuangkan oleh kaum multikulturalis, tetapi mengimplementasikan cita-cita tersebut secara nyata di kelas. Di sini, masalah teknis pembelajaran hanyalah faktor sekunder. Faktor primer adalah adanya sikap yang positif dari guru tentang persamaan dalam keragaman yang ditandai oleh semangat untuk mengamalkannya. Untuk itulah, guru perlu mengadakan introspeksi-diri dengan meminjam pertanyaan yang dikemukakan oleh Chalmers (1999), “apa yang saya tahu tentang diri, sikap, dan pemahaman saya mengenai seni rupa, dan apakah saya secara tulus mencoba untuk menjadikan seni rupa relevan dengan setiap murid?”
Model pengamalan ini dapat diidentikkan dengan transformation approachnya Banks, infusion levelnya Gay, acceptance dan respect levelnya Nieto, teaching the culturally different, teaching the human relation, dan teaching the multikultural education approachnya Sleeter dan Grant.
Agar supaya model pengamalan ini dapat terlaksana dengan baik, maka lingkungan sekolah pertama-tama harus dibuat kondusif. Misalnya, tidak adanya perlakuan diskriminatif atas dasar latar belakang murid. Untuk membangun suasana yang non-diskriminatif ini, maka guru dan pegawai yang menjadi fasilitator di sekolah seyogyanya merefleksikan pula keragaman latar belakang murid. Demikian pula dengan kebijakan sekolah, yang tercermin pada aturan dan kurikulum, semuanya mestilah bersifat serba melingkupi sehingga murid merasakan bahwa keyakinan, tradisi keluarga, dan kondisi sosialnya diterima dan dihormati. Jelaslah, bahwa seorang guru seni rupa akan mengalami kesulitan menerapkan model pengamalan ini bila ia tidak didukung oleh segenap komponen sekolah.
Pada model pengamalan, konsep seni rupa yang digunakan sebagai titik tolak dalam merancang kegiatan pembelajaran, adalah konsep yang bersifat terbuka. Artinya, guru harus menggunakan konsep seni rupa sebagaimana seni rupa itu dimaknai dan difungsikan secara beragam. Dalam kehidupan nyata, seni memang memiliki arti dan fungsi yang bervariasi seperti: mengekspresikan perasaan, memperindah sesuatu, menceriterakan pengalaman, mendokumentasikan kejadian, mengeritik, menghibur, memperingati peristiwa, menampilkan simbol budaya, merangsang imajinasi, menghasilkan nilai ekonomis, dan banyak lagi. Dengan demikian, menjadi tantangan bagi guru seni rupa untuk memilih tema pembelajaran yang dapat di ditafsirkan secara bebas oleh murid sesuai dengan pengalaman, tradisi, dan keinginannya masing-masing.
Penerapan model pengamalan ini dalam praktik studio (penciptaan karya seni rupa) dapat dimulai dengan memilih tema penciptaan. Salah satu cara yang disarankan adalah dengan menggali tema dari murid. Dengan demikian tema penciptaan tidak seragam tetapi bervariasi sesuai dengan latar belakang murid seperti tema barongsai, wayang, ondel-ondel, idul-fitri, natal, dan sebagainya. Selain itu, tema dapat dipilih dengan menggali budaya atau karakteristik lokal tempat sebuah sekolah berada. Sekolah yang berada di Jakarta mungkin dapat memilih tema: monas, ondel-ondel, Taman Mini Indonesia, Pasar Seni Ancol, atau Bundaran HI; Sekolah yang berada di Yogyakarta dapat mengangkat tema: andong, Malioboro, alun-alun, keraton, ketoprak, wayang, batik, atau sekaten; Sekolah yang berada di Makassar dapat memilih tema: Pantai Losari, Monumen Mandala, Benteng Ujung Pandang, Tari Pakarena, Tari Ganrang Bulo, dan sebagainya. Tema yang bersifat lokal ini dianggap mampu mengikat secara psikologis karena secara nyata murid hidup di daerah tersebut.
Tema yang telah dipilih kemudian diwujudkan secara visual dengan menggunakan media sesuai dengan keinginan murid. Tidak ada media yang lebih unggul dari media lainnya demikian pula, tidak ada teknik mengolah media yang lebih baik dari teknik lainnya. Pada suatu kegiatan praktik studio dengan tema “barongsai” misalnya, berbagai cara pemisualan dapat dipilih oleh murid seperti media tanah liat dengan teknik butsir, media daun lontar dengan teknik anyaman, media kertas berwarna dengan teknik mosaik, media cat air dengan teknik pengecatan tebal (teknik poster), atau media cat air/kanji dengan teknik finger painting.
Penerapan model pengamalan ini dalam pembelajaran yang bersifat teoritis (estetika, sejarah seni rupa) atau apresiatif (kritik seni rupa) juga harus berpijak pada keragaman seni rupa dengan prinsip bahwa tiap karya seni rupa memiliki makna, dan kriteria keindahannya masing-masing. Dengan perkataan lain, tidak ada standar baku yang berlaku untuk semua. Menjadi tugas guru untuk memperkenalkan makna dan kriteria keindahan dari setiap karya yang dibahas dalam kegiatan pembelajaran. Upaya pengenalan ini dapat dilakukan dengan menginformasikan secara langsung, menyiapkan bahan bacaan, atau menghadirkan orang yang kompeten mengenai masalah yang dibahas. Dengan pemahaman yang baik, maka murid dapat memiliki bekal yang relevan dalam merasakan nilai artistik yang dimiliki oleh sebuah karya seni rupa. “Bekal yang relevan” ini penting oleh karena menurut Kaepler (dalam Chalmers, 1999) seseorang dari kelompok budaya tertentu menanggapi secara berbeda dengan anggota kelompok lainnya terhadap suatu stimulasi yang sama. Atas dasar inilah, Chalmers (1999) menyarankan agar guru jangan merasa berhak untuk memberikan penilaian terhadap suatu karya seni rupa berdasarkan kriteria yang diyakininya oleh karena setiap budaya memiliki definisi dan kriterianya sendiri mengenai apa yang berkualitas dan bermakna. Selanjutnya ia menyarankan pendekatan antropologis dalam kritik seni rupa yang memberikan hak kepada orang yang kompeten (seniman) dari budaya tersebut untuk menafsirkan, memberikan penilaian, dan mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas karyanya.
Keinginan untuk menyajikan bahan pembelajaran yang “serba melingkupi” dalam pendidikan seni rupa multikultural tercermin pada sebagian rumusan tujuan pembelajaran yang dikemukakan oleh Lankford (dalam Chalmers, 1999) seperti: (1) murid mempelajari teori seni rupa yang tradisional dan yang bersifat alternatif; (2) murid mengenal bahwa konsep seni rupa bervariasi di antara berbagai budaya, dan berubah sesuai tuntutan jaman; (3) murid memahami bahwa karya seni rupa dapat dinilai dengan berbagai cara; (4) murid akan mencoba menemukan nilai tentang seni rupa yang dianut dalam keluarganya, temannya, dan masyarakat; (5) murid akan mempelajari nilai individual dan nilai masyarakat yang tercermin pada karya seni rupa; (6) murid akan mempelajari tentang lembaga dan jaringan sosial yang mendukung dan mempengaruhi seni rupa; dan (7) murid akan diperkenalkan berbagai bentuk penajaan (pensponsoran) terhadap seni rupa yang terjadi dalam sejarah dari berbagai budaya.
Dengan pendidikan seni rupa multikultural model pengamalan ini, maka orientasi seorang pendidik seni rupa tampaknya memang harus berubah menjadi lebih terbuka dan akomodatif.
2.2.3 Model Perombakan
Pendidikan seni rupa multikultural model perombakan merasa tidak puas dengan sekedar mengamalkan gagasan keragaman budaya dan sosial oleh karena menurut mereka, kondisi masyarakat saat ini pada dasarnya tidak kondusif karena masih maraknya ketidakadilan atas dasar suku, ras, agama, kondisi sosial, jenis kelamin, atau pandangan yang dianut. Karena adanya ketidakadilan ini, maka pendidik seharusnya mengagendakan perombakan struktur dan pola hidup masyarakat dalam kurikulum dan kegiatan pembelajarannya. Ia tidak seharusnya membiarkan ketidakadilan tersebut oleh karena bila ia melakukan itu, maka kegiatan pembelajaran seni rupa multikultural yang dilakukannya hanyalah bersifat semu. Pendukung pendidikan seni rupa multikultural model perombakan ini tampaknya dapat dikelompokkan sebagai kaum Rekonstruksionis Sosial.
Menurut pendukung model perombakan, budaya bukanlah suatu yang mesti diterima dan tak dapat dirubah, dan karena itu ia perlu ditinjau. Kalantzis dan Cope (dalam Nieto, 1996/1997) menegaskan bahwa, agar efektif, pendidikan multikultural mestilah proaktif dan tidak hanya memikirkan kenikmatan yang ditawarkan oleh keragaman hidup tetapi tetapi juga memberikan perhatian pada isu pokok yang timbul akibat pergesekan antarkelompok yang mungkin akan melahirkan konflik dan rasa sakit.
Stuhr, Petrovich-Mwaniki, dan Wasson (1992) yang menjadi pendukung pendidikan seni rupa multikultural model perombakan ini menegaskan dalam sebuah pernyataannya bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, mereka memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dinamik dan kompleks yang mempengaruhi interaksi manusia yakni kemampuan fisik dan mental, kelas sosial, jender, usia, politik, agama, dan kesukuan. Mereka mencari pendekatan yang lebih demokratik yang memberikan peluang bagi kelompok yang terpinggirkan untuk menyuarakan dirinya dalam proses pendidikan seni rupa, dan menumbuhkan kepekaan semua pihak akan asumsi yang dianggap benar yang melekat pada ideologi yang dominan. Lebih jauh, Stuhr, Petrovich-Mwaniki dan Wasson mengidentifikasi lima langkah utama dalam mengembangkan kurikulum pendidikan seni rupa multikultural sebagai berikut: Langkah pertama adalah guru menganalisis dan memperbaiki sikap negatif yang mereka mungkin miliki terhadap pluralisme sosial dan keragaman suku. Dengan cara ini, mereka akan menciptakan suasana belajar seni rupa multikultural yang kondusif; Langkah kedua adalah guru dan siswa melakukan analisis situasi agar akrab dengan masyarakat; Langkah ketiga, guru dan murid memilih bahan kurikulum yang relevan dan sekaligus menarik; Langkah keempat adalah guru dan murid secara berkolaborasi menyelidiki persoalan yang berkaitan dengan bahan kurikulum yang telah dipilih; Pada langkah yang keempat ini, Stuhr, Petrovich-Mwaniki dan Wasson menyarankan tindakan yang perlu ditempuh yakni mengidentifikasi persoalan sosial yang berkaitan dengan agama, suku, tingkat kehidupan ekonomi, jenis kelamin, usia, dan kemampuan mental serta fisik. Sesudah itu, mengumpul data yang relevan, mengklarifikasikannya, menantang nilai yang dianut siswa, membuat keputusan reflektif lalu mengambil langkah nyata sesuai keputusan: Terakhir, langkah kelima adalah guru melaksanakan program evaluasi baik formatif maupun sumatif.
Pendidikan seni rupa multikultural model perombakan ini tampaknya identik dengan Decision making and Social Action Approachnya Banks, Deconstruction dan Transformation approachnya Gay, Affirmation, Solidarity, dan Critique levelnya Nieto, dan Multicultural and Social Reconstructionistnya Sleeter dan Grant.
Topik Diskusi:
Persoalan dalam Penerapan Pendidikan Seni Multikultural
Harap mempersiapkan diri untuk diskusi dengan topik tersebut di atas!
PENDIDIKAN SENI KONTEKSTUAL
Sofyan Salam
A. Pengantar
Ketika panitia menghubungi saya via SMS (Short Message Service ) menanyakan mengenai topik ceramah yang akan saya sajikan, saya sedang membaca artikel tulisan Kerry Freedman Artistic Development and Curriculum: Sociocultural Learning Consideration. Sebuah pernyataan dalam artikel tersebut menarik perhatian saya, yakni “setiap pembelajaran terkait dengan konteks tertentu.” Secara serta-merta saya mengajukan topik ke panitia: “Pendidikan Seni Kontekstual.” Lewat SMS.
Pernyataan Freedman tersebut bukanlah sesuatu yang baru karena seperti kita ketahui bersama, keterkaitan antara kegiatan pembelajaran dengan aspek ruang dan waktu telah lama menjadi objek kajian. Ketertarikan saya adalah pada bagaimana melihat hubungan antara “esensi pendidikan seni sebagai kegiatan pemberian pengalaman estetik” dengan “konteks sosiokultural[1] yang melingkupinya.” Mudah-mudahan dengan bahasan ini, timbul kesadaran baru yang memungkinkan kita mampu melihat persoalan pendidikan seni yang dihadapi sehari-hari, secara lebih bermakna. Itulah arah tulisan[2] ini.
B. Pendidikan Seni: Antara Esensi dan Konteks
Dijadikannya seni sebagai salah satu mata pelajaran dalam kegiatan pendidikan karena seni menawarkan “sesuatu” yang tidak dapat dipenuhi oleh mata pelajaran lain. Sesuatu tersebut itu adalah “pengalaman estetik.” Pengalaman estetik dianggap penting karena manusia merupakan makhluk estetikus, yakni makhluk yang berkeindahan[3]. Karena pengalaman estetik yang ditawarkannyalah, maka pendidikan seni hadir. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa esensi pendidikan seni terletak pada “pemberian pengalaman estetik[4].” Dalam sejarah perjalanan pendidikan seni, esensi pendidikan seni ini sering mengalami “gangguan” oleh berbagai “hal lain” yang bersumber dari konteks sosiokultural masyarakat. Beberapa di antara “gangguan” yang berdampak kolosal terhadap pelaksanaan pendidikan seni, saya kemukakan berikut ini.
1. Gangguan Kepentingan Ekonomi
Ketika sistem persekolahan diperkenalkan pada awal abad ke-19 di Eropa, pendidikan seni (dalam bentuk pelajaran menggambar dan menyanyi) telah menjadi bagian dari kurikulum. Pelajaran menggambar dan menyanyi telah mentradisi di Eropa sejak lama. Pada masa Yunani Klasik, menggambar dan musik diajarkan bagi anak usia sekolah dasar. Plato, misalnya, melihat pengalaman estetik yang ditawarkan dalam kegiatan seni perlu diberikan. Ia mengatakan bahwa anak harus diajari musik sebelum mata pelajaran yang karena melalui irama dan harmoni kesadaran anak akan menjadi teratur. Selanjutnya ia menegaskan bahwa musik dan puisi dapat membantu anak mendapatkan wawasan tentang susunan harmoni alam. Pentingnya hal ini, juga ditunjukkan oleh Aristoteles yang menempatkan musik, menggambar, dan gimnastik (relevan dengan seni tari) sebagai mata pelajaran yang penting.
Ketika mata pelajaran menggambar dan menyanyi diajarkan di sekolah pada masa awal diperkenalkannya sistem persekolahan, metode pembelajarannya mengikuti tradisi akademi seni yang menekankan pada pelatihan teknis yang ketat.
Perkembangan selanjutnya adalah pelajaran menggambar di sekolah diarahkan untuk kepentingan dunia industri. Disadari oleh pengambil kebijakan publik bahwa
sekolah potensil untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi. Di Inggris, Australia, Swedia, Belanda, dan Amerika Serikat, praktik pengajaran menggambar yang mengarahkan peserta didik untuk memeroleh keterampilan yang relevan dengan tuntutan industri, merupakan hal yang umum (Kauppinen x). Bahkan, di Negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat, pemilik modal berhasil memengaruhi para legislator sehingga lahirlah undang-undang yang mewajibkan diajarkannya menggambar bagi anak laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas yang bermukim di kota yang berpenduduk lebih dari 10.000. Untuk memperkuat program ini, pada tahun 1871, seorang pakar menggambar untuk kepentingan industri (industrial drawing) dari Inggris diundang ke Amerika (Eisner dan Ecker, 1966).
Di Indonesia, pendidikan seni untuk keperluan ekonomi sangat nyata pada masa penjajahan Belanda melalui pemberian pelajaran kerajinan tangan (batik, anyaman, gerabah, dll) bagi anak-anak pribumi. Program yang dikelola oleh OEN (Onderwijs, Eeredients en Nijverheid/Pendidikan, keagamaan, dan industri) ini menghasilkan produk yang dikirim ke benua Eropa. Karena kemudian disadari bahwa aspek industri dan perdagangannya lebih penting, maka kemudian pengelolaannya diserahkan ke LNH (Landbow, Nijverheid en Handel/Pertanian, industri, dan perdagangan). Dalam konteks yang demikian ini, dapatlah dipastikan bahwa pelajaran yang diberikan berlangsung dalam semangat memicu peningkatan mutu industri yang akan membawa kemajuan ekonomi. Metode pembelajaran serta penilaian hasil belajar tentu saja berkiblat pada kepentingan ekonomi tersebut. Pemberian pengalaman estetik, tentu saja terganggu oleh ambisi kepentingan ekonomi ini.
2. Gangguan Ide Penanaman Kesadaran Budaya
Pergaulan antar bangsa, suku, atau kelompok memicu tumbuhnya kesadaran akan perlunya suatu bangsa, suku, atau kelompok membangun identitas dirinya. Salah satu media yang dipandang efektif untuk itu adalah seni. Maka pendidikan seni pun dituntut untuk “memberikan jasa” bagi keperluan promosi identitas diri tersebut.
Di Jepang, yang sejak masa Restorasi Meiji menerapkan tradisi menggambar ala Barat di sekolah, timbul keinginan untuk menanamkan pada diri murid rasa kebanggaan pada budaya tradisional Jepang. Cara yang ditempuh adalah dengan memperkenalkan teknik seni rupa tradisional Jepang di sekolah misalnya dengan menggunakan kuas, dan bukannya pensil, dalam menggambar. Perlunya murid memelajari seni rupa tradisional Jepang kembali ditekankan pada masa Perang Dunia II. Menurut Masuda ( 1992, 102) pada Shotoka Zuga, buku teks pelajaran menggambar untuk sekolah dasar, ditegaskan bahwa guru harus menanamkan kepada murid akan kehebatan tradisi Jepang.
Di Cina, seni rupa tradisional seperti seni kaligrafi dan seni lukis juga menjadi bagian penting dari program pendidikan di sekolah dengan fokus kegiatan pada pengenalan teknik tradisional Cina sebagaimana yang diterapkan oleh para seniman. Misalnya, bagaimana memegang dan menggoreskan kuas, cara duduk yang tepat, cara mencampur tinta, dan sebagainya. Teknik tradisional Cina ini diajarkan secara ketat dan murid tidak dibiarkan untuk bereksperimen sendiri. Tujuannya adalah untuk menanamkan pada diri anak rasa memiliki budaya leluhur yang mereka agungkan. Tentang hal ini, Hutt (1987, 43) menulis:” ... karya seniman Cina dari masa lalu amat dihargai dan lukisannya dianggap berisi esensi tradisi, dan karena itu dianggap penting untuk memelajari dan menyalinnya...”
Di Indonesia, upaya membangun kesadaran budaya melalui pendidikan seni telah dilakukan sejak masa kolonial. Hal ini dilakukan oleh tokoh pendidik yang aktif memerjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh pendidik pejuang ini menyadari bahwa sistem persekolahan kolonial tidak kondusif bagi penanaman rasa kebanggaan terhadap budaya sendiri. Oleh karena itu, mereka mendirikan sekolah swasta dengan filosofi yang berbeda. Dua di antara sekolah tersebut adalah Taman Siswa dan Indonesische-Nederlansche School (INS).
Taman Siswa didirikan oleh R.M. Soewadi Soerjaningrat yang populer dengan nama Ki Hadjar Dewantoro. Ki Hadjar Dewantoro diasingkan di Belanda selama enam tahun karena mempropogandakan kemerdekaan Indonesia. Ketika ia kembali ke Indonesia, ia mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922. Ia amat dipengaruhi oleh pemikiran Rabindranath Tagore tentang pendidikan nasional. Di Taman Siswa, kegiatan menggambar termasuk dalam kurikulum dan dianggap sebagai program yang penting untuk menanamkan kesadaran budaya murid.
Indonesische-Nederlandsche School (INS) didirikan oleh Moh. Sjafei di Kajutanam, Sumatera Barat. Ia mengeritik sistem persekolahan kolonial yang tidak peduli pada upaya pengembangan kepribadian anak. Motto pendidikannya adalah “Kepala, hati, dan tangan.” Di INS, menurut Surjomihardjo (1978,284-286) kegiatan menggambar tidak hanya ditekankan pada aspek keterampilan, tetapi juga pada aspek pengembangan pribadi anak. Sebagai bentuk penghargaan kepada anak, karya-karya mereka dipajang pada majalah dinding sekolah.
Setelah Indonesia merdeka, ide penanaman kesadaran budaya menjadi hal penting dari kebijakan kebudayaan pemerintah sebagaimana yang tercermin pada Konstitusi Republik Indonesia. Pada Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Implikasinya dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan seni, adalah kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada penumbuhan kesadaran budaya Indonesia. Implikasi ini tentu saja dapat dipandang sebagai bentuk “gangguan” bagi upaya pemberian pengalaman estetik bagi peserta didik.
3. Gangguan Modernisme
Istilah modern dimunculkan dalam bidang sosiologi pada abad ke-19 untuk menandai perbedaan “masa sekarang” dari “masa sebelumnya.” Karena itu, pada kata modern melekat makna “baru, mutakhir.” Selanjutnya, modernisme memiliki arti pandangan yang menekankan pentingnya kebaruan atau kemutakhiran. Tidak mengherankan bila modernisme dalam seni menomorsatukan kekreatifan sebagaimana yang terlihat pada karya-karya seni modern yang mulai semarak kemunculannya di penghujung abad ke-19.
Ide tentang “pentingnya kekreatifan” kemudian merasuk ke dalam pendidikan seni, sejalan dengan merasuknya gagasan baru dari dunia pendidikan. Studi tentang psikologi anak dan juga psikologi jiwa-dalam menyadarkan pendidik bahwa anak perlu diberi kebebasan untuk mengaktualisasikan dirinya. Salah satu media pengaktualisasian diri tersebut adalah seni. Frank Cizek, seorang seniman dan pendidik seni rupa dari Austria, merupakan orang yang pertama kali mengakui secara terbuka nilai intrinsik karya seni rupa anak (Efland; 1990, 195). Cizek yakin bahwa karya seni rupa anak adalah karya seni yang hanya mampu dihasilkan oleh anak. Untuk itu, karya anak semestinya dibiarkan tumbuh bagaikan bunga tanpa pengaruh orang dewasa (Macdonald; 1970, 341- 342). Ide bahwa anak seharusnya dibebaskan dari pengaruh orang dewasa dalam kegiatan penciptaan karya seni rupa agar dapat mengaktualisasikan dirinya, kemudian populer dengan istilah “pendekatan ekspresi-bebas” atau “pendekatan berbasis-anak.” Dengan pendekatan ini, “kebebasan” dan “kekreatifan” menjadi panglima. Bahkan, disebutkan bahwa metode adalah racun.
Pendekatan ekspresi-bebas kemudian dipromosikan secara luas oleh oleh dua orang tokoh pendidik seni rupa yang dikenal dalam dunia internasional yakni Herbert Read dari Inggris dan Viktor Lowenfeld dari Amerika Serikat. Herbert Read, dalam bukunya Education Through Art menegaskan bahwa ekspresi-bebas tak dapat diajarkan dan peranan guru hanyalah pendamping dan pemberi inspirasi. Viktor Lowenfeld dalam Creative and Mental Growth menekankan bahwa seni rupa bagi anak adalah media untuk menyatakan diri. Ide pendekatan ekspresi bebas yang mulai diperkenalkan oleh Cizek pada awal abad ke-20 kemudian menjadi populer di seluruh dunia, khususnya setelah Perang Dunia II (Kauppinen ; 1995, x-xi).
Di Indonesia, pendekatan ekspresi bebas ini mendapat sambutan hangat yang meluas terutama pada dekade tujuhpuluhan. Penulis yang pada masa itu berstatus mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa IKIP Ujung Pandang (program sarjana muda) dan IKIP Yogyakarta (program sarjana), secara jelas sekali menyaksikan kegegapgempitaan sambutan ini. Kreativitas dan ekspresi bebas menjadi sang primadona, sementara menggambar mencontoh yang sebelumnya populer dipandang sebagai najis. Hingga saat ini, pendekatan ekspresi bebas masih begitu melekat di hati para pendidik seni di Indonesia.
Perkembangan selanjutnya, di Barat, pendekatan ekspresi bebas mulai menuai kritikan yang tajam karena ternyata telah menjadikan pemberian pengalaman estetik yang merupakan esensi pendidikan seni terabaikan. Hal ini disebabkan karena praktik pendidikan seni hanya berfungsi sebagai ajang bagi peserta didik untuk bermain-main. Greer dan Silverman (1987/1988; 11) membandingkan antara pelaksanaan pendidikan seni rupa dengan pendidikan bidang studi lain di sekolah dasar sebagai berikut:
Mata pelajaran di sekolah dasar umumnya diajarkan secara konsisten, berkelanjutan, dan peduli pada materi pelajaran; dan guru mendorong anak untuk mempelajarinya secara sungguh-sungguh. Tetapi untuk mata pelajaran seni rupa, bila itu ada, biasanya digunakan sebagai kegiatan selingan dari mata pelajaran yang menuntut keseriusan. Guru pun tidak begitu peduli untuk mengembangkan pemahaman dan apresiasi anak terhadap dunia seni rupa.
Jelaslah, bahwa pendidikan seni yang demikian ini tidak memberikan pengalaman estetik yang bermakna karena dikalahkan oleh keinginan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik. Kritikan yang lebih tajam menuding pendekatan ekspresi bebas sebagai pendekatan yang bersifat “anti-estetik. ” Alasannya adalah: demi menyalurkan emosi anak melalui seni secara bebas, kualitas artistik karya anak tidak lagi dipedulikan. Artinya, pendekatan ekspresi bebas telah “mengganggu” dengan serius esensi pendidikan seni.
4. Gangguan Tuntutan Akuntabilitas
Ketika Uni Soviet meluncurkan pesawat Sputniknya ke ruang angkasa pada akhir tahun 1950 an, pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat panik. Mereka merasa kalah langkah dari pesaing utamanya itu. Mereka lalu bertanya pada dirinya “what is wrong with us?”, What is wrong with our education?” Suasana batin yang sedang galau itulah yang mendorong bangsa Amerika Serikat untuk memeriksa sistem pendidikan mereka. Hasil pemeriksaan itu berujung pada satu rekomendasi: pendidikan harus berkualitas. Agar pendidikan yang berkualitas tersebut dapat dipantau, maka cara yang memungkinkan pemantauan itu pun kemudian dikembangkan. Dipilihlah “Pendekatan Sistem” sebagai jalan keluar. Pendekatan sistem merupakan cara sistematis untuk mengembangkan kurikulum, baik pada tingkatan makro maupun mikro. Karena kesuksesannya di sekolah tentara saat pertama kali digunakan, pendekatan sistem segera dilirik oleh kalangan pemerintah untuk diterapkan pula di sekolah (Herschbach 3). Pada tingkat mikro (unit pembelajaran), pendekatan ini memandang proses pembelajaran sebagai sebuah sistem yang utuh yang terdiri atas komponen tujuan, strategi, dan evaluasi, yang harus diorganisasi secara logis dan harmonis (Dick dan Carey 2-10). Karena menuntut perencanaan yang cermat dan sistematis, maka pendekatan ini disebut sebagai “disain instruksional.” Pada disain instruksional, tujuan instruksional menjadi dasar dalam memilih dan memilah strategi dan materi pembelajaran serta menyusun alat evaluasi (Tyler 3).
Pendidikan seni yang sedang asyik dengan “ekspresi bebas” terperangah dengan sistem ini. Banyak di antara pendidik seni yang serta-merta menolak penerapan pendekatan sistem ini. Alasannya, dengan memilah-milahkan kegiatan penciptaan seni menjadi pokok bahasan atau sub-pokok bahasan yang mengacu pada tujuan yang spesifik dan teramati, serta dikaitkan dengan prosedur evaluasi yang mengikat sebagaimana yang dituntut oleh disain instruksional, akan menghilangkan jiwa dari proses penciptaan seni.
Di Indonesia, disain instruksional populer dengan istilah PPSI yang diperkenalkan secara resmi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung Kurikulum 1975. Sejak itu, guru diwajibkan untuk menggunakan sistem PPSI dalam mengembangkan rencana pembelajaran (SP) yang akan dilaksanakannya. Sejak itu pulalah, pendekatan kompetensi diterapkan secara resmi di Indonesia.[5] Pendidik seni secara otomatis mengadopsi pula sistem ini.
Dengan kewajiban menggunakan pendekatan sistem, pendidik seni di Indonesia dituntut untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akuntabel yakni yang dapat ditelusuri seberapa jauh pernyataan yang dirumuskan pada Tujuan Instrusional khusus, menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran, dan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, guru pertama-tama harus menyiapkan SP yang sistematis, cermat, dan lengkap, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Beberapa orang pengamat pendidikan seni memandang kegiatan pembuatan SP yang demikian ini sebagai “gangguan” bagi guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator dalam pemberian pengalaman estetik bagi peserta-didik. Gangguan ini berupa banyaknya waktu pendidik yang tersita untuk pembuatan SP, dan karakteristik SP yang dapat mematikan seni mengajar karena menurut Leeds, kegiatan pembelajaran seni adalah sebuah “proses kehidupan” yang tak mudah diatur-atur.
5. Gangguan Ide Keberagaman
Ide keberagaman merupakan inti dari “pendidikan multikultural” yang oleh Bullivant (dalam Davidman, 1996/1997: 67) didefinisikan sebagai: “…to teach about the many social groups and their different designs for living in a pluralistic society.” (untuk mengajarkan tentang banyak kelompok sosial dan perbedaan cara hidupnya di dalam masyarakat yang pluralistik). Definisi tersebut di atas, berpijak pada pengertian budaya yang dianut oleh Bullivant sebagai “… a social group’s design for survival in and adaptation to its environment.” ( Cara suatu kelompok sosial untuk mempertahankan diri dan beradaptasi dengan lingkungannya). Definisi ini oleh Davidman dikritik karena dipandang terlalu sempit dan lembut. Pendidikan multikultural menurut Davidman merupakan hasil perjuangan yang berdarah-darah terhadap ketidak adilan ekonomi, rasial, dan jender. Itulah sebabnya ia lebih menyetujui definisi pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Banks yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah “ an educational reform movement that is concerned with increasing educational equity for a range of cultural and ethnic groups” (Gerakan reformasi pendidikan yang memberikan perhatian kepada peningkatan kesamaan dalam bidang pendidikan terhadap beragam kelompok budaya dan sosial) (dalam Davidman, 1996/1997:68).
Perbedaan dalam mendefinisikan pendidikan multikultural di atas merupakan cerminan dari keragaman wajah pendidikan multikultural itu sendiri. Ada kelompok pendidik yang dalam upayanya mempromosikan keragaman budaya dan sosial merasa puas dengan hanya sekadar memperkenalkan budaya “lain.” Sementara kelompok lain merasa tidak cukup dengan hanya memperkenalkannya saja tetapi mengamalkannya secara nyata dalam suatu lingkungan yang dirancang untuk itu. Kelompok yang lain lagi merasa bahwa ketidakkondusifan iklim keberagaman yang ada saat ini mestilah dirombak melalui kegiatan reformasi masyarakat. Untuk itu, kegiatan merombak masyarakat merupakan agenda yang harus hadir dalam pendidikan multikultural. Tidak mengherankan bila pendidikan multikultural sangat sarat dengan muatan politik.
Pendidikan multikultural mendapatkan lahan yang subur dalam pendidikan seni. Seperti halnya dengan pada pendidikan multikultural secara umum, pendidikan seni multikultural tampil dalam wajah yang beragam dan sarat dengan agenda politik. Bahkan, ada tokoh pendidikan seni multikultural secara terang-terangan mengemukakan bahwa guru seyogyanya menjadi provokator dalam kegiatan pembelajaran untuk memanas-manasi peserta didik agar mereka bersedia mengambil bagian dalam upaya mereformasi masyarakat. Dalam keadaan seperti inilah, gangguan terhadap pemberian pengalaman estetik kepada peserta didik tidak dapat dihindari.
Di Indonesia, pendidikan seni multikultural masih lebih banyak diperbincangkan dari pada dipraktikkan. Kalau pun dipraktikkan, masih terbatas pada pendidikan multikultural yang sekadar memperkenalkan seni budaya “orang lain.” Pendidik yang berperan sebagai provokator untuk mereformasi masyarakat relatif tak terdengar. Karena itu, gangguannya terhadap pemberian pengalaman estetik masih terbatas, kalau ada.
C. Penutup
Uraian di atas mempertegas apa yang telah dituliskan oleh Kerry Freedman bahwa setiap pembelajaran terkait dengan konteks sosiokultural. Tak ada kegiatan pembelajaran yang tanpa konteks. Dalam keadaan tertentu, konteks tersebut mengancam esensi pendidikan seni sebagai kegiatan pemberian pengalaman estetik. Pendidik seni perlu menyadari hal ini agar tidak “terbuai” oleh konteks yang biasanya hadir dalam wajah yang berbunga-bunga. Semoga.
Referensi
Davidman, Leonard. 1996/1997. “Multicultural Education: A Movement in
Search of Meaning and Positive Connections.” Multicultural Education. Editor Fred Schultz. Guilford, Connecticut: Dushkin.
Dick, Walter dan Lou Carey. 1985. The Systematic Design of Instruction.
Glenview: Scot.
Efland, Arthur D. 1990. A History of Art Education. New York dan London:
Teachers College.
Eisner, Elliot W.1997. Educating Artistic Vision. Reston, VA: The NAEA.
Eisner, Elliot W dan David W. Ecker. 1966. Readings in Art Education. Waltham,
Massachusetts; Toronto, dan London: Blaisdell.
Freedman, Kerry.1997. “Artistic Development and Curriculum: Sociocultural Learning
Considerations.” Kindler, Anna M. (ed). Child Development in Art. Reston, VA:
NAEA.
Greer, Dwaine dan Silverman, Ron. H. 1987/1988. “Making Art Important for Every
Child” Educational Leadership. Vol 45 No. 4. Hal. 10-16.
Herschbach, Dennis R. “Technology and Efficiency: Competencies as
Content.” Journal ofTechnology Education. Volume 3 No.2 . Online. 30 Juni 2004.
Hutt, Julia. 1987. Understanding Far Eastern Art. Oxford: Phaidon.
Kauppinen, Heta. 1995. “Introduction.” Trends in Art Education from Diverse Cultures.
Editor Heta Kauppinen dan Read Diket. Reton, VA: NAEA.
Leeds, Jo Alice. “Teaching and The Reasons for Making Art.” Art Education. (1986):17-21
Lowenfeld, Viktor dan W. Lambert Brittain. 1982. Creative and Mental Growth. New York:
Macmillan, 1982.
Macdonald, Stuart. 1970. The History and Philosophy of Art Education. New York:
American Elsevier.
Mager, Robert F. 1984. Preparing Instructional Objectives. Belmont: David S.
Lake.
Masuda, Kingo. “The Transition of Teaching Methods in in Japanese Art Textbooks.”
The History of Art Education: Proceedings from the Second Penn State Conference
Ed. Patricia M Amburgy, dkk. Reston, VA: NAEA,1992. 98-103.
Read, Herbert. 1974 Education Through Art. New York: Pantheon Books.
Surjomihardjo, Abdurrahman. 1978. “National Education in A Colonial Society.” Dynamic of Indonesian History. Ed. Haryati Soebadyo dan Carine A du Marchie Sarvaas.
Amsterdam: North Holland, 277-306.
Tyler, Ralph W. 1949. Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago
dan London: The University of Chicago Press.
Winner, Ellen. 1992. “How Can Chinese Children Draw So Well.” Aesthetic Education. 45 (1).
Lampiran
PENDIDIKAN ESTETIK[6]
Istilah aesthetic, dipopulerkan oleh Baumgarten pada pertengahan abad ke-18 untuk menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan keindahan. Hingga sekarang ini, makna tersebut masih bertahan. Sesuatu yang estetik bermakna sesuatu yang indah. Karena seni secara tradisional dihubungkan dengan keindahan, maka seni pun berkaitan erat dengan istilah estetik. Ringkasnya seni bersifat estetik.
Tetapi, istilah estetik memiliki makna lain yang secara gampang dipahami jika kita menelusuri kata yang merupakan lawannya yakni anaesthetic (ingat istilah kedokteran, anestesia). Anaesthetic berfungsi menghilangkan rasa. Dengan demikian, sebaliknya hal atau peristiwa yang estetik berfungsi menimbulkan rasa. Jadi, cakupan maknanya menjadi meluas karena tidak hanya berkaitan dengan rasa keindahan saja tetapi segala perasaan. Jika kita mengamati hasil karya seniman kreatif dewasa ini, tidak sulit untuk menemukan karya yang menurut pandangan yang lazim tak lagi indah. Atas dasar itulah, filosof Suzanne Langer memandang seni sebagai media untuk mengungkapkan perasaan. Perasaan yang diungkapkan tidaklah harus identik dengan keindahan meskipun keindahan itu dapat dihayati sebagai perasaan yang bersifat khusus.
Perbedaan makna estetik di atas bukanlah sekedar perbedaan filosofis, tetapi lebih jauh perbedaan tersebut memiliki dampak praktis. Jika istilah estetik atau pendidikan estetik hanya dibatasi pada hal yang bersifat indah saja, maka segala objek atau hal yang tak indah menurut cita rasa tradisional otomatis tersingkirkan dari pendidikan estetik. Sebaliknya, jika estetik mengacu pada beragam bentuk perasaan yang dialami dalam kehidupan, maka segala jenis pendidikan pada dasarnya merupakan pendidikan estetik. Karena semua peserta didik mengalami perasaan tertentu dalam hubungannya dengan bidang ilmu yang dipelajari, maka sifat dan kualitas perasaannya tampaknya mempengaruhi kesenangannya terhadap subjek tersebut.
Meskipun demikian, kualifikasi perlu dibuat tentang hubungan antara pengalaman estetik dengan pengalaman merasakan. Jika semua pengalaman merasakan adalah pengalaman estetik, maka pengalaman estetik kehilangan sifatnya yang khas. Padahal, sesungguhnya pengalaman estetik merupakan suatu pengalaman yang khas dan unik yang ditandai dengan terpuaskannya “hasrat akan sesuatu yang harmoni dan lengkap.” Kepuasan ini lahir dari proses keterlibatan batin, baik dalam proses kreasi maupun dalam kegiatan persepsi.
Ada hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam kita memahami istilah pendidikan estetik yakni perbedaan makna kata estetik (aesthetic) sebagai sesuatu yang berkaitan dengan perasaan dengan makna kata estetika (aesthetics) yang bermakna cabang filsafat yang membahas pemahaman tentang hakikat seni. Bila peserta didik diajarkan estetika, maka peserta didik digiring untuk mengeksplorasi beragam ide filosofis tentang seni. Tentu saja sebagai kegiatan eksploratif, ia dapat pula menawarkan pengalaman estetik.
Meskipun seni secara alamiah merangsang timbulnya pengalaman estetik, pengalaman estetik sebagaimana yang ditegaskan oleh John Dewey, dapat muncul dalam semua bidang yang digeluti manusia. Memecahkan persoalan matematika, berkebun, menemukan teori baru, atau melukis dapat menjadi sumber pengalaman estetik.Dengan perspektif yang luas tentang sumber pengalaman estetik ini, maka seyogyanya pemberian pengalaman estetik menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Pandangan semacam ini menjadi dasar pijakan Herbert Read, seorang filosof Inggris, yang mengajukan tesis bahwa semestinya pendidikan bertujuan untuk mencetak seniman. Istilah “mencetak seniman” yang dikemukakan oleh Herbert Read tersebut bermakna proses pendidikan seyogyanya mengembangkan potensi peserta didik untuk menciptakan sesuatu yang indah dan memberi kepuasan. Sesuatu yang diciptakan itu dapat berwujud ide atau karya, dapat bersifat teoretis maupun praktis. Orang yang mampu menciptakan sesuatu yang indah dan memuaskan pastilah merupakan orang yang terampil, sensitif, dan penuh imajinasi. Karena itu ia layak disebut seniman.
Implikasi dari pandangan Herbert Read sangat mendasar. Bila diikuti dengan serius, maka pendidik akan menilai keberhasilan peserta didik pada keartistikan, daya imajinasi, dan koherensi karya yang diciptakannya. Lebih jauh, guru yang menganut pandangan Herbert Read akan mengembangkan kurikulum yang mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang menghargai keorisinalan, tidak hanya dalam bidang seni, tetapi juga dalam matematika, sejarah, ilmu pengetahuan alam, atau olah raga. Pendidikan estetik berdasarkan pandangan Herbert Read mencakupi keseluruhan program sekolah.
John Dewey menganut pandangan tentang estetik yang tidak berada jauh dari pandangan Herbert Read. John Dewey tidak setuju adanya perbedaan antara seni dengan estetik meskipun ia mengakui bahwa istilah seni biasanya merujuk pada penciptaan karya, sedang estetik ditekankan pada aspek persepsi. Dewey meyakini bahwa persepsi yang orisinal pada dasarnya merupakan kegiatan kreasi. Atas dasar itulah, ia menolak perbedaan yang tegas antara estetik dengan artistik. Lebih jauh, pengalaman dalam bentuk seni menurut Dewey merupakan pengalaman yang paling menyenangkan secara intrinsik.
Dewey tidak membatasi seni pada bidang-bidang khusus seperti seni lukis, seni patung, seni grafis dan sebagainya meskipun dalam tulisannya ia meyakini bahwa seni memberi perhatian khusus pada pengalaman yang menyenangkan tersebut. Pengalaman yang menyenangkan dapat pula diperoleh melalui matematika atau ilmu pengetahuan alam. Kesenangan yang intrinsik yang dicapai melalui proses eksplorasi merupakan kebajikan pendidikan yang utama.
Konsepsi tentang apa yang penting dari sudut pendidikan ini tidak selaras dengan praktik pemberian rangsangan atau motivasi kepada peserta didik dengan iming-iming yang tak memiliki hubungan secara intrinsik dengan apa yang kepada peserta didik diminta untuk diperbuat.
Konsepsi tentang pengalaman estetik yang telah diuraikan di atas belum juga menjadi topik diskusi yang penting dalam bidang pengajaran, kurikulum, atau persekolahan. Pendidikan seni dan estetik merupakan istilah yang tak begitu populer di kalangan pendidik. Hanya segelintir pakar yang menjadikan pendidikan estetik atau filsafat seni sebagai pusat perhatian kajiannya.
Makna yang ketiga dari istilah estetik perlu pula mendapatkan perhatian. Makna ini berkaitan dengan bagaimana karya seni khususnya, dan hal yang dapat dicerap di alam ini pada umumnya, memengaruhi pikiran dan memperluas wawasan kita. Pada kesempatan ini saya akan memokuskan pembicaraan pada karya seni rupa.
Karya seni rupa, sebagaimana yang dikatakan oleh baik filosof maupun psikolog yang tertarik pada hal yang bersifat estetik, bukanlah sekadar objek atau peristiwa yang dimaksudkan untuk menyenangkan hati. Karya seni rupa merupakan simbol yang menghadirkan dunia di hadapan kita secara khas. Kursi, misalnya, sebagaimana dikatakan oleh Arnheim, bukan hanya merupakan objek tempat kita duduk, tetapi menyandang suatu makna. Kursi di ruang tunggu berbeda dengan kursi yang diperuntukkan khusus untuk Paus. Keduanya merupakan tempat duduk tetapi masing-masing menghadirkan makna kehidupan yang berbeda. Persepsi terhadap objek semacam itu, tidak hanya berkaitan dengan fungsi praktis tetapi juga nilai dan karakteristik budaya dari mana objek tersebut dibuat. Lebih jauh, perupa yang menciptakan bentuk yang dapat merangsang kesadaran kita akan berbagai aspek visual alam ini membantu kita untuk melihat sesuatu secara segar dan unik yang pada akhirnya akan memperkaya pengamatan kita. Dengan menghayati karya patung Rodin misalnya, kita akan menjadi semakin peka terhadap lekukan otot tubuh manusia.
Kesadaran terhadap lingkungan merupakan salah satu fungsi seni. Fungsi lainnya yang tak kalah pentingnya adalah kapasitas karya seni – novel, lukisan, bangunan, puisi, lakon, dan komposisi musik- untuk menimbulkan rasa empati kita terhadap kehidupan orang lain. Dengan membaca novel tentang Holocaust karya Elie Weisel (1969) kita dapat merasakan horror yang diderita oleh orang yang menjadi korban holocaust. Dengan membaca Grapes of Wrath karya Steinbeck, kita akan memiliki pemahaman yang mendalam akan makna kemiskinan. Pendeknya, seni dan media estetik memungkinkan kita untuk menghayati perasaan orang lain sehingga kita lebih memahami dunia secara lebih bermakna. Sebuah deskripsi statistik tentang penyalahgunaan narkoba di daerah miskin yang padat penduduk di kota besar dapat memberikan kita informasi statistik yang bermanfaat. Tetapi deskripsi semacam itu tidak mampu membangun pemahaman yang menggugah rasa empati kita terhadap kondisi kehidupan dan perjuangan untuk bertahan hidup dari para korban narkoba tersebut. Kita akan sulit memahami penyebab keadaan tersebut kecuali kita mampu menumbuhkan rasa empati kita secara mendalam.
Dengan pertimbangan tersebut, betapa besar potensi pendidikan estetik dalam bidang pengajaran ilmu sosial. Epstein, misalnya, menunjukkan bahwa perbudakan dapat dipahami secara lebih meluas dari pada apa yang dapat diberikan oleh buku teks jika peserta didik diberi peluang untuk menyimak musik para budak, mendengarkan ceritera dan mitosnya, mengecap makanannya, membaca novel pada periode tersebut atau menyaksikan video Roots. Tiap karya seni atau sistem simbol memberikan kepada peserta didik asses ke masa lalu yang tak mampu diberikan oleh buku teks pada umumnya (Makassar, 16 April 2006, Sofyan Salam).
[1] Tentu saja saya hanya akan memilih beberapa konteks sosiokultural saja dan melupakan yang lainnya karena keterbatasan ruang dan waktu.
[2] Tulisan, yang diniatkan sebagai hand out ini, merupakan ramuan dari berbagai tulisan yang pernah saya hasilkan. Dengan demikian beberapa bagian dari tulisan ini bukanlah tulisan yang orisinal.
[5] Disebut demikian, karena “kompetensi peserta didik” yang secara operasional dirumuskan dalam tujuan instruksional khusus menjadi acuan kegiatan pembelajaran dan penilaian. Istilah KBK yang digunakan untuk Kurikulum 2004 sesungguhnya hanyalah sekedar nama untuk menarik perhatian, seolah-olah ada hal yang baru. Padahal tidaklah demikian.
[6] Pendidikan Estetik, disarikan secara bebas oleh Sofyan Salam dari: Elliot W. Eisner, “Aesthetic Education,” yang dimuat dalam Marvin C. alkin dkk (ed) 1992. Encyclopedia of Educational research. New York: Macmillan Library reference USA.
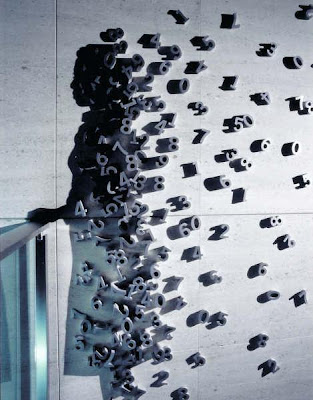
Komentar
Posting Komentar